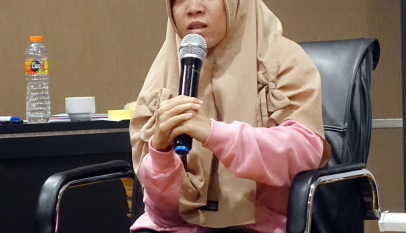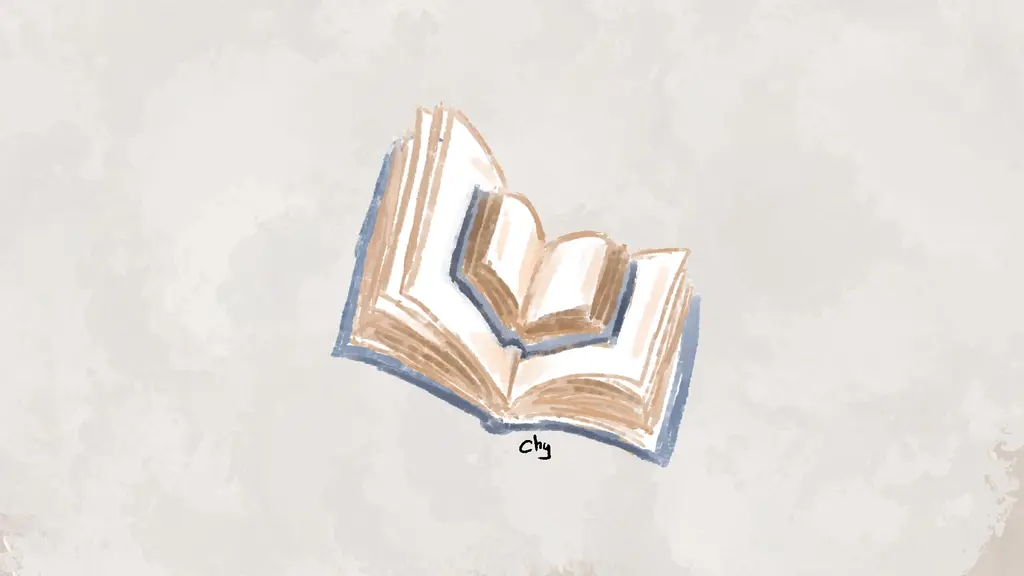Salah Kaprah Radikalisasi lewat Game Online
Oleh Pradipa P Rasidi Antropolog Digital, Project Officer Technology and Violence Program, Monash University Indonesia
Artikel ini dimuat di Kompas.id pada 19 November 2025.
Wacana pembatasan game online atau gim daring perlu dicermati dengan hati-hati. Jika tidak, regulasi ini hanya akan dilandasi kepanikan moral dan cara pandang yang menggurui. Selama ini, percakapan publik terpaku pada aspek permukaan, yaitu apakah suatu gim mengandung kekerasan, senjata, atau darah. Padahal bermain gim daring adalah sebuah tindakan sosial. Artinya, ia dibentuk oleh praktik bermain gim dan ekosistem yang tumbuh di luar gim itu sendiri.
Penelitian ilmiah sejauh ini tidak menemukan konsensus bahwa gim memicu kekerasan. Literatur tentang kekerasan menunjukkan bahwa tindakan agresif harus dipupuk dalam rentang waktu panjang. Salah satu studi paling komprehensif dari Massey University (Drummond et al, 2020) menganalisis 28 riset longitudinal tentang dampak gim bermuatan kekerasan, seperti game action dan shooter, mencakup lebih dari 21.000 anak dan riset dari 2008 hingga 2019. Temuannya jelas, yaitu tidak ada hubungan sebab-akibat antara gim kekerasan dan peningkatan kekerasan anak.
Studi lebih baru (Lacko et al, 2024) mengonfirmasi hal yang sama. Hasil risetnya menunjukkan bahwa paparan terhadap gim bermuatan kekerasan tidak mengurangi empati maupun perilaku prososial anak.
Kekhawatiran publik sering berangkat dari asumsi bahwa anak tidak dapat membedakan fantasi dan realitas saat bermain gim kekerasan. Namun, riset Martarelli et al (2015) menunjukkan bahwa kebingungan ini umumnya hanya terjadi pada anak usia prasekolah. Pada dasarnya, mereka pun belum memiliki kemampuan kognitif maupun motorik untuk memainkan gim dengan intensitas gameplay tinggi.
Dengan demikian, fokus pada elemen kekerasan semata justru terlalu dangkal. Ada tiga hal lain yang jauh lebih penting diperhatikan.
Pertama adalah elemen yang justru tidak berkaitan langsung dengan kekerasan, yaitu bagaimana pemain berkompetisi dengan pemain lain? Banyak gim daring kini menjual barang dalam gim (in-game item) yang bisa dibeli dengan uang sungguhan agar meningkatkan kemampuan karakter atau mendapat perlengkapan eksklusif.
Gim seperti ini dikenal sebagai pay-for-convenience atau pay-to-win. Sistem ini kerap dilengkapi sistem lootbox: alih-alih membeli barangnya langsung, pemain membeli kotak hadiah berisi barang acak—bisa dapat yang bagus, bisa dapat yang jelek, tak ubahnya judi.
Negara seperti Belgia, misalnya, sudah meregulasi gim dengan lootbox karena dianggap membahayakan anak. Bukan karena sisi kekerasan dalam gimnya, melainkan karena sistem ini justru menjadi elemen non-kekerasan yang dapat meningkatkan agresifitas anak ketika bermain.
Kedua, penting untuk bicara mengenai genre dan imajinasi. Tidak semua gim kekerasan memiliki derajat pencerapan dunia yang sama. Genre arena shooter seperti PUBG atau Fortnite memberi jarak yang jelas antara pemain dan dunia fiksinya. Senjatanya bisa jadi realistis, tetapi kostumnya konyol, seperti helm panci di kepala, piyama kelinci, atau kostum beruang. Kekerasan di sana terbaca sebagai fantasi. Mereka sekadar menciptakan arena bermain.
Lain halnya dengan military shooter seperti Call of Duty: Modern Warfare atau Operation Flashpoint. Yang mereka tunjukkan bukan sekadar kekerasan, melainkan sebuah imajinasi geopolitis tentang kekerasan. Ada bendera negara, seragam militer, dan demarkasi moral-ideologis. Di Modern Warfare, kita bermain sebagai tentara Amerika di Timur Tengah dan menumpas orang-orang Arab yang digambarkan sebagai teroris. Di Operation Flashpoint kita menghabisi ”setan” komunis Rusia.
Masalahnya bukan pada darah atau adegan perangnya, melainkan pada cara gim ini mengasah imajinasi moral. Siapa yang dianggap ”musuh”, siapa yang ”pahlawan”? Bagaimana pemain diseret masuk ke dalam logika kawan dan lawan yang politis? Hal serupa muncul dalam gim laga berlatar Perang Salib, seakan peristiwa tersebut hanya dipahami sebagai sejarah penaklukan yang penuh darah.
Tentunya, sekadar membayangkan siapa kawan dan lawan tidak cukup menjadi dorongan kekerasan. Dan karena itulah, poin ketiga yang harus diperhatikan adalah ekosistem atau komunitas moral yang dibangun di luar gim. Gim daring tidak pernah dimainkan dalam ruang vakum. Anak muda membangun komunitas, identitas, dan pertemanan.
Hal tersebut dilakukan salah satunya melalui peladen Discord, semacam aplikasi percakapan yang diorientasikan untuk bermain gim. Setiap pengguna bisa membuat peladennya sendiri, seperti grup percakapan Whatsapp. Dan ada peladen-peladen yang tumbuh besar karena kesamaan minat dan hobi menjadi sebuah forum diskusi.
Percakapan dalam komunitas inilah yang dapat menjadi titik masuk radikalisasi, bukan melalui gimnya. Di ruang ini pemain membicarakan pertanyaan seperti: ”Ancaman mana yang paling nyata?” ”Bagaimana kita bisa menumpas mereka sebelum kita yang ditumpas?” ”Siapa dalang di balik ini semua?”
Mereka membicarakan bukan hanya gim, melainkan juga berita aktual dan pertanyaan mengenai identitas ketika bertemu atau membayangkan orang berbeda, ”dalang di balik layar”, ”penguasa”, dan lain sebagainya. Radikalisasi bisa dipupuk, baik oleh aktor dengan niat buruk maupun terjadi dengan sendirinya seraya anak bergulat dengan pertanyaan mengenai posisinya di dunia.
Dan dalam ekosistem ini, Discord bukan satu-satunya. Streamer di Youtube, pemengaruh, grup Telegram—semuanya berperan dalam radikalisasi.
Karena itulah, gim harus dipahami sebagai bagian dari praktik bermedia anak muda. Ia hanyalah salah satu dari banyak modalitas untuk membangun identitas, belajar berinteraksi, dan mencari ruang aman di antara teman sebaya.
Fokus berlebihan pada tampilan kekerasan justru mengaburkan pertanyaan paling mendasar: mengapa anak bermain gim itu? Apa hubungan sosial yang dibangun? Apa makna gim tersebut bagi mereka? Label seperti ”kecanduan gim” sering kali muncul dari ketidakpahaman dan kecurigaan, bukan dari pembacaan jujur terhadap pengalaman anak.
Sudah waktunya publik berhenti mengatur anak dari jauh dan mulai mendengar mereka. Pendekatan seperti ini tidak pernah menyentuh akar masalah. Alih-alih, publik perlu memahami makna gim bagi anak dan menciptakan ruang diskusi tentang imajinasi yang muncul dari gim. Permainan daring bukan pengganti orangtua, melainkan bagian dari dunia anak yang membutuhkan pemahaman bersama, bukan pelarangan.
Di sinilah lantas peran penting pemerintah. Pahamilah pemain gim sebelum mengambil kebijakan, bahkan libatkanlah mereka dalam pengambilan kebijakan. Di Malaysia, direksi penanggulangan terorismenya bahkan sudah dikepalai oleh seorang gamer. Pemerintah tidak bisa hanya merespons kejadian secara reaksioner. Mulailah mengakui anak dan gamer—dan warga secara lebih luas—sebagai subjek yang otonom, bukan obyek pengaturan.