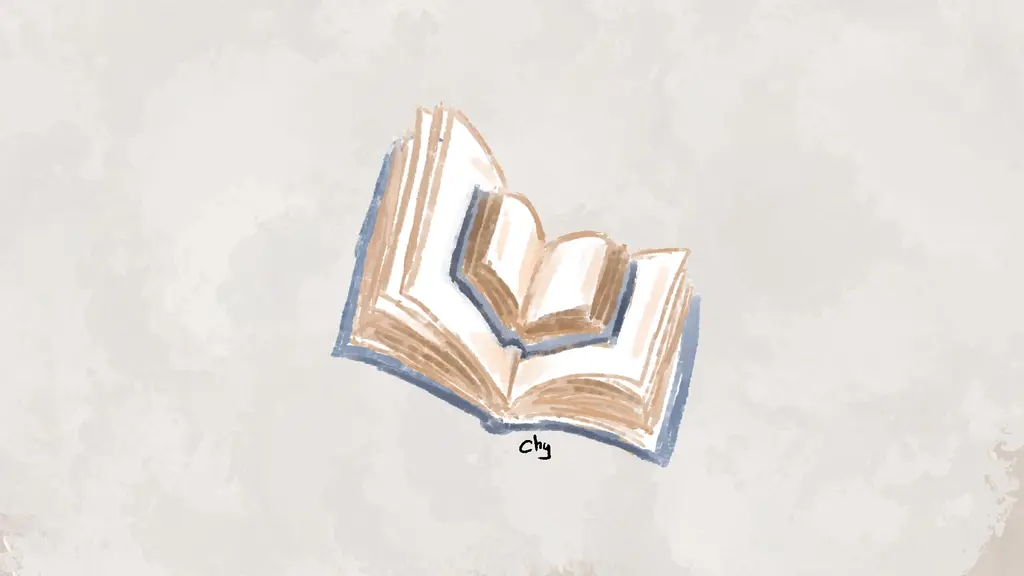Mendukung Korban Terorisme yang Terabaikan
Oleh Heru Susetyo/Jakarta
Serangan teror terjadi di seluruh belahan dunia, yang terbaru di Selandia Baru pada 15 Maret dan di Sri Lanka pada 21 April, menewaskan ratusan korban. Namun, penegakan hukum serta perhatian publik sebagian besar tertuju pada pelaku, bukan para korban terorisme.
Tentu saja orang ingin tahu siapa penjahatnya -dengan risiko si pelaku akan mendapatkan publisitas. Contoh paling mengerikan adalah serangan atas dua masjid di Christchurch, Selandia Baru yang menewaskan 50 orang dan melukai banyak lainnya. Perdana Menteri Jacinda Ardern dengan tepat menolak menyebutkan nama pelaku yang memfilmkan kejahatannya serta membagikannya secara langsung (live streaming).
Jauh lebih sedikit, orang yang terus peduli kepada para korban dan penyintas, meskipun jumlah korban jiwa di Sri Lanka mencapai lebih dari 200 orang, belum lagi mereka yang terluka parah; semua mata hanya terfokus pada pelaku, kelompok Islamic State atau siapa pun yang mengaku bertanggung jawab atas serangan teror itu.
Demikian juga di Indonesia, lebih sedikit orang yang mengingat kondisi para korban pemboman gereja di Surabaya tahun lalu pada 13 dan 14 Mei 2018, ledakan di Jl. Thamrin, Jakarta pada 2016 dan kantor polisi di Pekanbaru tahun lalu, dll.
Selain korban langsung, ada juga korban sekunder, korban tidak langsung dan orang-orang yang berpotensi menjadi korban terorisme. Korban sekunder terorisme adalah keluarga terdekat atau keturunan dari korban langsung aksi teror. Korban tidak langsung adalah mereka yang telah menderita luka parah fisik atau psikologis sebagai akibat tidak langsung dari aksi terorisme, menurut sebuah laporan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) tahun 2015.
Korban kejahatan, termasuk terorisme, seharusnya tidak menjadi sasaran viktimisasi sekunder yang biasanya terjadi bukan sebagai akibat langsung dari tindakan kriminal yang menyebabkan kerugian bagi korban, tetapi melalui respons dari institusi dan individu terhadap korban.
Fase-fase berbeda terjadi pascaserangan teroris, sebagaimana ditulis oleh Josie Cm Netten dan Maarten Van Donk tahun lalu dalam sebuah artikel tentang upaya meningkatkan ketahanan korban serangan teroris. Pertama, fase dampak; insiden dramatis terjadi, menimbulkan malapetaka, kematian, kehancuran, dan kehilangan. Para korban dan masyarakat bingung dan mengalami shock berat.
Kedua, fase bulan madu, yang dimulai beberapa hari setelah kejadian mengerikan tersebut dan berlangsung tiga hingga enam bulan. Bantuan diberikan, peringatan berlangsung, berbagai komunitas dan otoritas menyalurkan bantuan spontan besar-besaran, bersamaan dengan banyaknya perhatian media, dan kedermawanan banyak pihak. Banyak dukungan sosial dimobilisasi dan tersedia.
Yang ketiga adalah fase kekecewaan (disillusion), ketika serangan teroris tidak lagi menjadi fokus perhatian. Masyarakat kembali ke rutinitas hariannya. Berita lain lebih menarik perhatian. Yang keempat adalah fase reintegrasi. Pembangunan kembali individu-individu dan masyarakat terdampak mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun, fase pemulihan jangka panjang.
Sesaat setelah kejadian terorisme, seperti dilaporkan oleh PBB, “Para korban terorisme terus berjuang agar suara mereka didengar, kebutuhannya didukung dan hak-haknya ditegakkan.”
“Para korban sering merasa terlupakan dan terabaikan sesaat setelah serangan teroris memudar, yang bisa memunculkan konsekuensi-konsekuensi besar bagi mereka,” ungkap PBB tahun lalu dalam penerimaannya atas Hari Internasional untuk Mengenang dan Menghormati Korban Terorisme setiap 21 Agustus. Saat rutinitas harian kembali, para korban sering kali kehilangan harapan, kebencian, kegetiran dan persepsi ditinggalkan sendirian. Tidak ada lagi perasaan tentang komunitas bersama. Fase ini sering disebut sebagai “bencana kedua” atau “bencana setelah bencana”. Periode ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun, sebagaimana dikonfirmasi oleh riset-riset di atas.
Sebagai contoh, berapa banyak dari kita yang masih ingat penyintas dari Bom Bali tahun 2002, pemboman Hotel JW Marriott tahun 2003, pemboman Kedutaan Besar Australia di Jakarta tahun 2004, pemboman Hotel JW Marriott kedua dan pemboman Hotel Ritz Carlton di Jakarta tahun 2009?
Sebagian besar dari kita tidak tahu kondisi mereka saat ini, nasib keluarga atau pun apakah mereka masih hidup, bagaimana mereka menangani pekerjaan, karir, dan kesehatan mereka setelah kejadian tersebut.
Peneliti Supriyadi Widodo Eddyono menulis pada tahun 2016, menurut data yang disediakan oleh Yayasan Penyintas Indonesia (YPI), di antara 544 korban terorisme, tidak ada satu pun yang telah menerima kompensasi dari Negara. Juga, setelah serangan Thamrin 2016, tanggung jawab untuk pembiayaan perawatan medis bagi para korban masih tidak jelas dan tidak terkoordinasi dengan baik.
Karena itu, tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana cara untuk memberikan dukungan bagi para korban terorisme yang terabaikan dan bagaimana mencegah mereka agar tidak mengalami viktimisasi sekunder.
Tanggung jawab utama untuk mendukung korban terorisme dan menegakkan hak-hak mereka berada di tangan negara. Masyarakat termasuk sektor swasta, media, lembaga pendidikan dan komunitas serta keluarga juga berbagi tanggung jawab terkait dengan korban langsung dan tidak langsung. Negara harus memberikan bantuan medis dengan segera serta dukungan psikologis jangka panjang bagi para korban, di samping kompensasi yang mudah diakses.
Negara harus mengembangkan strategi, kebijakan, dan perundang-undangan pemerintah untuk menyediakan respons yang memadai guna mendukung para korban terorisme dalam kerangka peradilan pidana. Negara juga harus menangani kebutuhan para korban dan keluarga mereka segera setelah serangan teroris terjadi, seperti yang dikutip sebuah laporan UNODC pada tahun 2017.
Lebih lanjut, negara harus memastikan bahwa para profesional pendukung korban direkrut dan ditugaskan untuk mendampingi para korban pada tahap awal penyelidikan kasus terorisme, guna memberi tahu mereka tentang semua layanan dukungan yang tersedia dan mengidentifikasi kebutuhan mereka.
Semua profesional yang berurusan dengan korban harus menerima pelatihan spesifik sensitivitas korban terkait dengan kebutuhan korban, strategi untuk menangani mereka secara tepat serta kebutuhan untuk mencegah terjadinya viktimisasi sekunder.
Media massa juga harus menghormati hak-hak korban terorisme dan mematuhi kode etik dalam meliput korban terorisme. Jangan biarkan media, termasuk media sosial, membuat korban menjadi terkorbankan lagi dengan mengeksploitasi penderitaan para korban, misalnya dengan terus-menerus mewawancara dan mengekspos keluarga korban secara berlebihan setelah serangan teroris terjadi.
Yang terakhir, korban terorisme lintas batas harus diperhitungkan. Misalnya, ada warga negara Indonesia di antara para korban serangan teroris 9/11 tahun 2001 di Amerika Serikat dan serangan Chrischruch tahun ini.
Perawatan korban terorisme harus selalu dalam fase bulan madu, bukan pada fase kekecewaan. Dan, harus ada keseimbangan antara perhatian yang diberikan kepada pelaku dan kepada korban.
Penulis adalah associate professor di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), dan anggota dewan eksekutif Victim Support Asia.
Tulisan ini diterjemahkan dari sebuah artikel di The Jakarta Post edisi Jumat, 14 Juni 2019. [SWD, WR]