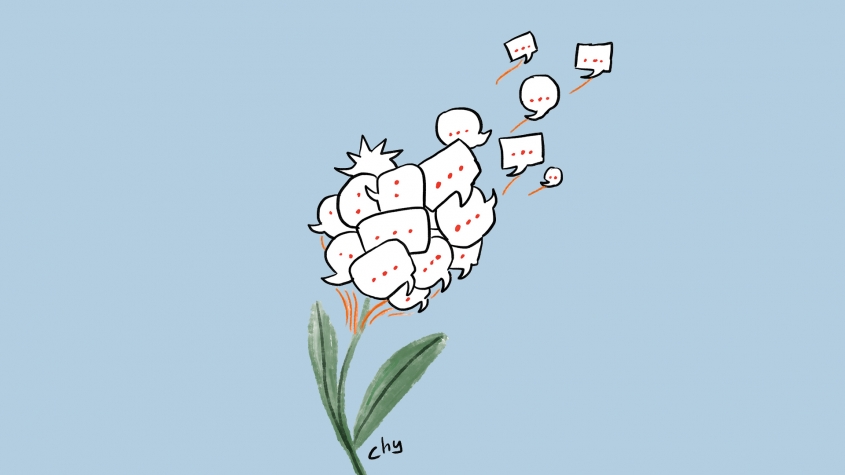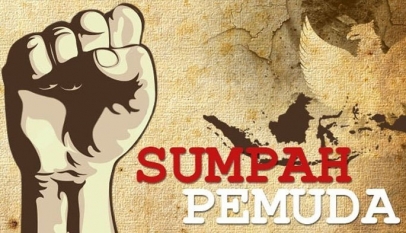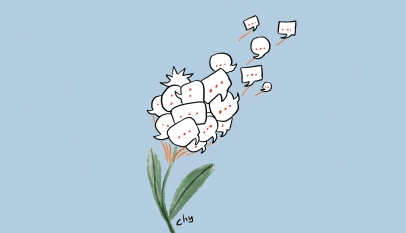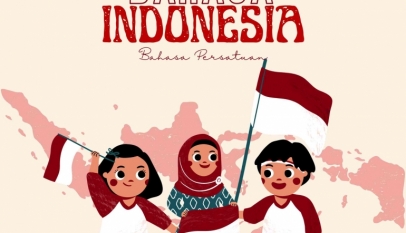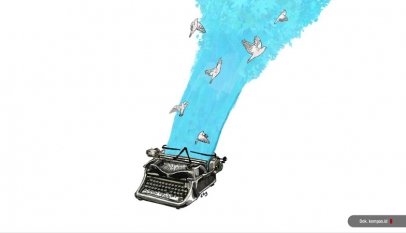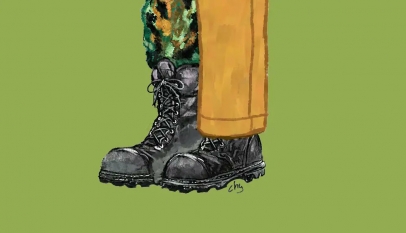Bahasa Indonesia Mendunia, Bahasa Nusantara Tetap Terjaga
Oleh Waliyadin, Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Mahasiswa PhD di University of Canberra, Australia
Artikel ini dimuat di Kompas.id, 27 Oktober 2025
Setelah diakui sebagai salah satu bahasa resmi oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) pada November 2023, bahasa Indonesia akan mulai digunakan dalam sidang umum UNESCO pada 1 November 2025. Hal itu tentu menjadi kabar baik dan penanda kiprah bahasa Indonesia di kancah internasional.
Namun, bahasa Indonesia yang saat ini menjadi bahasa nasional dan dikenal sebagai bahasa pemersatu bangsa memiliki sejarah yang panjang dan unik. Keberhasilan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dianggap sebagai suatu keajaiban, miraculous success (Woolard 2000); sukses besar a great success” (Bukhari 1996: 19) dan fenomena linguistik yang spektakuler, perhaps even the most spectacular linguistic phenomenon of our age (Alisjahbana 1962: 1).
Bahasa Indonesia mulanya adalah bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perdagangan (Paauw, 2009; Sneddon, 2003). Puncaknya adalah ketika bahasa ini dipilih sebagai bahasa pemersatu; pada 28 Oktober 1928 bahasa Indonesia dikumandangkan sebagai salah satu isi sumpah pemuda: ”Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”.
Catatan sejarawan menunjukkan beberapa alasannya. Misalnya, Jared Diamond (2019) menjelaskan alasan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dan kini bahasa nasional. Menurut dia, bahasa Jawa sebenarnya menjadi bahasa yang paling banyak digunakan oleh kurang dari sepertiga populasi Indonesia ketika itu dan dikenal sebagai bahasa elit politik dan sosial, the language of the political and social elite (Holmes dan Wilson, 2022, hlm: 148). Sehingga muncul kekhawatiran akan adanya dominasi Jawa, sebagaimana saat ini juga masih dikhawatirkan berbagai pihak.
Selain itu, bahasa Jawa juga memiliki hierarki atau dalam sosiolinguistik bahasa Jawa dikenal memiliki sistem penanda kesopanan yang kompleks (Holmes dan Wilson, 2022). Saat Anda berbicara dengan orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi, kosakata yang digunakan berbeda ketika berbicara dengan orang dengan status sosial biasa atau yang lebih rendah.
Sebaliknya, bahasa Melayu relatif lebih mudah untuk dipelajari (Paauw, 2009). Hanya sekitar 18 tahun setelah Indonesia menduduki Papua Niugini yang saat itu masih diduduki Belanda, saat ini masih banyak ditemui orang Papua Niugini di daerah pedalaman yang bisa berbahasa Indonesia (Diamond, 2019).
Faktor lain, tata bahasa Indonesia lebih sederhana dan supel dengan menambah awalan atau akhiran pada kata dasarnya menjadikan bahasa Indonesia mudah dipelajari. Misalnya kata bersih (kata sifat) ditambah awalan me- dan akhiran -an menjadi membersihkan (kata kerja). Dibandingkan dengan bahasa Inggris, misalnya, ada 16 bentuk waktu dan banyak juga kata kerja tidak beraturan yang tetap harus dihafalkan. Adapun dalam bahasa Indonesia kata kerja tidak mengenal bentuk waktu seperti dalam bahasa Inggris.
Bahasa Indonesia yang saat ini menjadi bahasa nasional juga diakui sebagai bahasa yang secara ekonomi bermanfaat atau economically useful (Clarke dan Morgan, 2011). Dengan demikian, bahasa ini juga mulai diminati di beberapa negara, seperti Australia. Bahasa Indonesia banyak diminati warga Australia yang akan bekerja di bagian diplomasi. Hal ini beralasan karena Indonesia dan Australia adalah negara di kawasan Asia Pasifik yang menjalin kerja sama ekonomi maupun pertahanan. Dengan demikian, menguasai bahasa Indonesia menjadi keharusan bagi calon diplomat yang akan ditempatkan di Indonesia.
Tidak hanya soal kepentingan ekonomi dan hubungan diplomasi, ada juga warga Australia yang menikah dengan orang Indonesia sehingga mereka perlu belajar bahasa Indonesia. Ada juga yang belajar bahasa Indonesia sekadar untuk keperluan berwisata ke Indonesia, terutama ke Bali.
Meskipun demikian, internasionalisasi bahasa Indonesia masih mengalami berbagai tantangan. Pertama bahasa Indonesia belum menjadi bahasa pengantar dalam interaksi antarnegara karena kekurangan kekuatan politik dan keterbatasan pengaruh budaya dan saintifik (Zein, 2022).
Saat ini, bahasa internasional yang utama adalah bahasa Inggris. Tidak heran memang karena bahasa Inggris berkembang lewat kolonisasi serta diperkuat dengan dominasi ekonomi Amerika Serikat. Adapun bahasa Indonesia tidak memiliki sejarah kolonisasi yang masif selain ketika Indonesia mengambil alih Papua Niugini yang saat itu masih dikuasai Belanda (Diamond, 2019).
Bahasa Indonesia akan mengglobal jika Indonesia mampu berperan dalam kancah global, baik dalam bidang ekonomi maupun penyebaran ilmu pengetahuan. Saat ini, kondisi di dalam negeri, para ilmuwan lebih memilih untuk menggunakan bahasa Inggris untuk diseminasi ilmu pengetahuan yang artinya orang Indonesia sendiri kurang percaya diri dengan bahasanya sendiri.
Namun, saya tidak mengatakan bahwa mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris adalah satu hal yang harus dihindari. Saya ingin mengatakan bahwa seharusnya kita tetap bangga dengan bahasa Indonesia dengan menggunakannya sesuai dengan tempat dan waktunya. Ketika berada dalam forum-forum masyarakat Indonesia, kita usahakan untuk bangga menggunakannya secara paripurna.
Ketika berada pada lingkungan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan bahasa Indonesia, alternatifnya adalah dengan mencampurkan dengan bahasa lain (code mixing). Dengan begitu, bahasa Indonesia akan berbaur dengan bahasa asing lainnya. Melalui pembauran itulah, ada kemungkinan bahasa Indonesia akan beralih menjadi bahasa yang mengglobal.
Dalam sidang umum UNESCO ada baiknya jika kita perkenalkan bahasa Indonesia campuran dari pada bahasa Indonesia terstandar. Selain karena bahasa Indonesia terstandar akan terasa sangat asing di dunia internasional, kita bisa menunjukkan bahwa bahasa Indonesia selain supel, juga bisa berbaur dengan bahasa lain. Nyatanya, kosakata bahasa Indonesia juga banyak menyerap dari bahasa asing, seperti Arab, Belanda, dan Inggris.
Internasionalisasi bahasa Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah tidak hanya bagi Balai Bahasa, tetapi juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, ilmuwan dan peneliti perlu mencantumkan bahasa Indonesia dalam publikasinya, paling tidak pada bagian abstraknya. Beberapa jurnal Sinta—jurnal Kemendiktisaintek—memang sudah memulai dengan mencantumkan abstrak dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada abstraknya.
Lebih dari itu, ketika mengirim ke jurnal internasional, para ilmuwan Indonesia bisa juga memilih jurnal yang ramah terhadap penggunaan bahasa Indonesia untuk dicantumkan paling tidak untuk bagian abstraknya. Dengan begitu, para ilmuwan juga ikut terlibat dalam diseminasi bahasa Indonesia dalam karya ilmiah di jurnal internasional. Para ilmuwan China dan Hong Kong, misalnya, sudah masif dalam penerbitan karya ilmiah di jurnal internasional dengan abstrak menggunakan bahasa China.
Selain ilmuwan, diaspora Indonesia juga bisa turut terlibat dalam penyebaran bahasa Indonesia di negara mereka saat ini bertempat tinggal; misalnya, melalui promosi kebudayaan dan bahasa Indonesia dalam festival multikultural yang sering diadakan di sejumlah negara. Saat ini, saya pun yang tengah studi S-3 berkesempatan untuk menjadi pengajar bahasa Indonesia untuk warga Australia yang akan ditugaskan di Indonesia sebagai diplomat. Atau warga Australia yang ingin belajar bahasa Indonesia untuk menambah penguasaan bahasa asing selain bahasa pertama mereka (i.e. bahasa Inggris).
Namun, internasionalisasi bahasa Indonesia tidak harus berarti mengabaikan keragaman linguistik di dalam negeri. Wacana menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional sering kali menafikan realitas superglossia Indonesia, yakni situasi berbagai bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa global saling bersaing dalam ranah komunikasi (Zein, 2022). Dalam konteks ini, perencanaan bahasa nasional tidak cukup berfokus pada peningkatan status bahasa Indonesia semata, tetapi juga perlu melindungi dan menguatkan bahasa-bahasa daerah yang terancam punah. Anderbeck (2015) memperingatkan bahwa hampir separuh dari 707 bahasa yang masih hidup di Indonesia dapat punah dalam dua dekade mendatang jika tidak segera dilestarikan.
Superglossia Indonesia juga menuntut pengakuan terhadap Regional Lingua Franca, yakni bahasa-bahasa penghubung di tingkat lokal, seperti Melayu Papua, Melayu Manado, Bakumpai, atau Ngaju, yang berfungsi vital dalam interaksi sosial, perdagangan, dan budaya. Pengakuan terhadap variasi linguistik ini penting untuk membangun kebijakan bahasa yang lebih adil dan inklusif. Dalam konteks ini, kekuasaan dan politik kebahasaan seharusnya dijalankan dengan perspektif superdiversity (Quinn, 2012; Sze et al, 2015), yakni menghargai dinamika, agama, dan identitas penutur bahasa di seluruh wilayah Nusantara.