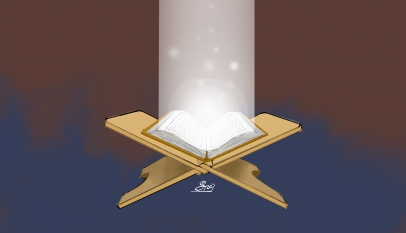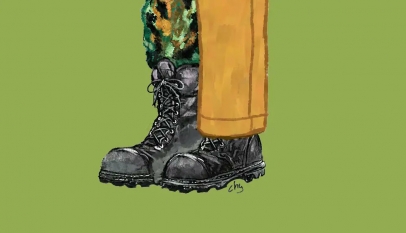Transformasi Pesantren dalam Pembangunan Peradaban
Oleh M Zainuddin, Guru Besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Artikel ini terbit di harian Kompas.id, 21 Oktober 2025
Tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional oleh Presiden RI Joko Widodo yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015.
Ketetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa para santri memiliki peran besar dalam pembangunan bangsa, termasuk usaha memerdekakan Republik ini. Ketetapan tersebut bertepatan dengan deklarasi Resolusi Jihad yang dimotori pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari, dan puluhan kiai se Jawa-Madura di Surabaya pada 22 Oktober 1945 saat itu.
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 juga menetapkan Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, setelah ditetapkan Hari Santri Nasional tersebut. Demikian juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan perpres yang mengatur dana abadi pesantren. Ini tentu menjadi energi bagi pesantren sebagai lembaga pendidikan tentang pembangunan akhlak (revolusi mental) dan moderasi beragama yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Ulama, kiai, pesantren
Sofistikasi sains dan teknologi di era internet of things (IoT) serta budaya modern telah membuat banyak kalangan dan pemerintah khawatir akan berpengaruh fatal terhadap kehidupan manusia dan bahkan semua spesies yang ada di Bumi ini. Ketika perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat semakin terasa dampaknya, tuntutan terhadap peran agama semakin besar. Sementara itu, kepergian ulama satu demi satu terus bertambah dan belum muncul penggantinya yang signifikan, maka pada gilirannya tuntutan terhadap ulama pun tak kalah besarnya, sebab merekalah sebagai penerus (perjuangan) Nabi (warasat al-anbiya).
Secara sosiologis, predikat keulamaan memang lebih banyak disandangkan kepada para kiai daripada para sarjana pada umumnya. Bahkan tidak sedikit para sarjana—meski mereka kompeten di bidang studi keislaman—mereka hampir tidak pernah menyandang gelar ini (kecuali sarjana yang berbasis pesantren). Hal itu mudah dipahami, sebab sebutan ulama secara kultural sudah amat melekat dalam diri para kiai yang memiliki kontribusi besar dalam perjuangan bangsa, utamanya kiai yang ada di pesantren yang memiliki karisma dan kekuatan spiritual.
Jadi, ini persoalan kultur yang sudah membentuk dalam masyarakat kita. Selain itu, memang kiai telah memiliki kontribusi besar dalam mencerdaskan anak-anak bangsa, terutama di bidang pembentukan karakter dan ketahanan mental. Dan begitulah memang predikat ulama itu lebih banyak terkait dengan sikap moral, selain kedalaman ilmu. Dalam Al Quran sendiri ditegaskan bahwa yang taat kepada Allah adalah ulama (QS Fathir: 28).
Pola pendidikan pesantren
Pesantren, sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia, memiliki kontribusi besar dalam pengembangan kepribadian, antara lain, adanya perhatian besar kiai terhadap santri, rasa hormat dan tawadu santri terhadap kiai, hidup sederhana, hemat dan mandiri, kesetiakawanan, saling menolong, disiplin, serta tahan uji. Dalam kehidupan pesantren terlihat leburnya individualisme dan egoisme.
Apalagi jika dikaitkan dengan peluang kerja, pesantren tidak akan khawatir dengan peluang kerja bagi para santrinya, sebab pesantren memang tidak menjanjikan kerja (promise of job). Namun, lulusannya justru banyak yang mendapatkan pekerjaan dan bahkan menciptakan tenaga kerja. Tujuan pendidikan pesantren yang asasi adalah mencetak generasi berilmu dan berkarakter. Dua entitas ilmu dan karakter tersebut harus dimiliki oleh seorang santri untuk diakui keberadaannya.
Sistem pendidikan pesantren hingga saat ini masih diakui sebagai yang terbaik, karena tiga hal. Pertama, pola pendidikan live in (tinggal di ma’had) selama masa pendidikan (24 jam). Kedua, adanya kurikulum yang tersembunyi (hidden curriculum) dari para kiai dan ustaz yang menjadi role model bagi para santrinya. Ketiga, tradisi santri yang memiliki sikap dan karakter yang excellent, yaitu tawadu, ulet, dan mandiri. Sikap-sikap tersebut menjadi kebutuhan yang sangat didambakan di era modern seperti sekarang ini. Maka, lulusan pesantren pada umumnya juga tidak kenal menganggur karena dengan modal soft skill-nya mereka bisa bekerja di hampir semua sektor, meski terkadang missmatch dengan keilmuannya. Inilah kelebihan santri.
Tentang pentingnya pendidikan mental atau karakter ini, temuan psikolog Reuven Bar-On menjelaskan, IQ manusia rata-rata hanya berpengaruh 6-20 persen dalam menentukan keberhasilan, sementara 80-90 persennya lebih ditentukan oleh attitude (karakter). Sementara itu, Institut Teknologi Carnegie memaparkan, dari 10.000 orang sukses, 15 persennya sukses karena kemampuan teknis dan 85 persennya karena faktor-faktor kepribadian (karakter). Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Dr Albert Edward Wiggam yang menghasilkan temuan bahwa dari 4.000 orang yang kehilangan pekerjaan, adalah 400 orang (10 persen) karena kemampuan teknis dan 3.600 orang (90 persen) karena faktor kepribadian (karakter).
Ini relevan dengan sifat yang ada pada diri Nabi yang dimulai dari kejujuran (shiddiq), tepercaya (amanah), komunikatif (tabligh), baru smart (fathanah). Dan beliau pun menegaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang terbaik kepribadiannya (ahsanuhum khuluqa).
Oleh sebab itu, dalam era modern yang menurut Alvin Toffler ditandai dengan budaya impersonal dan ketergantungan teknologi ini, maka tradisi pesantren yang mandiri, ulet, dan tahan uji harus tetap dipertahankan. Misalnya, jika menurut penelitian Clifford Geertz, santri yang bekerja mengabdi (ngawulo) kepada kiai dengan memasak, mencuci, dan menggarap tanah untuk memperoleh berkahnya, apakah di era internet of things ini masih ada? Paling tidak, nilai-nilai itulah yang mesti dipertahankan.
Selain itu, pendidikan di pesantren juga bersifat inklusif dan tidak membatasi usia santri. Siapa pun boleh dan bebas belajar (nyantri) di pesantren, termasuk yang tidak memiliki ijazah dan biaya hidupnya. Karena para kiai memiliki tanggung jawab dan perhatian besar terhadap keberlangsungan pendidikan anak bangsa. Inilah sejatinya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM).
Tradisi pendidikan khas pesantren ini yang kemudian juga menginspirasi para pengelola pendidikan di beberapa madrasah/sekolah dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) saat ini untuk menyelenggarakan program ma’had (boarding school) yang memadukan intelektual dan spiritual seperti yang sudah berlangsung lama diterapkan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan ma’had jami’ah-nya.
Pesantren dan NKRI
Indonesia yang menjadi role model bagi bangsa lain merupakan negara majemuk yang memiliki persatuan dan kesatuan yang sangat kuat hingga sekarang. Hal ini karena Indonesia memiliki enam pilar perekat bangsa. Pertama, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (agama), Indonesia merupakan negara yang penduduknya sangat religius, yang memiliki enam agama yang diakui oleh negara dan merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar dunia. Kedua, falsafah negara dan konstitusi (Pancasila dan UUD 1945). Ketiga, keutuhan wilayah negara (NKRI). Keempat, bahasa persatuan (bahasa Indonesia). Kelima, budaya Nusantara dan kearifan lokal. Keenam, keberadaan militer yang merupakan tulang punggung penjaga wilayah NKRI.
Santri memiliki peran besar dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peran sosial-kemasyarakatan, lembaga pendidikan pesantren membimbing masyarakat dengan mempertimbangkan maqashid syari’ah, yakni mashlahah (kebaikan dan harmoni hidup bersama). Dalam peran kenegaraan, santri membebaskan negeri dari segala bentuk penjajahan dan penindasan dengan kokoh memegang komitmen demi perkembangan dunia yang terus berubah. Dalam peran reformasi, santri turut serta mengawal pemerintahan, melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Peran lain yang tak kalah pentingnya dari masa ke masa adalah, pertama, pada era pra-Kemerdekaan, yaitu fase embrio lahirnya pesantren dimulai zaman Wali Sanga, sekitar abad 15-16. Kehidupan para santri sejak pra-Kemerdekaan selalu berhadapan dengan masalah eksistensi bangsa. Masalah tersebut, di antaranya, adalah perlawanan santri menghadapi penjajah di Sumatera Barat (1821-1828), Perang Jawa (1825-1830), perlawanan di barat laut Jawa pada 1840 dan 1880, serta Perang Aceh pada 1873-1903. Sementara di Jawa Barat, ada Perang Kedongdong (1808-1819). Perang yang terjadi di Cirebon ini melibatkan ribuan santri dalam pertempurannya.
Kedua, era Kemerdekaan, di mana para ulama dan santri berperan untuk menggalang kekuatan dalam rangka merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Paling tidak sejarah ”Resolusi Jihad” pada Oktober 1945 menjadi bukti kontribusi nyata kaum santri dalam merebut kemerdekaan. Kita juga diingatkan sejarah bagaimana dahulu Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah di bawah komando dan barisan KH Zainul Arifin, KH Masjkur, dan KH Wahab Hasbullah telah menjadi kekuatan pasukan Kemerdekaan saat itu, dan yang hari ini telah bertransformasi menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Bersama KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Hasbullah (1888-1971) juga berkontribusi besar dalam memperjuangkan bangsa Indonesia dengan mempelopori semangat nasionalisme melalui pendirian Nahdlatul Ulama (NU) dan pesantren, serta menjadi aktor pejuang melawan penjajah melalui Laskar Hizbullah. Beliau juga merupakan penggagas konsep halalbihalal sebagai sarana rekonsiliasi politik, serta mempromosikan kebebasan berpikir dan dialog melalui kelompok diskusi Tashwirul Afkar, yang semuanya berkontribusi pada pembentukan identitas dan kemerdekaan Indonesia.
Bersama KH Hasyim Asy’ari dan Mas Mansoer, KH Wahab Hasbullah juga mendirikan koperasi sebagai badan usaha yang menggerakkan ekonomi rakyat, jauh sebelum koperasi menjadi salah satu bentuk Badan Usaha Mandiri Nasional (BUMN era itu). Dengan demikian, koperasi yang menjadi saka guru perekonomian nasional yang tercantum dalam UUD 1945 bukanlah cita-cita yang lepas dari akar sejarahnya (a historis), tetapi secara empirik pernah dilakukan oleh para santri sebelumnya, yang dikomandani langsung oleh dua tokoh, KH Hasyim Asy’ari dan KH Wahab Hasbullah. Kedua figur tersebut juga yang mendirikan pesantren Tebuireng dan Tambakberas (Bahrul Ulum) yang sangat terkenal di Tanah Air.
Transformasi pesantren
Di banyak pesantren saat ini sudah memiliki sekolah atau madrasah negeri, MTsN, MAN, SMP, SMA, dan SMK. Begitu pula sudah bermunculan perguruan tinggi. Statistik Kementerian Agama 2020/2021 melaporkan, jumlah madrasah di Indonesia saat ini 83.391 lembaga, terdiri dari jenjang raudlatul athfal (RA) yakni sebanyak 30.148 RA atau setara dengan 36.08 persen. Berikutnya, madrasah ibtidaiyah (MI) sebanyak 25.840 MI (30,92 persen), madrasah tsanawiyah (MTs) sebanyak 18.380 MTs (21,99 persen) dan sisanya madrasah aliyah (MA) sebanyak 9.150 MA (11,01 persen). Jika ditambah pondok pesantren, menjadi 113.886 lembaga. Sementara data mutakhir yang dilaporkan Kementerian Agama per September 2025 terdapat perkembangan jumlah pesantren mencapai 42.391 unit yang tersebar di 34 provinsi.
Jika dipersentasekan jumlah pondok pesantren dengan pendidikan keagamaan menjadi 26,77 persen. Persebaran pesantren di Jawa Timur sebanyak 5,121 lembaga dengan jumlah santri 970.541. Sementara itu, jumlah ustaz yang mengabdi di pesantren seluruh Jawa Timur mencapai 95,681 orang. Inilah kekuatan besar santri sebagai modal dan perisai NKRI. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah orientasi keilmuannya harus tetap terjaga. Modal yang sudah mapan di pesantren tidak perlu terkikis oleh arus modernisasi dan globalisasi.
Kini upaya transformasi sistem pendidikan pesantren (pengembangan dan pembaruannya) sudah banyak dilakukan. Memang, tidak semua pesantren melakukan transformasi dan pembaruan, sebab seperti yang dikatakan oleh A Mukti Ali, pesantren adalah milik pribadi kiai. Oleh karena itu, wajarlah jika masih ada pesantren yang tetap bertahan dengan tradisi lamanya dan tidak mau menerima pembaruan.
Mukti Ali juga mengapresiasi model ”madrasah dalam pesantren” yang dinilainya sebagai sistem pendidikan yang paling baik. Oleh karena itu, pesantren seharusnya dilengkapi dengan pendidikan keterampilan, pertanian, pertukangan, kepramukaan, seni, dan olahraga. Dengan demikian, dalam pendidikan madrasah pesantren akan terhimpun tiga komponen: seni, ilmu, dan agama.
Di era modern dan global saat ini, pesantren memang perlu sistem pendidikan yang lebih terbuka dan tetap dapat memenuhi tuntutan zaman tanpa harus kehilangan eksistensi dan jati dirinya sebagai lembaga pendidikan agama. Suatu optimisme dalam dunia pesantren, tetapi di sisi lain pesantren juga perlu melihat kelemahan-kelemahannya.
Kelemahan pesantren memang bukan tidak ada, misalnya soal manajemen dan tata kelola kelembagaan, infrastruktur, kepedulian terhadap ekosistem, serta proses kaderisasi. Sementara kelebihan pendidikan pesantren yang menonjol adalah terbentuknya karakter santri yang unggul. Melalui role model para kiai, mereka diajarkan bagaimana menjadi manusia yang berjiwa solidaritas, tangguh, dan tahan dalam menghadapi berbagai masalah.