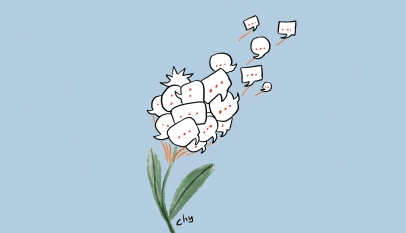Menghargai Kearifan Budaya
Oleh: Chubbi Syauqi
Mahasiswa Jurusan Tarbiyah Prodi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Purwokerto, alumni kegiatan AIDA.
Masih ada kalangan yang memertentangkan antara ajaran Islam dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. Misalnya menganggap kearifan lokal sebagai perilaku tahayul, bid’ah, khurafat, bahkan syirik. Apabila hal ini terus berkembang, maka kehidupan dan keberagamaan masyarakat Islam di Indonesia terancam jauh dari perdamaian. Lebih dari itu dapat dimanfaatkan oleh gerakan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada tindakan terorisme.
Padahal dalam sejarahnya, Islam dan budaya begitu harmonis berkembang di Indonesia, malahan meresapi bangun ruang hidup kita secara keseluruhan, sebagaimana dulu dicetuskan dalam bingkai dakwah para ulama penyebar Islam awal di Indonesia. Mereka mendakwahkan Islam di bumi Nusantara dengan watak kosmopolitan. Segala keragaman suku, budaya dan kepercayaan dipahami sebagai instrumen dakwah. Melihat kondisi masyarakat Nusantara yang multikultural, para ulama dan wali mendakwahkan Islam secara kultural, dari kota-kota pantai utara Jawa yang menjadi pusat perdagangan Nusantara ke daerah-daerah pedalaman.
Baca juga Memaknai Hijrah dalam Bingkai Perdamaian
Para ulama yang kita kenal dengan sembilan wali (Walisongo) ikut mendorong percepatan unsur lokal guna menopang efektivitas dakwah. Kebudayaan dijadikan sebagai teknis operasionalnya. Misalnya menggunakan media gamelan dan seni wayang untuk mendakwahkan Islam. Dengan sedikit merombak seperlunya, wayang kulit dan gamelan terbukti dapat menjadi media dakwah yang efektif. Hingga kini, jejak dakwah tersebut masih dapat dilihat dalam tradisi Sekatenan di pusat-pusat kekuasaan Islam, seperti Cirebon, Demak, Yogyakarta, dan Surakarta.
Sudah barang tentu, metode dan langkah dakwah melalui perantara budaya tersebut tidak dilakukan oleh Walisongo secara gegabah. Mereka tetap mempertimbangkan batas-batas ajaran dasar agama. Selain itu juga telah dipertimbangkan masak-masak. Terkait hal ini, terdapat hadis mauquf yang menegaskan bahwa sesuatu yang dinilai baik oleh komunitas Muslim, maka hal itu juga baik di hadapan Allah Swt. Sebagaimana dinukilkan dalam kitab al-Mustadrak karya Imam al-Hakim (321-405 H) disebutkan bahwa sahabat Abdullah bin Mas’ud pernah menyatakan, “Sesuatu yang dinilai baik oleh masyarakat Muslim, maka hal itu juga dinilai baik di sisi Allah” (H.R. al-Hakim).
Baca juga Mengembangkan Dakwah, Menyuburkan Damai (Bag. 1)
Dalam term ushul fiqh, adat istiadat (baca: budaya) disebut urf. Adat kebiasaan dari masyarakat yang tidak kontradiktif dengan syariat Islam dalam taraf tertentu bisa dijadikan landasan hukum. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi al-’adatu muhakamatun (adat dapat dijadikan dasar sebuah hukum.) Hasil ijtihad para Walisongo inilah melatarbelakangi dakwah kultural di Nusantara. Melalui dakwah yang menghargai kearifan budaya justru Islam mudah berkembang pesat di Indonesia.
Warisan kolonial
Sebenarnya pertentangan ajaran Islam dan budaya dianggap oleh beberapa ilmuwan sebagai bagian dari warisan kolonialisme. Keyakinan ini muncul setelah saya membaca buku berjudul Saya, Jawa, Dan Islam (2019) dan Jawa-Islam di Masa Kolonial (2020). Secara garis besar, isi kandungan buku tersebut adalah memberikan jawaban atas upaya memertentangkan agama dengan budaya yang ternyata merupakan warisan dari penjajah. Proyek pemisahan Islam dengan budaya ini dimulai dari kekalahan perang Jawa yang digawangi oleh Pangeran diponegoro versus Belanda.
Semenjak kekalahan tersebut, Belanda menyadari bahwa agama (Islam) yang dianut oleh sebagian besar penduduk pribumi menjadi pemicu berbagai perlawanan dan pemberontakan. Sebab, Belanda merasa terancam dengan Islam, maka Belanda melancarkan taktik devide et impera (politik adu domba). Belanda berupaya menghadap-hadapkan Islam dan budaya yang selama kurun waktu tertentu begitu menumbuh dalam keberagamaan orang-orang Nusantara.
Baca juga Mengembangkan Dakwah, Menyuburkan Damai (Bag. 2-Terakhir)
Dalam melancarkan politiknya, Belanda mendirikan pusat kajian Kebudayaan Jawa yang dikenal dengan Javanologi. Lewat kajian Javanologi yang bekerja keras mendalami Islam berkebudayaan atau bisa disebut Islam yang disebarkan oleh para Walisongo, kemudian Belanda mempropagandakan serta menuduh Islam berkebudayaan sebagai Islam yang tak murni. Lebih parah lagi, Belanda mengidentifikasikan kaum Islam pribumi dengan istilah abangan dan putihan (santri).
Secara etimologis, abangan mengacu pada kata abang dalam perbendaharaan bahasa Jawa. Istilah Islam abangan dan putihan pertama kali dipopulerkan oleh Clifford Geertz yang menuai begitu banyak kritik. Pasalnya, Islam di Nusantara menurut Clifford Geertz merupakan Islam yang bercampur dengan sinkretisme. Pandangan itu kemudian melahirkan dikotomi abangan dan putihan (santri).
Baca juga Keikhlasan dan Pengampunan Menyembuhkan Luka: Kisah Andi Dina Noviana, Penyintas Bom Thamrin
Seperti yang dimaksud Clifford Geertz, kaum abangan merupakan kaum Jawa yang otentik dan menolak Islam, sedangkan kaum putihan (santri) merupakan kaum Jawa yang menolak Jawa dan menerima Islam. Maka dapat kita tarik benang merah bahwa Islam di Indonesia sedari dulu sudah termarjinalkan melalui kajian akademik ngawur oleh sarjana Barat. Konsekuensi dari pandangan sinkretisme Islam yang memisahkan Jawa dan Islam membuat keduanya seolah-olah vis a vis. Cara pandang ini terkesan terburu-buru dan sembrono.
Sebagaimana juga pendapat Irfan Afifi (2019) dalam bukunya “Saya, Jawa dan Islam” Jawa dan Islam merupakan suatu kesatuan. Segala perilaku bahkan tradisi dalam Jawa merupakan bentuk manifestasi dari ajaran Walisongo. Karakter Islam di Nusantara yang saling bertautan antara Islam dan tradisi, menjadikan ia beragam dan semakin berkembang. Dikotomi abangan dan putihan merupakan strategi kolonial guna memecah belah persatuan, kata Nancy K. Florida dalam artikelnya “Jawa-Islam di Masa Kolonial”.
Baca juga Cermat dengan Stigma Sosial
Islam memunculkan kecurigaan sebagai sebuah kenyataan berbahaya, suatu kekuatan yang mampu dan mungkin akan muncul di mana saja. Kemudian pihak kolonial mengelompokkan masyarakat sebagai “Muslim Sinkretik”. Seperti pandangan Giddens (1990), tradisi akan selalu terbarukan secara berkesinambungan. Lantas, tidak sepantasnya kita terburu-buru mengklaim perubahan yang terjadi akibat dari globalisasi dan modernitas, tetapi lebih mengarah kepada negosiasi. Dengan demikian pandangan Irfan Afifi menjadi penting untuk memahami masyarakat modern perihal Islam di Nusantara.
M.C.Ricklefs dalam “The Birth of The Abangan” (2008) menjelaskan penggolongan sosial masyarakat Jawa antara kaum abangan dan putihan mulai muncul sebagai gejala khas masyarakat Jawa pada paruh kedua abad ke-19. Periode tersebut penting dalam sejarah Islamisasi masyarakat Jawa. Tercatat jumlah orang yang naik haji berkembang. Menurut kalkulasi pemerintah kolonial pada 1850 hanya 58 orang naik haji dari Jawa, akan tetapi di penghujung tahun 1898, jumlah itu naik sampai 5322.
Baca juga Jihad untuk Perdamaian
Hal ini juga dipicu oleh pembukaan terusan Suez pada tahun 1869 yang memudahkan kapal uap berlayar ke negeri Arab. Orang-orang Jawa yang pergi berhaji di sana mendapat sentuhan purifikasi Islam, sehingga memiliki gaya baru dalam berislam. Orang Jawa inilah yang kemudian hari dikenal dengan kaum putihan. Namun, dalam perkembangannya, kaum putihan ini semakin berjarak dengan kehidupan rukun-rukun agama (yang sebelumnya agama rakyat, yang bersinkretis kepada budaya lokal). Kemudian mereka yang menolak ajakan kaum putihan disebut kaum abangan. Sampai di abad ke 19, perbedaan abangan dan putihan semakin gaduh di antara kehidupan orang Jawa.
Dakwah Walisongo
Dakwah yang dilakukan oleh Walisongo menyebar luas di seluruh penjuru pulau Jawa. Keberhasilan dakwah Walisongo lewat jalur kultural yang damai membuat masyarakat Jawa jatuh hati. Walisongo menjadikan budaya sebagai instrumen dakwah sekaligus memiliki ijtihad dalam sudut pandang masyarakat Jawa dengan disuguhi ajaran tauhid serta memberikan kesadaran bahwa hakikat manusia adalah khalifah. Proses manunggalnya Islam dan kebudayaan kemudian lazim disebut pribumisasi Islam.
Dalam perspektif saya, faktor keberhasilan dakwah Walisongo di pulau Jawa adalah adanya sikap kosmopolitan yang ada pada diri mereka. Kita dapat menyaksikan bagaimana para Wali mendakwahkan Islam dengan lemah lembut, serta adanya dialog antarnilai-nilai lokal, sehingga dapat diselaraskan dan tidak vis a vis dengan Islam. Mungkin oleh sebab itu, masyarakat Jawa memiliki corak kebudayaan yang kompleks dan luwes, tetapi memiliki akar filosofi dan dasar hukum Islam yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca juga Negara Madinah: Potret Ideal Pemerintahan Islam
Saya kira, sikap kosmopolitan bukan hanya terjadi pada penyebaran Walisongo yang ada di Jawa. Melainkan berbagai ulama atau wali yang menyebarkan Islam di Nusantara. Hal ini dapat kita tengarai dengan adat kebudayaan suatu daerah tertentu seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, yang mana bentuk adat dan kebudayaannya selaras dengan nilai-nilai Islam. Pada titik inilah saya optimis atas kegelisahan mengenai segala sengkarut permasalahan keberislaman di Indonesia.
Wajah Islam rahmatan lil alamin sudah diimplementasikan oleh para leluhur Nusantara dengan produk Islam berkebudayaan. Adapun yang membuatnya seolah bertentangan tidak lain merupakan taktik kolonial untuk melemahkan umat Islam. Ironisnya, di zaman yang serba modern ini kesadaran untuk meresapi atau mengkaji khazanah Islam berkebudayaan belum menggelora. Padahal untuk melihat esensi Islam di Nusantara, seseorang perlu melihat lebih jeli dengan berbagai perspektif ilmu yang mendalam, tidak dengan kacamata kuda yang sempit dan dangkal.
Baca juga Terapi Pemaafan