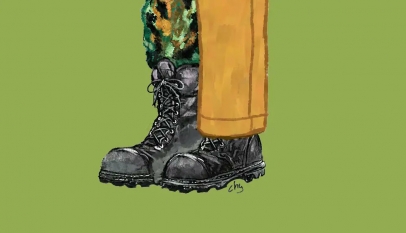Setelah Puasa, Lalu?
Oleh Suharso Monoarfa
(Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (2019-2022), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional [2019-2024]).
Artikel ini terbit di Harian Kompas edisi 26 Maret 2025
Puasa adalah salah satu modal utama untuk mewujudkan pesan profetik yang dibawa Nabi Muhammad, “dan tidaklah kami utus engkau [Muhammad], melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. Al-Anbiya: 107)
Allah mewajibkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa, agar mereka menjadi orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 183). Hal yang sama juga telah diwajibkan (dalam bahasa Al-Qur’an “dituliskan”, kutiba) kepada umat-umat terdahulu sebelum Islam. Dan kesamaan itu hampir pada semua agama dalam sejarahnya. Puasa menjadi rukun-rukun agama karena, seperti dikatakan Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsir Al-Manar, ia termasuk ibadah yang paling kuat dan sarana pendidikan paling efektif.
Muhammad Abduh, guru Rasyid Ridha dalam kitab yang sama mengatakan, “Allah memang hanya menyamarkan ‘mereka sebelum kita’ itu; dan memang bahwa puasa disyariatkan oleh semua agama, sampai-sampai agama yang berciri keberhalaan.” Puasa dikenal orang Mesir Kuno, dan dari sana merembet ke Yunani, yang mewajibkan ibadat itu terutama kepada perempuan. Demikian pula orang Romawi.
Di antara para politeis Hindu, puasa dikenal sampai sekarang. Dan tentu saja di kalangan Yahudi dan umat Nasrani. Nabi Musa, misalnya diketahui berpuasa 40 hari. Adapun umat Yahudi di masa-masa belakangan berpuasa satu minggu sebagai peringatan kehancuran Ursyalim dan penjarahannya, dan satu hari pada bulan Aab.
Sedangkan puasa di kalangan Nasrani yang paling masyhur dan paling kuno adalah puasa besar sebelum Hari Paskah, seperti juga yang dilaksanakan baik oleh Isa maupun Musa, serta para hawari (pengikut Isa). Kemudian para kepala Gereja membuat berbagai peraturan lain, dan di situ terdapat perbedaan di antara pelbagai sinoda dan denominasi. Ada yang berpuasa dari makan daging, dari makan ikan, dari makan telur atau susu, antara lain. Ini berkaitan dengan amal kemanusiaan: dana yang tadinya digunakan untuk konsumsi seperti yang disebut Rasyid itu disisihkan, dikumpulkan, dan disumbangkan kepada fakir-fakir miskin, para korban bencana alam, dan seterusnya.
Baca juga Fitrah dan Keberagamaan yang Berdampak
Literatur-literatur keagamaan Islam menyebutkan puasa sebagai sarana berlatih mengendalikan diri dari jeratan nafsu perut dan faraj – keinginan melahap apa saja serta mengumbar selera rendah. Karena itu puasa disebut latihan perang melawan hawa nafsu. Rasulullah s.a.w. menyebut perang melawan hawa nafsu sebagai sebuah jihad. Sepulang dari Perang Badar melawan musyrikin Quraisy yang dimenangkan kaum Muslim, Nabi bersabda, “Kita kembali dari jihad kecil dan akan menghadapi jihad besar.” “Apa yang dimaksud dengan jihad besar yang akan kita hadapi itu?” tanya sahabat. “Berjihad melawan hawa nafsu,” jawab Nabi.
Jadi, puasa bukan semata melaparkan dan menghauskan diri. Berlapar-lapar dan berhaus-haus hanyalah media untuk melaksanakan ibadah yang sesungguhnya. Yakni menjauhi larangan-Nya, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diridhai-Nya, dan mengendalikan hawa nafsu agar sejauh mungkin tersalur sebagaimana telah digariskan oleh Allah. “Barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan keji (dusta) dan melakukan kejahatan (kepalsuan), Allah tidak akan menerima puasanya, sekalipun ia telah meninggalkan makan dan minum,” sabda Nabi (H.R. Bukhari, Muslim dan Ahmad)
Dalam Tafsir Al-Azhar Buya Hamka mengatakan, “Puasa adalah latihan dan didikan, pembentukan akal dan budi, untuk menaklukan hawa nafsu, untuk berganti ke akal murni yang sesuai dengan agama. Keluar dari latihan itu manusia dapat mengatur dirinya sendiri. Sedang terhadap barang yang halal dia bisa menguasai diri apalagi terhadap yang haram. Inilah arti la‘allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa.”
Selain pendidikan dan latihan, tujuan puasa adalah untuk memperoleh pengampunan dengan ketentuan sebagaimana sabda Nabi, ”Barangsiapa menjalankan puasa dengan penuh iman dan introspeksi (ihtisab), maka akan diampuni dosanya yang telah lalu.” Jadi, puasa adalah sarana untuk melakukan introspeksi. Bukankah dengan berintrospeksi, seseorang semestinya akan menjadi lebih baik?
Dalam banyak hadis juga disebutkan ajakan Rasulullah s.a.w kepada orang yang berpuasa untuk mengerjakan kebaikan. Termasuk mengembangkan solidaritas sosial, karena dengan merasakan sendiri haus dan lapar, seseorang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh yang miskin dan sengsara. Di zaman sekarang, tentu banyak cara yang bisa ditempuh untuk merealisasikan berbagai kebajikan dan mewujudkan solidaritas sosial.
Lalu tantangannya adalah, apakah berbagai hikmah dari ibadah puasa menjamin kita mampu mengisi relung kebaikan kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun sosial. Dan bagaimana menjelaskan jika yang terjadi sebaliknya. Kesemarakan beragama yang ditandai dengan semakin kencangnya orang-orang menjalankan ibadah tidak dengan sendirinya mengubah pekerti yang lalim di dalam masyarakat. Praktik-praktik yang menandai kemerosotan etika dan moral masih terus terjadi.
Baca juga Puasa dan Kemenangan Bangsa
Maka sesungguhnya kita tidak terlalu terkejut ketika kita dihadapkan pada fenomena yang saling berlawanan. Berbagai survei kerap menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang religiusitasnya tertinggi di dunia. Laporan majalah CEOWorld pada 8 April 2024 menempatkan Indonesia sebagai negara ketujuh paling religius di dunia, dengan 98,7 persen responden mengaku religius. Survei lain yang dilakukan oleh Pew Research Center pada 2018 juga menunjukkan bahwa 93 persen masyarakat Indonesia menganggap agama sebagai aspek penting dalam kehidupan mereka (Pew Research Center, 2018).
Fakta yang menggembirakan ini kemudian menjadi sebuah ironi, ketika data lain menunjukkan kebalikannya, yakni Indonesia menempati posisi separuh terbawah dalam Indeks Persepsi Korupsi dari 180 negara. Transparency International dalam laporan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2023 menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100, yang menunjukkan tingkat korupsi yang masih tinggi (Transparency International, 2023). Logikanya, jika masyarakat Indonesia semakin alim, maka seharusnya tingkat korupsinya semakin rendah.
Ironi itu terantuk pada kegagalan kaum beragama dalam mentransformasikan etika dan moralitas pribadi ke dalam etika sosial. Etika dan moralitas pribadi berfokus pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Etika sosial, di sisi lain, berfokus pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku individu dalam interaksi dengan orang lain dan dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Kegagalan dalam menjembatani kesenjangan antara kedua ruang lingkup ini dapat menyebabkan ketidakselarasan antara perilaku individu dan norma-norma sosial.
Maka patutlah berharap puasa sebagai bentuk ibadah paling efektif untuk menjadi manusia yang takwa, semestinya secara horisontal mendemonstrasikan akhlak sosialnya yang tidak lalim. Apakah secara sosial, akhlak kita sudah sejalan dengan pesan profetis bahwa Islam adalah rahmat bagi sekalian alam? Jika tidak, lalu apa artinya kita berpuasa sebulan penuh?
Minal ‘aidin wal-faizin.