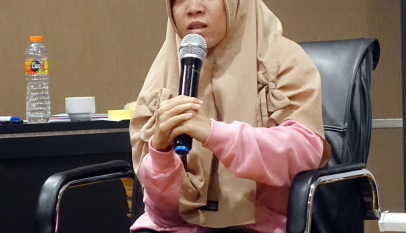Pencegahan Terorisme dan Hak Korban
Usai serangan teror bom menerjang Kampung Melayu Jakarta Timur akhir Mei lalu, Presiden Joko Widodo meminta agar pembahasan revisi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di DPR RI lekas diselesaikan. UU terorisme baru diharapkan menjadi payung hukum penguatan pencegahan aksi terorisme.
Revisi UU Terorisme sangat berfokus pada aspek pencegahan. Sejumlah isu yang muncul antara lain pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, perpanjangan masa penangkapan (penahanan), dan pengucilan terduga terorisme. Penguatan ini merespons perkembangan subur Islamic State of Iraq and Syam (ISIS) yang menuai simpati di banyak negara, termasuk Indonesia.
Negeri ini memiliki trauma mendalam terhadap kelompok jihadis transnasional semacam ISIS. Pada dasawarsa 2000, sebagian besar aksi teror bom di Indonesia didalangi oleh veteran perang Afghanistan yang berafiliasi kepada Alqaeda melalui Jamaah Islamiyah. Janji surga para petinggi ISIS berhasil membuai ratusan WNI berhijrah sukarela ke Suriah untuk bernaung dalam khilafah. Sementara yang tak memiliki kemampuan hijrah, dianjurkan melakukan amaliyat irhabiyah (aksi teror) di dalam negeri yang diyakini sebagai jihad fi sabilillah. Hal itu terimplementasikan dalam sejumlah serangan, antara lain di Jalan Thamrin Jakarta Januari 2016 dan Bom Kampung Melayu bulan lalu.
Aspek yang terlewat dari diskursus pencegahan dalam revisi UU Terorisme adalah peran penyintas (korban selamat). Sebagai saksi hidup kekejaman terorisme, penyintas sangat potensial menjadi agen perdamaian. Kisah hidupnya diharapkan memantik empati dan simpati kemanusiaan. Dengan menyaksikan langsung dahsyatnya dampak terorisme yang tampak dari kondisi fisik penyintas, mereka yang telah terindoktrinasi radikalisme agama diharapkan berpikir ulang untuk melakukan kekerasan.
Pendekatan afektif ini bisa menjadi alternatif atas pola kampanye antiradikalisme dan deradikalisasi yang selama ini lebih mengedepankan pendekatan kognitif (adu argumentasi keagamaan). Tak ada salahnya revisi UU terorisme ini juga menempatkan penyintas terorisme sebagai salah satu aktor utama pembangunan perdamaian dan kontraradikalisasi.
Tentu tak semua penyintas terorisme dapat menjadi juru perdamaian yang kuat. Namun melalui pembekalan yang memadai, naturalitas suara penyintas sangat potensial meluluhkan hati orang-orang yang telah terindoktrinasi radikalisme-terorisme. Dalam pengalaman AIDA, lembaga di mana penulis bekerja, sejumlah penyintas sanggup bertemu dan berdialog secara intim dengan sejumlah narapidana terorisme di dalam Lapas, bahkan dengan teroris yang terlibat aktif dalam serangan yang mencederai dirinya.
Namun sebelum memberdayakan penyintas terorisme sebagai juru kampanye perdamaian, seyogyanya negara memastikan hak-hak mereka, khususnya rehabilitasi medis dan psikis, serta menjamin hak-hak lainnya dapat terlaksana tanpa prosedur yang rumit. Semua itu adalah bentuk pertanggungjawaban negara atas kegagalannya menjamin keamanan warga.
Korban terorisme adalah “martir” negara, sebab selalu ada keterkaitan antara motif terorisme dengan kebijakan negara. Hampir seluruh pelaku terorisme di Indonesia menyatakan kekecewaannya karena Republik ini tidak menerapkan syariat Islam sebagai landasan konstitusional. Secara pribadi, korban tak mempunyai masalah dengan teroris. Namun mereka harus kehilangan nyawa, anggota tubuh, mata pencaharian, dan lainnya akibat ulah teroris.
Dalam banyak kasus yang penulis temui, tanggung jawab negara dalam pembiayaan medis korban terorisme hanya seumur jagung. Padahal sebagian penyintas harus mendapatkan perawatan medis seumur hidup. Karena itu sangat penting negara memastikan jaminan pembiayaan rehabilitasi medis dan psikis korban terorisme hingga sembuh. Revisi UU terorisme adalah momentum tepat.
Sementara kompensasi korban yang diatur dalam UU Terorisme tak pernah terlaksana karena prosedur yang rumit. Kompensasi diberikan oleh negara atas dasar putusan majelis hakim yang menyidangkan perkara terorisme. Klausul ini menjiplak pasal 35 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Sejauh ini praktik kompensasi korban tindak pidana telah banyak terlaksana kepada korban pelanggaran HAM berat berdasarkan UU Pengadilan HAM. Sementara bagi korban salah prosedur penegakan hukum berdasarkan PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP (telah direvisi menjadi PP No. 92 Tahun 2015). Dalam dua kasus tersebut, pelakunya adalah alat negara, karena itu negara lah yang wajib memberikan ganti rugi.
Sementara terorisme dilakukan oleh warga sipil. Jaksa Penuntut Umum sebagai pengacara negara barangkali merasa gamang harus menuntut “kliennya” sendiri atas kejahatan yang dilakukan oleh warga sipil non aparat. Maka tak mengherankan, pada awal November 2016, permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mengajukan kompensasi bagi sembilan orang korban Teror Thamrin melalui tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada Fahrudin (terdakwa Teror Thamrin) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ditolak. Jaksa urung membacakan tuntutan kompensasi korban itu.
Seyogyanya revisi UU terorisme mengubah ketentuan pencairan kompensasi korban terorisme. Bukan lagi berdasarkan amar putusan pengadilan, melainkan kajian mendalam lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh UU.
Aksi terorisme mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis para korban dalam rentang waktu panjang. Rehabilitasi dan kompensasi bermanfaat mengembalikan kualitas hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Karena itu kompensasi bukan sekadar santunan karitatif seperti diterima oleh para korban dan keluarganya selama ini. Nominal kompensasi harus ditaksir berdasarkan kerugian korban atau keluarga yang ditanggungnya.
Tak ada yang berharap terorisme kembali terjadi. Namun jika tragedi itu tak terhindarkan, setidaknya penderitaan korban terorisme tak berlipat ganda karena lemahnya kepedulian negara. Jika diberdayakan, korban yang telah menjadi penyintas adalah agen kampanye perdamaian yang efektif.
*Artikel ini pernah dimuat di Tempo.co 3 Juli 2017