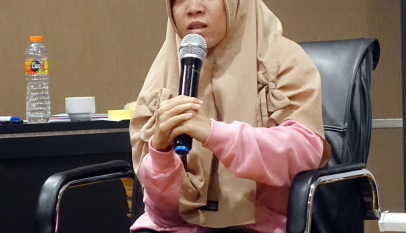Indonesia dan Paradoks Negara Paling Religius
Oleh: Muhamad Wafa Ridwanulloh
Ketua Paguyuban Duta Baca Jawa Barat
Sebuah penelitian menyebutkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang paling menganggap penting posisi ”agama” dalam kehidupan. Namun, pada saat yang bersamaan hampir tidak pernah terlewat dalam berita-berita di media massa dan media sosial tentang kasus-kasus kriminal, seperti pembunuhan, pemerkosaan atau pencabulan, korupsi, judi daring, dan tindakan diskriminasi.
Fenomena ini menjadi ironi dan paradoks di tengah religiositas yang dianut mayoritas masyarakat di Indonesia. Paradoks secara harfiah artinya bertentangan dengan opini sehingga bersifat kontradiktoris (T Kasturi: 2015, 5). Alih-alih menjadi landasan hidup, agama tidak lebih sebatas simbol yang hanya muncul di permukaan sebagai identitas, bukan substansi yang esensial.
Indonesia paling religius
Jonathan Evans, peneliti senior Pew Research Centre yang berfokus pada penelitian agama, melakukan survei tentang komitmen beragama di 102 negara dalam rentang tahun 2008 hingga 2023. Dalam laporan yang dirilis 9 Agustus 2024 di situs resmi Pew Research Centre, Indonesia menduduki urutan pertama sebagai negara yang memprioritaskan agama dan berdoa setiap hari.
Baca juga Menguatkan Komitmen Dunia Digital Ramah Anak
Negara-negara di sub-Sahara Afrika termasuk yang berada di urutan teratas dalam aspek religiositas. Sebaliknya, hampir semua negara Eropa paling tidak memosisikan agama sangat penting dalam hidup mereka. Bahkan di Swiss, Denmark, Inggris, Swedia, dan Finlandia hanya 10 persen atau kurang orang dewasa yang berpandangan religius.
Agama sebagai panduan hidup akan membawa bangsa Indonesia pada nilai kesopanan, moralitas, kejujuran, dan empati yang besar. Namun, ada kontradiksi dalam sikap masyarakat: di satu sisi menganggap agama penting, dan secara bersamaan juga membudayakan tindakan-tindakan yang keluar dari substansi ajaran agama.
Religius tetapi nakal
Predikat negara paling religius ternyata beririsan dengan predikat-predikat lain yang bertentangan. Pertama, indeks persepsi korupsi di Indonesia konsisten rendah. Lembaga Transparency International (TI) mengukur indeks tersebut dalam Corruption Perception Index (CPI), semakin tinggi indeks persepsinya, semakin bersih negara tersebut.
Korupsi di Indonesia menjadi budaya yang mengakar dari hulu ke hilir. Budaya korupsi tidak hanya hadir di kalangan elite pemerintah, tetapi sudah merambah ke level masyarakat kecil di akar rumput. Misalnya, serangan fajar, amplop untuk kelancaran birokrasi, plagiat atau mencontek, serta keculasan mengambil atau menjarah barang yang bukan miliknya telah menjadi budaya di kalangan masyarakat.
Baca juga Strategi “Dua Tangan” Trump di Timur Tengah
Misalnya, laporan Digital Civility Index (DCI) yang dikeluarkan Microsoft pada akhir 2021 pernah menobatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat keadaban atau kesopanan di dunia maya terendah se-Asia. Warganet Indonesia rentan melakukan perundungan siber (cyberbullying), menyebarkan hoaks, trolling, dan melakukan pelecehan terhadap kaum marjinal.
Krisis moral di kalangan generasi muda terus terjadi, baik di dunia nyata maupun maya. Alih-alih menjaga moralitas ketimuran, justru bermunculan kasus-kasus seperti tawuran, vandalisme, bahkan muncul video siswa yang membentak dan menghina guru.
Anonimitas di dunia maya lebih parah lagi dalam menggambarkan ketidaksopanan masyarakat Indonesia. Ujaran kebencian dan cacian menjadi hal lumrah bagi warganet Indonesia. Kesopanan menjadi barang langka di negara yang bangga dengan ramah tamahnya.
Ketiga, Indonesia juga menjadi negara dengan pemain judi daring terbanyak di dunia. Tidak tanggung-tanggung, menempati urutan pertama dengan 201.122 pemain, melampaui Kamboja di urutan kedua dengan 26.279 pemain (laporan: Drone emprit). Peningkatan eksponensial jumlah pemain judi daring di Tanah Air menjadikan Indonesia pasar empuk bagi situs-situs ilegal.
Masyarakat kian kehilangan arah. Nilai transaksi judi daring di Indonesia mencapai Rp 600 triliun per Maret 2024. Masyarakat tertipu dengan ilusi kemenangan palsu dari judi daring, para pencandunya kehabisan uang, utang menumpuk, kehilangan harga diri, moralitas, dan mendapat tekanan yang tinggi. Tidak sedikit kecanduan judi daring berakhir pada tindakan kriminal hingga bunuh diri.
Beberapa paradoks menunjukkan bahwa agama tidak benar-benar dihayati secara esensial oleh masyarakat. Parahnya, beberapa kasus korupsi, ujaran kebencian, tindakan kriminal, seperti kekerasan seksual, justru dilakukan sosok yang mestinya menjadi teladan dan tidak jarang membawa simbol keagamaan untuk menutupi kejahatannya.
Kita sering kali bangga dengan Asian Value atau nilai ketimuran yang dimiliki dengan mengedepankan nilai moral, norma, empati, dan adab. Kini, semua terkikis individualisme, egosentris, bahkan sistem yang sering kali menciptakan ketidakadilan. Simbol religiositas hanya menjadi hiasan bukan landasan moral. Religius kita lebih kuat di simbol daripada substansi.
Kini saatnya bertanya, apa kita sudah benar-benar memahami agama? Masalahnya bukan pada agama, melainkan cara kita memahami dan menjalaninya. Agama bukan soal ritual, atribut yang dikenakan, doa yang dilantunkan, atau rumah ibadah yang dibangun. Agama adalah tentang memilih dan menjalani hidup di setiap helaan napas agar berada dalam koridor yang benar.
Manusia beragama harus kembali ke inti dari segalanya: mengapa kita ada di sini? Apa tujuan hidup kita? Manusia umumnya sering lupa bahwa kehidupan ini adalah perjalanan. Perilaku individu beragama yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut sejatinya telah menciptakan kerusakan-kerusakan terstruktur.
* Artikel ini telah terbit di Kompas.id edisi 22 Februari 2025