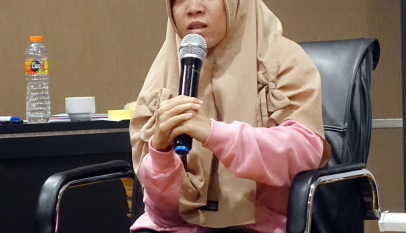Mudik dengan Damai
Oleh Deddy Mulyana
(Guru Besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran)
Artikel ini terbit di laman Kompas.id edisi 26 Maret 2025
Salah satu peristiwa kolosal tahunan di negeri kita adalah mudik lebaran. Diperkirakan lebih dari 100 juta orang melakukannya tahun ini.
Fenomena mudik ini menarik untuk dikaji dari berbagai sudut pandang, dan tak pernah kering untuk diwacanakan. Ada nuansa filosofis, sakral, nostalgik, dan puitis di dalamnya. Semuanya berakar pada hakikat diri manusia. Siapakah diri ini?
Filsuf Jerman, Martin Heidegger, pernah membahas mudik (pulang kampung), terutama lewat pemikirannya tentang ”menjadi,” ”tempat tinggal,” dan ”eksistensi yang otentik,” khususnya dalam Being and Time (1927) dan Building, Dwelling, Thinking (1954).
Dalam karya pertama, Heidegger menggagas bahwa manusia sering terjebak dalam kehidupan sehari-hari, terperosok dalam hiruk-pikuk dunia dan konvensi sosial sehingga terasing dengan dirinya sendiri.
Kembali ke jati diri yang otentik
Dalam konteks ini, menurut Heidegger, mudik bukan berarti kembali ke lokasi fisik, melainkan ke jati diri yang otentik, disertai keteguhan hati untuk bertanggung jawab atas eksistensi diri.
Keteguhan hati seseorang bermakna bahwa ia tidak terserap oleh kesibukan dunia dan bahwa ia bersiap menghadapi keterbatasan diri, menuju kematian.
Kebanalan dunia dengan teknologinya yang canggih dewasa ini sering membuat manusia kehilangan jati diri seolah ia hanya tunawisma kehidupan, sekrup kecil dari sebuah mesin raksasa atau selembar daun yang terombang-ambing di samudra luas.
Itu sebabnya Heidegger menekankan sifat puitis tempat tinggal, merujuk pada puisi Friedrich Holderlin, yang mengungkapkan kerinduan nostalgik untuk pulang kampung.
Namun, bagi Heidegger, mudik bukan hanya kepulangan nostalgik, melainkan transformasi eksistensial—menengok kembali asal-usul diri untuk melangkah maju secara bermakna.
Dengan kata lain, mudik bukan sekadar kepulangan fisik, melainkan perpindahan ontologis-eksistensial—kembali ke diri sendiri, ke tempat tinggal yang otentik, dan ke hubungan yang lebih dalam dengan alam semesta (Tuhan, manusia, dan lingkungan alam, termasuk hewan dan tumbuhan).
Dalam karya selanjutnya, khususnya esai Building, Dwelling, Thinking (1951), Heidegger mengembangkan gagasan tentang berdiam sebagai cara mendasar manusia untuk hidup.
Ia berpendapat bahwa berdiam berarti betah di dunia, tidak sekadar tinggal di rumah fisik, tetapi hidup dengan cara yang menghargai dan merawat keberadaan segala sesuatu.
Jadi, mudik berkaitan dengan gagasan belajar untuk bertempat tinggal dengan benar—menyelaraskan diri dengan lingkungan, sejarah, dan hakikat diri, bukan sekadar menempati suatu ruang.
Struktur tempat tinggal ini terdiri atas empat hal: bumi, langit, Tuhan, dan makhluk fana. Mudik berlangsung ketika manusia menyadari posisi mereka dalam harmoni keempat hal ini dan memahami dimensi puitis dan sakral keberadaan.
Baca juga Puasa sebagai Terapi dan Ragam Perspektifnya di Benua Eropa>
Heidegger berpandangan, mudik bukan sekadar kepulangan secara spasial atau emosional, melainkan peristiwa fenomenologis yang memungkinkan manusia mampu mengatasi keterasingan dirinya di dunia.
Hal ini melibatkan pencarian kembali eksistensi seseorang, belajar untuk hidup selaras dengan alam semesta untuk menjadi diri yang otentik.
Perspektif Heidegger senada dengan pandangan Rabindranath Tagore, pemenang Nobel Kesusastraan tahun 1913 asal India, bahwa pendidikan tertinggi manusia tidak sekadar memberi informasi, tetapi membuat hidup kita harmonis dengan seluruh alam semesta.
Tidak salah melakukan mudik bernuansa kultural atau etnis, untuk memuaskan kerinduan dan obsesi mengenai asal-usul kita, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang di negeri kita pada hari-hari ini.
Kembali kepada Tuhan
Kecenderungan untuk merasa menyatu kembali dengan leluhur bersifat primordial, manusiawi, dan universal.
Namun, jika kita setuju dengan pandangan Heidegger bahwa mudik seyogianya ditandai dengan kedamaian dengan alam semesta, termasuk lingkungan manusia, maka hanya orang-orang berhati bersih yang dapat menikmati mudik mereka.
Mereka bisa pulang dengan damai. Bahkan, mereka siap melakukan mudik sejati, yakni kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
Itulah induk dari segala mudik. Dalam ungkapan Agus Noor dalam cerpennya yang berjudul ”Mudik ke Kuburan” (Kompas, 28/4/2024), kuburan adalah sebaik-baik tempat mudik. Apa yang akan kita bawa saat kita mati nanti?
Saat berbaring di ranjang rumah sakit dan mengingat kembali seluruh hidupnya, Steve Jobs, inovator teknologi komunikasi terdepan sejagat, menjelang wafatnya karena kanker pankreas tahun 2011, pernah berujar, ”Aku menyadari bahwa semua penghargaan dan kekayaan [7 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 100 triliun] yang sangat kubanggakan menjadi tidak ada artinya dalam menghadapi kematian yang sudah dekat.”
Sulit bagi kita membayangkan bagaimana orang-orang yang selama ini menggarong harta rakyat dan menyengsarakan mereka dapat mudik dengan damai karena hati mereka kotor.
Baca juga Puasa dan Kemenangan Bangsa
Apakah para koruptor ini sebahagia warga biasa yang mudik tanpa beban dengan membawa oleh-oleh ala kadarnya untuk keluarga dan kerabat?
Sebagai manusia yang memiliki nurani, apakah mereka merasa sedikit bersalah ketika mereka berbagi cuan dengan handai tolan? Tebersitkah di benak mereka bahwa uang yang mereka bagikan itu haram?
Seandainya para koruptor ini sempat berziarah ke makam orang tua dan atau makam leluhur mereka, adakah rasa gelisah dan nestapa di hati mereka saat mereka melihat nisan kuburan dan membayangkan bagaimana kelak nasib mereka sendiri jika mereka sudah berada di alam sana?
Kesuksesan macam apa yang kita cari dalam hidup? Mengapa kita harus menumpuk-numpuk kekayaan, siang malam, dengan menghalalkan segala cara? Mengapa kita harus mengkhianati dan menyakiti banyak orang, terutama rakyat, untuk mengejar kekuasaan dan ketenaran?
Keterhubungan dengan sesama
Menurut Paul Pearsall (2002), sukses demikian adalah sukses beracun (toxic success) yang ciri-cirinya adalah stres, depresi, sakit, bunuh diri, merasa kurang (tidak bersyukur), keterpisahan dari orang-orang tersayang, mengorbankan orang lain, ambisius, penuh keraguan, dan mudah kecewa.
Sebaliknya, menurut Pearsall, ciri-ciri sukses sejati (sweet success) meliputi kepuasan, ketenangan, dan keterhubungan dengan orang lain.
Lewat risetnya atas 100 orang sukses, Pearsall menemukan hanya 10 persen orang yang meraih sukses sejati.
Baca juga Tantangan Puasa di Era Digital Perspektif Beragama Maslahat
Sisanya, 90 persen, adalah peraih sukses toksik. Termasuk seorang profesional perempuan penderita kanker yang tajir, populer, tetapi bercerai dengan suaminya, dan ditinggal mati putri tunggalnya yang bunuh diri karena merasa ditelantarkan kedua orang tuanya.
Berdasarkan riset yang dilakukan Universitas Harvard sejak 1938, selama 75 tahun, terhadap 724 orang Amerika, keterhubungan dengan sesama manusia (keluarga, teman-teman, komunitas) membuat orang hidup bahagia dan sehat. Orang yang masih punya hubungan baik pada usia 50 tahun, menjadi orang paling sehat pada usia 80 tahun.
Marilah kita mudik dengan damai.