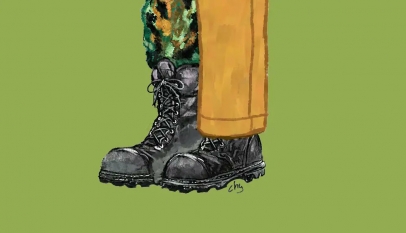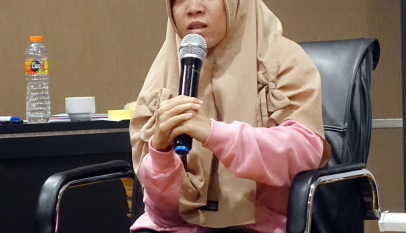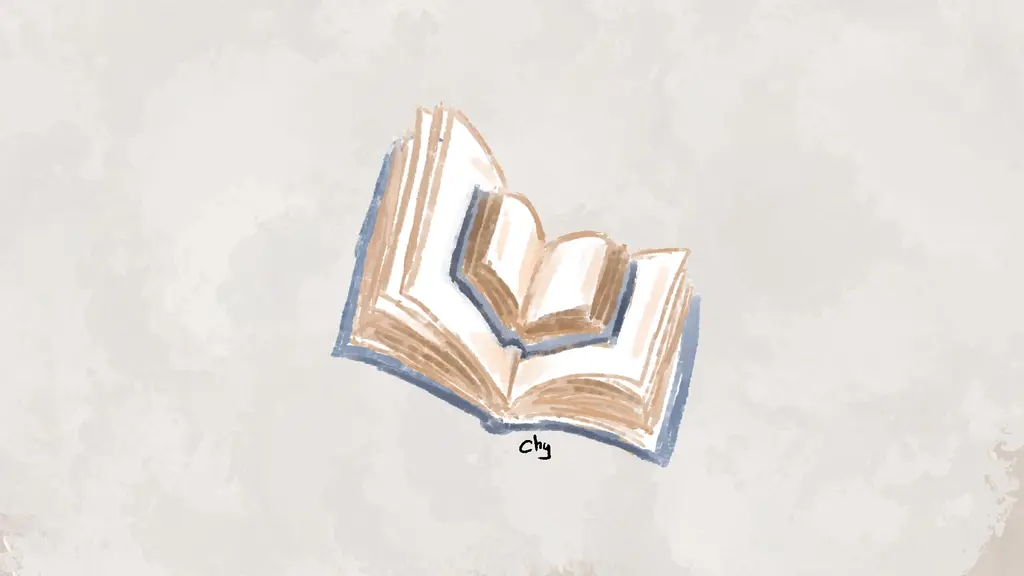Strategi Lunak Penanganan Terorisme (Bagian I)
Oleh: Novi, Lulusan Program Magister Kajian Terorisme, dan Laode Arham, Master Kriminologi, Universitas Indonesia.
Masih lekat dalam ingatan Ali Imron (terpidana seumur hidup kasus Bom Bali 2002), semburan api yang lebih tinggi dari pohon kelapa akibat ledakan bom mobil seberat satu ton lebih di Jalan Legian, Kuta Bali, pada 12 Oktober 2002 malam. Ia tidak menyangka ledakan dan dampaknya sebesar itu. Dua ratus orang lebih menjadi korban seketika. “Saya saja yang melihatnya terasa sakit, apalagi para korban,” ujar Ali Imron dengan nada sangat menyesal. Ia pun memohon maaf pada sejumlah korban bom yang bersilaturahmi dengannya di Markas Polda Metro Jakarta. Tim AIDA menjadi salah satu saksi harunya perjumpaan itu.
Ali Imron dan kebanyakan mantan pelaku terorisme di Indonesia merupakan contoh nyata dari strategi lunak (soft approach) penanganan terorisme yang berhasil dilakukan aparat keamanan dan pemerintah yang melibatkan banyak aktor, termasuk kelompok masyarakat sipil. Ali Imron dan banyak profil lain yang sudah berubah pernah menimba ilmu perang di Afganistan dan Filipina Selatan.
Baca juga Jalan Panjang Kebangkitan Korban Bom Bali 2002: Penyembuhan Luka (Bagian I)
Tidak sedikit pula yang “terbina” melalui perang lokal dalam konflik Poso dan Ambon di awal-awal reformasi (1999-2002), lantas terlibat dalam berbagai aski terorisme di tanah air. Adapun mereka yang pernah berperang di luar negeri disebut Foreign Terrorist Fighters (FTF), seperti Ali Imron yang tergabung dalam kelompok Jemaah Islamiyah (JI).
Dalam konteks keamanan global, perjalanan seseorang atau kelompok menuju wilayah-wilayah konflik dipandang sebagai hal yang “sangat serius”. Jurnal Foreign Terrorist Fighters: Trends, Dynamics, and Policy Response menyatakan, mereka yang pernah pergi ke negara konflik turut berkontribusi terhadap proses radikalisasi pemahaman ekstrem, memperluas pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan aksi-aksi kekerasan, serta memainkan peran penting dalam perpanjangan konflik (ICCT, 2016).
Selama periode 1980-an hingga 1990-an, sekitar 200 orang Indonesia, melakukan perjalanan ke perbatasan Pakistan–Afghanistan untuk mengikuti pelatihan militer bersama orang-orang dari berbagai belahan dunia lain di Afghanistan (Sumpter, 2018, Solahudin, 2011). Hal itu terulang kembali melalui munculnya Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) di tahun 2013 dan 2014. Terdapat peningkatan “hijrah”, dimana lebih dari 40.000 orang asing secara kolektif bergabung dengan Islamic State (IS). Kurang lebih 600 orang Indonesia menjadi FTF di Irak dan Suriah.
Baca juga Jalan Panjang Kebangkitan Korban Bom Bali 2002: Upaya Kebangkitan (Bagian II-Terakhir)
Jurnal Terror or Terrorism? Al-Qaeda and the Islamic State in Comparative Perspective (2018) menjelaskan, ada perbedaan motivasi antara individu yang hijrah ke Afghanistan dengan orang-orang yang berangkat ke Suriah dan Irak. Dulu, orang berangkat ke Afghanistan karena ingin terlibat membantu membebaskan negara tersebut dari invasi militer Uni Soviet. Usai peperangan berakhir, hampir semuanya pulang ke negerinya masing-masing, termasuk yang berasal dari Indonesia.
Sementara orang tertarik bergabung dengan ISIS memiliki tujuan untuk bernaung di bawah panji Khilafah. Selain itu, ada pula motivasi untuk misi kemanusiaan, kekecewaan akan negara yang mereka tinggali, mencari keluarga, atau mendapatkan penghasilan. Bagi orang-orang yang motifnya murni untuk bernaung di bawah pemerintahan Khilafah, kebanyakan mereka enggan kembali ke negerinya, kecuali mereka terpaksa pulang. (bersambung)
Baca juga Kekerasan Tidak Menyelesaikan Masalah