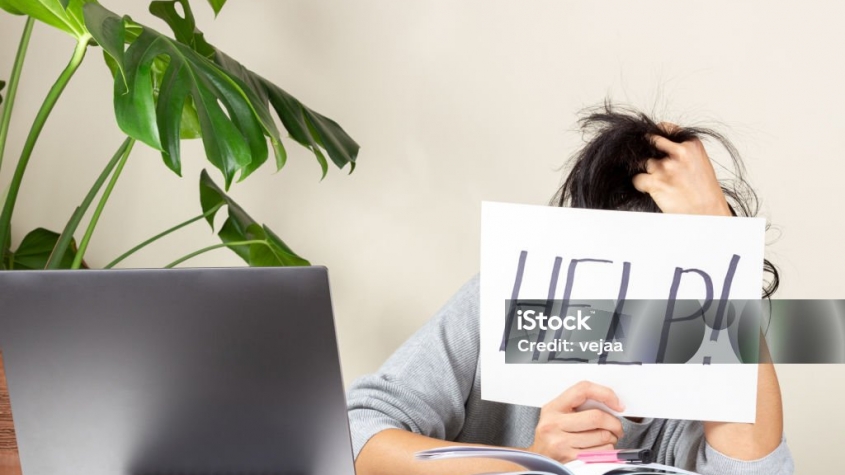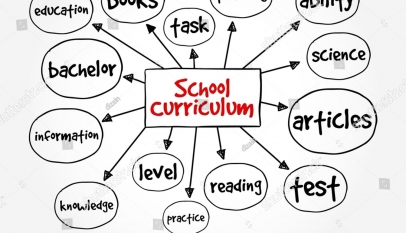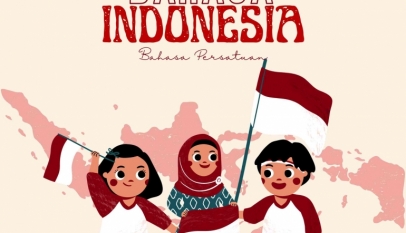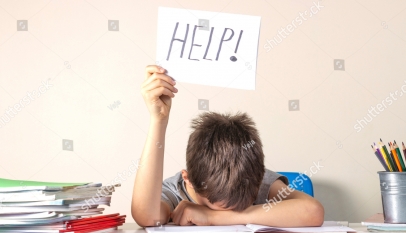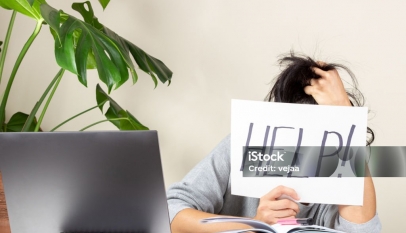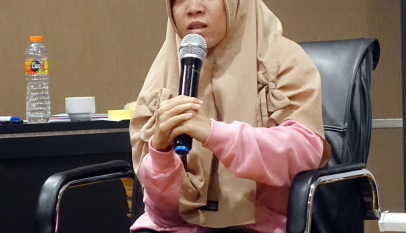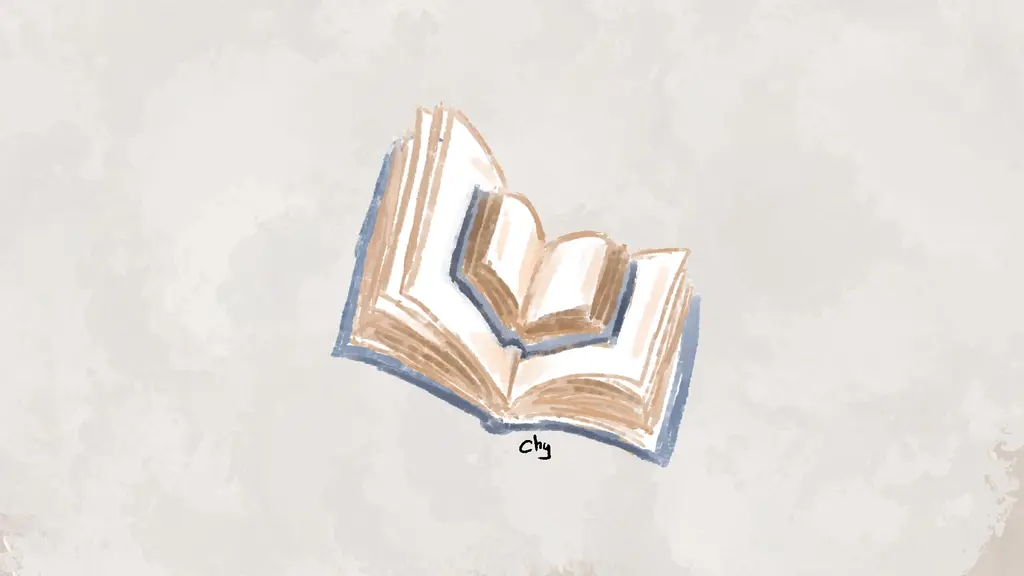Sasaran Kemarahan Itu Bernama Sekolah
Oleh Karunia Kalifah Wijaya
(Guru Bimbingan Konseling SMP Muhammadiyah 1 Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)
Artikel ini terbit di laman kompas.id, 19 Apr 2025
Mengapa orangtua bisa lebih marah kepada guru ketimbang pada koruptor pendidikan?
Di ruang guru yang pengap dan penuh tumpukan kertas, seorang ibu muda datang dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan kekesalan. Ia mengaku anaknya mengalami tekanan mental karena diberi nilai rendah. Guru yang menjadi sasaran kemarahan itu tak sempat menjelaskan bahwa penilaian diberikan berdasarkan standar yang disepakati bersama.
Saat kepala sekolah menjelaskan bahwa keterbatasan tenaga pengajar dan kurikulum yang berubah-ubah menyulitkan proses belajar, sang ibu tetap tak puas. Yang menarik: kemarahan itu tidak diarahkan pada sistem, pada birokrasi, atau pada negara. Ia ditumpahkan langsung kepada individu yang paling dekat, guru.
Fenomena semacam ini terjadi di banyak tempat. Masyarakat frustrasi terhadap kondisi pendidikan, tetapi sasaran kritik dan tuntutannya kerap keliru. Sekolah dalam konteks ini menjadi semacam ”benda publik emosional”, dipenuhi harapan, tapi juga menjadi wadah pelampiasan kekecewaan.
Baca juga Urgensi Pendidikan Perdamaian
Pertanyaannya, masihkah sekolah menjadi milik publik atau ia telah berubah menjadi proyek privat yang hanya melayani ambisi individu dan kelompok tertentu?
Sekolah sebagai ruang emosi kolektif
Studi Schools as Public Things (Keynes et al., 2023) mengajukan satu ide penting bahwa sekolah bukan sekadar institusi teknokratik, melainkan ”benda publik” yang menjadi pusat afeksi kolektif masyarakat.
Sekolah adalah tempat kita menaruh harapan akan masa depan yang lebih baik, juga tempat kita memproyeksikan rasa takut terhadap kegagalan, ketimpangan, dan kehilangan status sosial. Dalam konteks Indonesia, konsep ini sangat relevan.
Pendidikan telah lama menjadi jalan harapan di tengah ketidakpastian ekonomi. Orang tua menyekolahkan anak mereka bukan hanya agar bisa membaca dan berhitung, tetapi untuk melompat dari kelas sosial yang stagnan. Sekolah bukan sekadar tempat belajar, melainkan semacam ”mesin” mobilitas.
Namun, dalam tekanan semacam itu, sekolah menjadi ruang yang sarat tuntutan dan beban emosional. Guru dipaksa menjadi agen perubahan, pendidik moral, terapis, dan penghibur sekaligus, dengan gaji dan sumber daya yang terbatas.
Ketimpangan akses dan privatisasi emosi
Konstitusi Indonesia menjamin bahwa pendidikan dasar adalah hak semua warga negara. Namun dalam praktiknya, siapa yang benar-benar mendapatkan akses pendidikan berkualitas masih sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal, status sosial, dan daya beli keluarga.
Sekolah-sekolah negeri di pusat kota besar cenderung lebih difasilitasi dan diperebutkan, sedangkan sekolah di daerah pinggiran atau perdesaan sering kali tertinggal dalam infrastruktur, tenaga pendidik, bahkan kurikulum.
Sistem zonasi yang dirancang untuk meratakan kesempatan tak jarang memperkuat ketimpangan. Keluarga berdaya ekonomi tinggi akan pindah rumah agar anaknya masuk sekolah favorit. Adapun keluarga miskin harus pasrah dengan sekolah terdekat, yang belum tentu setara kualitasnya. Dalam situasi ini, pilihan akan sekolah menjadi cermin dari kekuasaan ekonomi dan sosial.
Privatisasi pun masuk melalui jalur ”emosi”. Ketika orang tua tidak percaya pada sistem pendidikan publik, mereka menciptakan solusi sendiri: mendaftarkan anak ke sekolah swasta yang mahal, sekolah agama yang selektif, atau program homeschooling berbasis kurikulum luar negeri.
Tujuannya bukan sekadar mendapatkan pendidikan yang lebih baik, tetapi juga membentuk ”identitas sosial” baru bagi anak, lebih eksklusif, lebih aman, dan lebih unggul. Di sinilah pendidikan berubah dari kebutuhan kolektif menjadi proyek personal yang dibungkus semangat meritokrasi.
Sekolah sebagai komoditas
Relasi antara orang tua dan sekolah kian menyerupai hubungan antara klien dan penyedia jasa. Orang tua membayar, sekolah harus menghasilkan. Guru menjadi operator dari mesin prestasi yang diukur lewat ranking, sertifikat, dan nilai ujian.
Jika hasil tak sesuai harapan, keluhan, protes, bahkan gugatan hukum bisa terjadi. Namun, siapa yang membela guru? Siapa yang memahami beban afektif mereka?
Dalam banyak kasus, sekolah privat justru lebih diuntungkan. Dengan sumber daya lebih, mereka dapat memasarkan diri sebagai ”sekolah berkarakter”, ”unggulan akademik”, atau ”berbasis nilai agama”, menarik segmen pasar yang spesifik.
Akan tetapi, realitasnya sekolah semacam ini hanya bisa diakses oleh mereka yang punya daya beli tinggi. Maka, sekolah berubah menjadi arena kompetisi status, bukan lagi ruang pembelajaran sosial.
Baca juga Memperhatikan Ruang Aktual Pendidikan
Keynes et al menyebut bahwa relasi afektif yang timpang antara orang tua dan sekolah membuat institusi pendidikan kehilangan identitas publiknya. Sekolah menjadi tempat ekspektasi berlebih, bukan tempat pertumbuhan kolektif. Dalam logika ini, pendidikan bukan lagi proses membentuk warga, tetapi proyek mencetak individu unggul untuk bersaing, bukan untuk berbagi.
Negara hadir secara parsial
Kehadiran negara dalam dunia pendidikan sering kali bersifat parsial dan terputus dari realitas lapangan. Kita melihat negara hadir dalam bentuk kurikulum nasional, penilaian berbasis komputer, dan berbagai program digitalisasi.
Namun, semua itu tidak otomatis menjawab kebutuhan manusiawi dari pendidikan: ruang dialog, otonomi guru, dan relasi sosial yang sehat. Negara hadir sebagai penyusun regulasi, tetapi belum benar-benar hadir sebagai penguat iklim belajar yang adil dan empatik.
Banyak guru merasa terjepit di antara sistem yang menuntut dan orang tua yang mendesak. Banyak kepala sekolah tak lagi bisa fokus pada pendidikan karena tenggelam dalam laporan administratif yang menumpuk.
Di sisi lain, orang tua merasa bahwa sekolah tak lagi bisa dipercaya mendidik anak secara utuh. Ketidakpercayaan ini menciptakan jarak, dan jarak itu makin diperparah oleh kebijakan yang tidak melibatkan mereka secara bermakna.
Pendidikan bukan sekadar angka
Yang hilang dari sistem pendidikan kita bukan hanya fasilitas, melainkan juga cara kita memaknai pendidikan. Kita terlalu fokus pada angka, nilai ujian, indeks prestasi, peringkat sekolah.
Padahal, pendidikan adalah ruang tumbuh—tempat membentuk karakter, empati, dan keberanian berpikir. Ia bukan pabrik sertifikat, melainkan laboratorium kehidupan sosial.
Kita juga lupa bahwa guru bukan makhluk sempurna. Mereka adalah manusia biasa, warga negara yang juga memikul beban ekonomi dan sosial.
Kita lupa bahwa anak-anak bukan obyek evaluasi, tetapi subyek yang hidup, dengan dinamika psikologis yang kompleks. Kita lupa bahwa sekolah bukan panggung unjuk prestasi, melainkan komunitas belajar.
Menjadikan sekolah ruang publik yang sesungguhnya
Jika kita ingin pendidikan yang lebih adil, kita harus mulai dari membangun kembali sekolah sebagai ruang publik, bukan ruang konsumsi. Hal ini berarti memulihkan kepercayaan antara orang tua, guru, dan negara. Hal ini berarti memperkuat partisipasi warga dalam pendidikan, tanpa menjadikannya proyek individualistik.
Baca juga Pendidikan sebagai Seni Pembudayaan
Pertanyaannya kini apakah kita siap memperlakukan sekolah sebagai milik bersama dengan semua tantangan dan kerumitannya? Ataukah kita akan terus menyerahkan pendidikan pada logika pasar hingga yang tersisa hanya mereka yang mampu membeli masa depan?
Sekolah bisa menjadi tempat di mana kita merawat masa depan bersama. Tapi itu hanya bisa terjadi jika kita mulai merawat sekolah itu sendiri dengan kepercayaan, kesabaran, dan solidaritas.