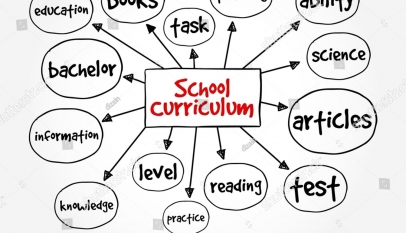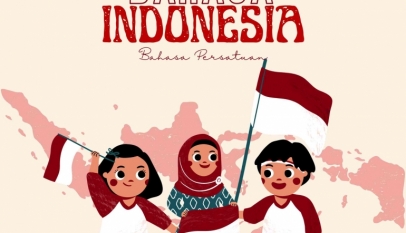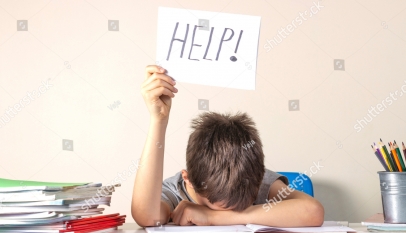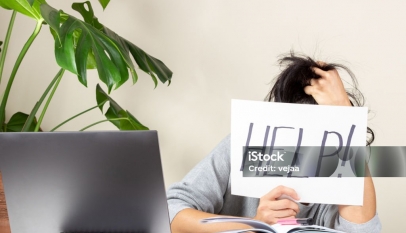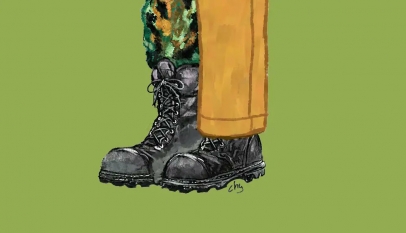Memperhatikan Ruang Aktual Pendidikan
Oleh: Anggi Afriansyah,
Peneliti Sosiologi Pendidikan Pusat Riset Kependudukan BRIN
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Pergantian kepemimpinan selalu membawa harapan sekaligus kecemasan baru.
Ketika memasuki era pemerintahan baru, selalu ada pertanyaan yang perlu diajukan: bagaimana fokus kebijakan yang menjadi prioritas? Apa saja perbaikan pendidikan menjadi target utama, dan tentu saja apakah setiap janji kampanyenya akan ditunaikan secara tuntas?
Tentu kita menunggu dengan saksama, apalagi Presiden Prabowo selalu menyatakan bahwa pendidikan merupakan prioritas yang paling tinggi. Selain itu, komitmen Prabowo-Gibran untuk berinvestasi dalam pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi sebagai upaya untuk memperkuat kemandirian bangsa terekam dalam janji kampanye yang mereka sampaikan.
Baca juga Pemuda Bela Negara dan Indonesia Emas 2045
Bicara pendidikan, sains, dan teknologi tidak mungkin meninggalkan sisi manusia. Manusia Indonesia seperti apa yang akan menggerakkan bangsa ini ke depan sangat bergantung pada kekokohan pemerintah memperhatikan ruang pendidikan.
Dan, gerak ruang pendidikan sangat bergantung pada tata kelola pendidikan yang memperhatikan kebutuhan pendidikan berbasis pada konteks demografi, geografi, dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Maka, penting bagi pembuat kebijakan memahami dengan presisi kompleksitas ruang pendidikan memperhatikan aspek demografi, geografi, dan sosial budaya di Indonesia.
Pertama, dengan memperhatikan aspek demografi, maka kebijakan pendidikan, meminjam istilah Harper (2018), memperhatikan antara karakteristik statis dan proses dinamis lingkungan sosial, ekonomi dan budaya di mana penduduk berinteraksi.
Baca juga Hari Santri dan Pemimpin Baru Indonesia
Dengan demikian pemerintah memperhatikan komposisi usia, jenis kelamin, status perkawinan, distribusi spasial, etnis, dan kelompok sosial ekonomi di setiap daerah sebelum merumuskan intervensi di bidang pendidikan. Perhatian kepada aspek demografi juga memperhatikan distribusi penduduk yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (Mantra, 2015).
Kedua, aspek geografis berarti memperhatikan kontur suatu wilayah, misal terkait dengan wilayah kepulauan, pegunungan, daratan, pantai, pertanian, atau perdesaan dan perkotaan. Riset Symaco (2013) di Filipina, misalnya, dapat menjadi gambaran betapa wilayah-wilayah terpencil dan wilayah yang rentan konflik memiliki permasalahan dengan akses pendidikan dan layanan dasar lainnya jika dibanding dengan wilayah perkotaan.
Perhatian pada Indonesia yang berbasis negara kepulauan juga menjadi hal mendasar sehingga desain pendidikan yang memperhatikan situasi tersebut tidak dapat ditawar lagi.
Baca juga Kewarasan Guru
Untuk wilayah Papua, misalnya, masih mengalami situasi pendidikan yang jauh dari harapan. Studi tim LIPI (2019) menemukan dua persoalan mendasar dalam pendidikan di Tanah Papua. Pertama, persoalan struktural terkait dengan regulasi, tata kelola, anggaran, dan program-program pendidikan belum responsif terhadap kondisi geografis, demografi, sosial budaya Orang Asli Papua. Kedua, tantangan sosial kultural terkait identitas budaya yang beragam, pemenuhan hak yang terkendala kondisi geografis, keterbatasan belajar, dan pendidikan yang tidak relevan dan tidak membangun imajinasi, berbasis kearifan lokal dan pengembangan diri.
Ketiga, memperhatikan aspek sosial budaya atau dalam bahasa Ki Hajar Dewantara, berbasis nasional-kulturil Indonesia. Artinya, pemerintah tidak membangun pendidikan yang seragam dalam program, kurikulum dan arah (M Sjafei, 1956).
Dalam konteks ini bias pembuat kebijakan untuk lebih memprioritaskan konteks global sering sekali terjadi. Misalnya dari segi kompetensi, para siswa ditarget untuk memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh pasar kerja global seperti daya kritis, kemampuan berkompetisi dan berkolaborasi, atau keterampilan di bidang teknologi.
Baca juga Dibutuhkan Negarawan
Hal tersebut tentu tidak dapat dibantah. Namun, dalam konteks Indonesia memerlukan penyesuaian-penyesuaian terutama di ruang aktualisasi sehingga apa yang disampaikan di ruang pendidikan dapat relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat, dan terutama kesiapan infrastruktur pendidikan dan pengajar yang memang sesuai dengan target yang dituju.
Tak elok jika berharap anak-anak meraih kecakapan global, tetapi meninggalkan budaya bangsanya sendiri. Ditambah jika target pendidikan yang dituju tinggi, tetapi intervensi yang diberikan amat terbatas tentu tidak banyak hal yang dapat diperoleh secara optimal.
Ruang aktual
Salah satu catatan yang perlu diingat adalah jangan sampai terjadi tambal sulam kebijakan pendidikan juga terjadinya ketidaksinambungan dari periode ke periode (Ball, 2008). Ada fenomena menarik dalam konteks kebijakan 20 tahun terakhir. Jika memperhatikan dokumen-dokumen kebijakan pendidikan, tampak sekali kita gemar membuat berbagai peta jalan pendidikan.
Jika diinventarisasi secara cepat ada berbagai peta jalan pendidikan (pendidikan karakter, vokasi, SMK, perguruan tinggi) baik yang dirilis oleh lembaga-lembaga pemerintahan atau yang bekerja sama dengan lembaga donor internasional. Yang paling terbaru adalah peluncuran peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2025-2045. Menariknya, di tahun 2020 juga dirilis peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2020-2035.
Baca juga Merdeka, Belajar, Merundung
Lalu apakah sesungguhnya kita surplus peta jalan pendidikan, tetapi luput memastikan bahwa kita bersama dapat mematuhi dan merealisasikan setiap langkah secara perlahan pada setiap rute yang disediakan dalam peta tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan?
Juga menjadi pertanyaan, apakah peta jalan tersebut sudah saksama disusun secara dialogis melibatkan berbagai pihak yang memang memiliki kekuatan struktural dan kultural di bidang pendidikan? Apakah penyusunan peta jalan tersebut juga melibatkan pihak-pihak yang marjinal, mereka yang biasanya jadi target pemajuan pendidikan tetapi selalu tertinggal gerbong pendidikan?
Sebab, jika meminjam pemikiran Freire (2008) dalam teori tindakan dialogis, para pelaku (dalam konteks ini seluruh pihak dalam ekosistem pendidikan) berkumpul dalam kerja sama untuk mengubah dunia (pendidikan) dengan tidak saling memaksakan, tidak menjinakkan, dan tidak berslogan. Poin utama yang diajukan adalah para pemimpin (bidang pendidikan) harus percaya pada potensi rakyat/masyarakat dan tidak boleh memperlakukan mereka sebagai obyek tindakan (kebijakan pendidikan).
Baca juga Kemerdekaan dan Pendidikan
Sebab, sudah mafhum secara aktual, masyarakat marjinal selalu ada di pinggiran kebijakan pendidikan. Hingga akhirnya kebutuhan dan masalah aktual pendidikan mereka cenderung kurang mendapat perhatian. Kebijakan pendidikan pun serba bias kelas menengah atas dan timpang.
Tak pernah salah jika lagi-lagi kembali kepada pikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa ”kita harus mengadakan pendidikan yang sesuai dengan hidup kita dan perikehidupan kita sendiri”. Jika tidak ada dialog, tidak saling percaya, dan menguatkan maka setiap orang menempuh peta jalannya masing-masing, dan kondisi ini tentu lebih menguntungkan kelompok berpunya sebab pada diri mereka terangkum semua kapital yang dibutuhkan untuk maju menjulang.
Apple (2012) dalam Education and Power menegaskan, betapa krisis kehidupan itu bukan fiksi melainkan sesuatu yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari di dunia kerja, sekolah, keluarga, dan pemerintah. Sehingga, soal pendidikan lagi-lagi, bukan perkara individu sebab sangat bergantung kepada bangunan struktural pemerintah dalam membuat, menyebarkan, dan menerapkan kebijakan dan sangat berhubungan dengan isu politik dan budaya (Apple, 2012).
Baca juga Proklamasi Kemerdekaan yang Sarat Makna
Jika menyimak paparan Domina, Gibss, Nun, dan Penner dalam Education and Society (2019), pendidikan formal menjadi bagian penting untuk perkembangan identitas sosial, memengaruhi pengalaman di pasar kerja, dan juga pengalaman personal seseorang terkait dengan keputusan pernikahan, pembentukan keluarga, serta kesehatan dan harapan hidup. Maka, sudah jelas bahwa perhatian pendidikan, meminjam ungkapan Ki Hajar Dewantara, yang dilakukan penuh keinsafan dan ditujukan ke arah keselamatan dan kebahagiaan manusia menjadi penting diutamakan.
*Artikel ini telah tayang di laman detik.com edisi Kamis 31 Oktober 2024