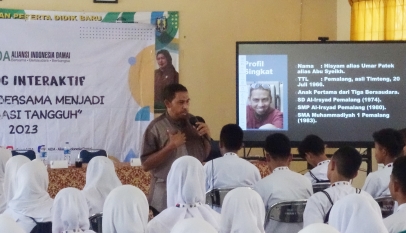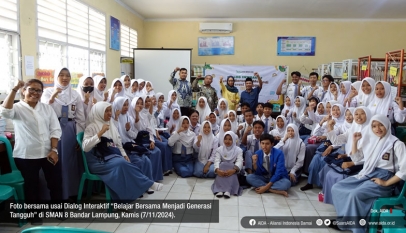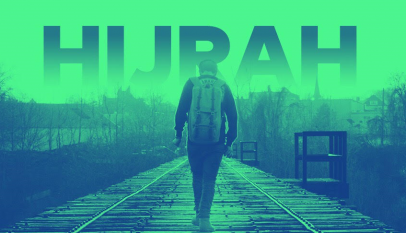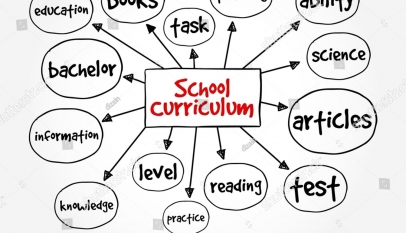Terorisme, Anarkisme, dan Deradikalisasi (2)
Oleh Hasibullah Satrawi
Alumnus Al Azhar Kairo Mesir, Pengamat Politik Timur Tengah dan Dunia Islam
Persoalan kedua adalah anarkisme. Persoalan ini mungkin terlihat ada kemiripan dengan terorisme mengingat sama-sama menggunakan kekerasan dalam menjalankan perjuangannya. Namun, anarkisme sejatinya beda dengan terorisme. Dalam hal kekerasan yang dilakukan, kelompok anarkis atau intoleran lebih menggunakan cara-cara konvensional, seperti pelemparan batu, bambu runcing, atau hal-hal konvensional lainnya. Pun demikian dengan sasaran aksinya. Pada umumnya kelompok intoleran menyasarkan aksinya pada tempat-tempat maksiat, penjual minuman keras, ataupun tempat-tempat lain yang dianggap menjadi tempat perbuatan yang dilarang oleh Allah.
Meski demikian, secara jumlah kelompok seperti ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan kelompok teroris mengingat kekerasan di wilayah ini acap melibatkan para pihak yang tergabung dalam sebuah ormas dengan struktur lengkap hingga ke banyak daerah. Bahkan, ormas yang ada secara resmi terdaftar sebagai organisasi yang legal dalam sistem hukum Indonesia.
Baca juga Terorisme, Anarkisme, dan Deradikalisasi (1)
Sebagaimana kelompok teroris, aksi kekerasan oleh kelompok ini juga menjadi persoalan. Walaupun kerap dilakukan atas nama melindungi masyarakat, kekerasan yang dilakukan tak bisa dibenarkan. Minimal karena perbuatan itu masuk dalam kategori tindakan kekerasan dan melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan Perppu No 2/2017 tentang Ormas (Pasal 59 poin 3 huruf c dan d). Secara spesifik dan definitif, kelompok ini dapat disebut dengan istilah anarkisme daripada radikalisme.
Dalam konteks NKRI dan Pancasila, kelompok teroris dipastikan bersikap anti dan tak mau mengakui mengingat Pancasila dan NKRI dianggap sebagai sistem thaghut. Tunduk dan menerima NKRI sama dengan tunduk dan menerima thaghut yang dianggap merusak keimanan mereka. Sementara kelompok anarkisme tak semua anti terhadap NKRI dan Pancasila walaupun sebagian dari mereka ada yang berjuang secara nonkekerasan untuk mengganti NKRI dengan sistem pemerintahan khilafah.
Deradikalisasi
Sebagaimana istilah radikalisme bersifat problematis karena cenderung liar dan subyektif, istilah deradikalisasi sejatinya mengandung problem lebih kurang sama. Sebelum jadi bahasa hukum, istilah deradikalisasi bisa dipahami sebagai upaya membuat seseorang tidak menjadi radikal. Belakangan, istilah deradikalisasi menjadi bahasa hukum seiring disahkannya UU No 5/2018 sebagai revisi atas UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Dalam UU ini, deradikalisasi didefinisikan sebagai ”Suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi” (Pasal 43D, Ayat 1). Deradikalisasi dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, dan orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme (Pasal 43D Ayat 2) melalui empat tahapan: identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, reintegrasi (Pasal 43D Ayat 4).
Baca juga Bunuh Diri dan Terorisme
Dengan pengertian seperti di atas, obyek deradikalisasi adalah mereka yang sudah terpapar paham radikal terorisme (meminjam istilah yang digunakan dalam UU ini). Sementara upaya deradikalisasi di kalangan masyarakat luas yang belum terpapar tidak disebut dengan istilah deradikalisasi, tetapi kontraradikalisasi (Pasal 43C). Konsepsi deradikalisasi yang sekarang telah menjadi bahasa hukum ada kemiripan dengan program deradikalisasi yang dikembangkan dan dijalankan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), khususnya pada masa-masa awal (sekitar 2013). Dugaan penulis, konsep deradikalisasi yang saat ini jadi salah satu norma dalam UU No 5/2018 diadopsi dan dikembangkan dari program deradikalisasi BNPT di atas.
Jika ini benar, pengadopsian konsep deradikalisasi dari bahasa program jadi bahasa hukum mengandung keistimewaan sekaligus kelemahan. Keistimewaan karena segala prosesnya telah menjadi norma hukum yang harus dijalankan para pihak. Menjadi kelemahan karena, dengan demikian, deradikalisasi sebagai sebuah proses mengalami sebentuk pembakuan dengan kekakuan tertentu pada tingkat tertentu pula.
Baca juga Peta Terorisme Pasca-Baghdadi
Berdasarkan pengalaman penulis beberapa tahun terakhir terkait upaya membangun perdamaian, baik di dalam maupun di luar lapas, dibutuhkan adanya energi sangat besar dengan segala kehati-hatian, kelenturan, dan keberanian dalam menghadapi mereka yang terpapar paham ekstrem sekaligus mendukung setiap perubahan yang dialami oleh mereka (akibat pendekatan tertentu), sekecil apa pun. Tentu semuanya dengan tetap berpegang teguh pada prinsip akurasi, koordinasi, dan partisipasi semua pihak, mulai dari aparat keamanan, petugas lapas, tokoh agama, peneliti, bahkan hingga para korban aksi terorisme, mengingat hal ini terkait dengan keyakinan orang yang tak otomatis berubah hanya karena dihukum atau bahkan ditembak mati sekalipun.
Visi besar Presiden Jokowi harus dibarengi penggunaan diksi yang tepat sebagai cerminan dari penguasaan masalah yang ada. Pada tahap selanjutnya, pemilihan dan penempatan orang yang tepat sesuai keahlian dan kebutuhan yang ada di lapangan. Terakhir, yang tak kalah penting adalah pengelolaan yang terorganisasi sebagai satu tim untuk memenangkan perdamaian dan mewujudkan Indonesia maju ke depan.
*Artikel ini telah dimuat di harian Kompas edisi Senin, 16 Desember 2019
Baca juga Kisah Korban dan Mantan Pelaku: Role Model Rekonsiliasi