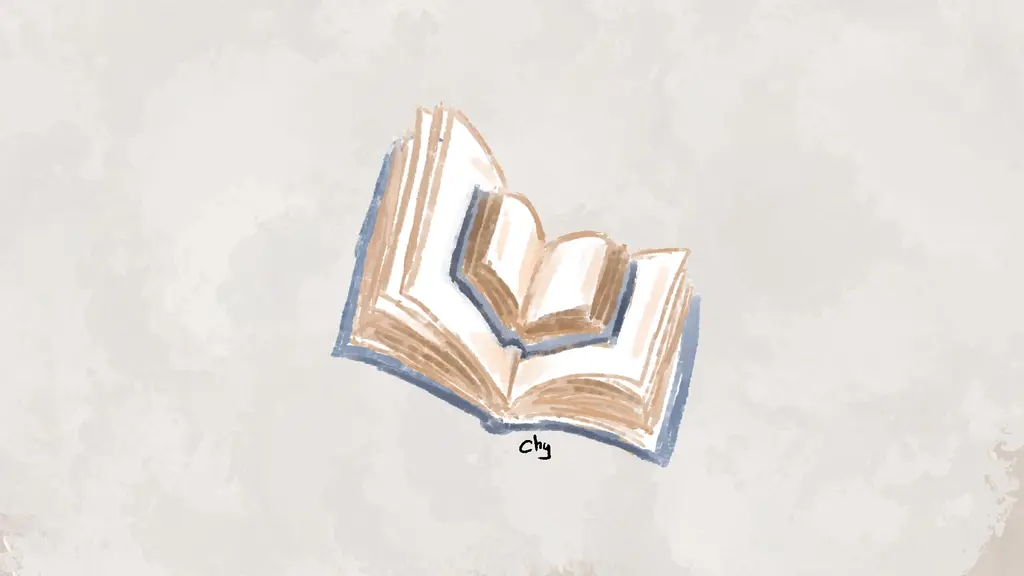Kekerasan Budaya
Oleh: Idi Subandy Ibrahim
Peneliti Budaya, Media, dan Komunikasi. Pengajar Pascasarjana Universitas Pasundan.
Akhir-akhir ini fenomena kekerasan dan tayangan kekerasan sudah seperti polusi udara panas kehidupan kita memasuki abad ke-21. Sekalipun kekerasan sudah setua peradaban manusia, baru pada pergantian abad ini limpahan visualisasi kekerasan dengan bebas membanjiri ruang privasi seperti lewat televisi dan aneka media sosial.
Teknologisasi dan digitalisasi media membuat banjir informasi kekerasan menjadi menu sajian hiburan dalam genggaman dan ruang keluarga. Kejadian-kejadian di luar nalar kemanusiaan, mulai dari pembulian siswa, kekerasan di sekolah, pemerkosaan, penembakan, pembunuhan berencana, aksi begal di siang bolong, aksi-aksi premanisme dan terorisme, mutilasi dan pembunuhan berantai, hingga kekerasan terhadap binatang, dimediakan dengan rinci dan berulang-ulang serta dibagikan bebas di media sosial.
Kekerasan seperti mimpi buruk! Nurani kita terketuk untuk bertanya: mengapa untuk alasan-alasan yang tampak sederhana orang begitu mudah saling menyakiti bahkan melayangkan nyawa? Mengapa bangsa yang terlihat murah senyum seperti murah nyawa manusia?
Baca juga Manusia Digital dan Ke(tidak)bebasan
Dalam masyarakat yang kian stres dan penerapan hukum yang lemah, kekerasan menjadi bahasa atau alat berucap antarmanusia. Kekerasan bahkan bisa menjadi landasan keberadaan seseorang, kelompok, atau suatu rezim lokal, nasional, dan global. Kekerasan menjadi legitimasi kebudayaan: hidupnya budaya kekerasan menjadi kekerasan budaya, untuk meminjam kata-kata Johan Galtung.
Kekerasan mewujud dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik. Sebutlah, misalnya, dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, penyeragaman merupakan kekerasan terhadap perbedaan: pemerkosaan terhadap potensi keragaman kreativitas anak didik. Penyeragaman membunuh kekayaan bakat manusia, anugerah Tuhan sejak lahir.
Baca juga Pendidikan Tanggung Jawab Bersama
Kekerasan dalam dunia pendidikan juga bisa mewujud dalam bentuk kebijakan komodifikasi pendidikan yang membuat hilangnya kesempatan anak-anak berbakat dari keluarga miskin dan kurang mampu untuk memasuki dunia pendidikan berbiaya tinggi. Hilangnya akses pendidikan adalah kekerasan terhadap asas keadilan yang bertentangan dengan dasar dan falsafah negara kita.
Kekerasan budaya bisa terasa meski tak terlihat, tetapi bisa juga terlihat meski tak terasa langsung. Kekerasan budaya berlangsung karena kekerasan telah mengalami proses internalisasi dalam jangka waktu cukup panjang. Tak heran kalau media sering menyebut bahwa kekerasan di media hanyalah cermin dari kekerasan yang sudah hidup dalam budaya masyarakat.
Baca juga Ruang Merawat Diri
Beberapa waktu lalu berbagai kalangan dibuat tersentak atas peristiwa penembakan yang menewaskan seorang polisi dan kemudian rincian pemberitaan kekerasan mengenainya yang bahkan hampir mencapai titik jenuh.
Peristiwa tragis tersebut mengetuk nurani kita. Apakah kejadian tersebut hanya gejala jiplak-menjiplak seperti kejadian kekerasan yang banyak ditayangkan lewat produk tontonan impor negeri adidaya?
Selama lebih dari 60 tahun, ilmuwan sosial telah meneliti mengenai akibat kekerasan media, termasuk program TV, film, video game, lirik dan video musik, dan internet. Mereka menemukan tiga bukti berbeda mengenai dampak kekerasan media: 1.) Efek penonton: semakin banyak media kekerasan yang Anda lihat, semakin tidak peka Anda terhadap kekerasan di dunia nyata. 2.) Efek agresor: semakin banyak media kekerasan yang Anda lihat, akan semakin agresif Anda. 3.) Efek korban: semakin banyak media kekerasan yang Anda lihat, semakin takut Anda menjadi korban kekerasan.
Baca juga Internalisasi Kerukunan di Tengah Keragaman
Berbagai penelitian menunjukkan bahwa paparan kekerasan media berkontribusi bagi peningkatan kekerasan sosial budaya. Di satu sisi, kekerasan media diyakini meningkatkan agresi, ditandai dengan menurunnya kepekaan manusia terhadap efek dari kekerasan nyata. Kekerasan media awalnya menghasilkan ketakutan, rasa jijik, kecemasan, dan keadaan motivasi untuk menghindarinya. Di sisi lain, paparan berulang terhadap kekerasan media, mengurangi dampak psikologisnya dan pada akhirnya menghasilkan motivasi dan mengarahkan pada peningkatan agresivitas seseorang.
Industri kekerasan di era digital mengomodifikasikan aksi agresi dalam aneka permainan (games) dan tontonan (spectacle) bernuansa kekerasan. Persaingan pemberitaan berorientasi viral membuat sebagian media tergoda logika tabloidisasi kekerasan. Kekerasan sebagai tontonan nyata dan fiksi/fantasi kian mendominasi ruang publik. Kejahatan dan perang menjadi hiburan (horrortainment) pada jam tayang utama, mengisi waktu senggang, dan menyesaki pesan gawai. Komedi situasi yang hendak menghibur tak jarang berisi agresi kata-kata berprasangka pada perempuan dan disabilitas serta masyarakat bawah (pembantu, satpam, sopir, pemulung, tukang sapu, dan lain-lain) sebagai bahan olok-olok.
Baca juga Mencari Celah Kebaikan
Sudah tentu, setiap bentuk kekejian mengiris nurani keadilan dan kemanusiaan kita. Mengapa kekerasan masih saja terjadi ketika sila kemanusiaan yang adil dan beradab hendak kita usung jadi karakter manusia Indonesia? Pandangan bapak psikologi Sigmund Freud (1922) mengenai ”naluri aktif (manusia) untuk membenci dan merusak” seperti melegitimasi akar kekerasan peradaban manusia.
Para psikolog komunikasi telah lama mengkhawatirkan efek media kekerasan seperti desensitisasi (hilangnya kepekaan), imitasi (peniruan), atau sosialisasi (pembelajaran sosial). Setelah bertahun-tahun meneliti kekerasan di berbagai media, dalam School for Violence (1964), Fredric Wertham mengingatkan, pada akhirnya media membuat anak muda bukan hanya terlatih menjadi ”korps perdamaian”, melainkan juga ”korps kekerasan”. Dalam Mind Abuse: Media Violence and Its Threat to Democracy, Rose A Dyson (2021) mengingatkan, ketika rumah dan sekolah mulai tidak menjadi tempat yang ramah dan menyenangkan, beberapa anak akan berpaling ke ”guru-guru” dan ”idola-idola” budaya populer yang tidak hanya menawarkan budaya konsumtif, tetapi juga budaya kekerasan.
*Artikel ini terbit di Kompas.id, 4 Februari 2023
Baca juga Melawan Rasa Takut