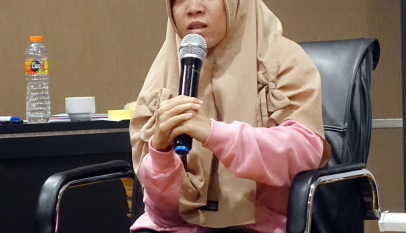Manusia Digital dan Ke(tidak)bebasan
Oleh: Agus Sudibyo
Dosen ATVI Jakarta, Anggota Dewan Penasihat PWI Pusat
Kebebasan di antara pilihan-pilihan yang terbatas dan ditentukan secara eksternal sesungguhnya merupakan simulakra kebebasan.
Sebuah keadaan di mana kita sepertinya menggenggam kebebasan, tetapi sesungguhnya terbelenggu. Kita memiliki otonomi diri sekaligus tersandera kendali pihak lain. Sudut pandang ini sering jadi titik tolak untuk mempersoalkan paham kebebasan memilih dalam konteks pemilu dan kebebasan konsumen membeli produk dalam konteks consumer model of freedom.
Sudut-pandang tersebut juga relevan untuk menyoal paham kebebasan internet (internet freedom). Internet tak terbantahkan lagi telah mengantarkan kita pada semesta informasi, gagasan, dan lingkup pergaulan yang nyaris tak berbatas.
Baca juga Pendidikan Tanggung Jawab Bersama
Dengan lompatan teknologi yang dibawanya, media sosial, mesin pencari, dan media baru lainnya telah memfasilitasi hampir semua orang untuk mengakses informasi, wacana, hiburan, dan kelompok percakapan dalam gradasi dan intensitas yang belum pernah terwujud sebelumnya. Ruang digital menjadi ruang bersemainya bentuk-bentuk ekspresi diri, pemikiran, nilai, dan inovasi untuk hampir semua orang.
Praktis tak ada lagi hierarki yang selama ini berlaku dalam sistem lama (komunikasi, politik, ekonomi, dan lain-lain) serta mengelompokkan masyarakat atas dasar otoritas yang bersumber pada status akademik, intelektual, strata sosial, dan kedudukan formal. Tom Nichols telah mendalilkan matinya otoritas itu dalam buku The Death of Expertise (2017).
Pada era media digital hari ini, setiap orang dapat mengaku diri sebagai jurnalis, narasumber, sekaligus pemilik media. Setiap orang adalah subyek yang bertindak secara ”otonom”. Otonomi itu tidak diletakkan pada status sosial atau posisi politis alih-alih pada jari setiap orang dengan gawai masing-masing.
Baca juga Ruang Merawat Diri
Maka, diktum Cartesian ”aku berpikir maka aku ada” pun telah berubah menjadi ”aku klik maka aku ada”. Dengan ponsel dalam genggaman, dengan jari yang melakukan gerakan klik itu, seakan-akan kita telah menjadi manusia yang bebas bertindak dan mengambil keputusan secara mandiri.
”Digital panopticon”
Hingga saatnya pakar digital seperti Jaron Lenier menyadarkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam dunia virtual kita dan bagaimana hubungan kita dengan kekuatan ekonomi yang menyediakan layanan-layanan digital untuk kebutuhan sehari-hari kita.
Penulis buku You Are Not a Gadget (2010) itu mengingatkan bahwa semakin aktif kita berinternet, semakin dalam kehidupan digital kita terintegrasi dalam ekosistem informasi-komunikasi yang dikendalikan perusahaan teknologi global.
Baca juga Internalisasi Kerukunan di Tengah Keragaman
Dalam ekosistem itu, kita sesungguhnya hidup dengan pilihan-pilihan yang serba terbatas dan diseleksi oleh kode-kode matematis-komputasional yang bekerja secara laten, otomatis, dan tanpa kita sadari.
Platform digital selalu mengawasi apa yang kita lakukan di dunia maya. Mereka selalu merekam apa yang kita cari, yang sering kita klik, dengan siapa kita berjaringan, dan seterusnya. Mereka mengetahui gerak-gerik kita, tetapi kita tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap kita. Dalam konteks inilah belakangan banyak orang menggunakan T-shirt dengan tulisan ”I don’t need Google, my wife knows everything”.
Yang terjadi sebenarnya justru sebaliknya. Google mengetahui lebih banyak tentang diri kita dibandingkan dengan orang terdekat kita sekalipun.
Baca juga Mencari Celah Kebaikan
Manusia digital terjerembap dalam apa yang disebut digital panopticon. Merujuk pada pemikiran Jeremy Bentham dan Michel Foucault, manusia digital ibaratnya hidup dalam kamp konsentrasi raksasa di mana hampir semua yang mereka lakukan diawasi the all-seeing digital eyes, yakni platform digital global.
Mereka telah menanamkan teknologi pengawasan dan penambangan data pada seluruh layanan atau aplikasi digital yang setiap hari mereka pinjamkan kepada pengguna internet di seluruh dunia.
Ternyata tidak ada yang benar-benar gratis dari layanan digital itu. Layanan gratis selalu dibarter dengan penyerahan data diri secara gratis. Maka, semakin aktif kita menggunakan layanan digital itu, sesungguhnya semakin kurang relevan kita berbicara tentang privasi.
Baca juga Melawan Rasa Takut
Jika hingga pengujung tahun 2022 pengguna aktif Facebook di seluruh dunia konon 2,94 juta miliar orang, lebih kurang data dan privasi orang sebanyak itu pula yang dikelola Google.
Maka, terciptalah dunia yang penuh pengawasan dan penambangan data pribadi seperti terangkum dalam istilah digital panopticon. Berbagai penelitian menunjukkan, mayoritas pengguna internet tak menyadari terjadinya praktik pengawasan dan penambangan data itu.
Praktik pengawasan dan penambangan data pribadi yang terjadi secara laten, otomatis, dan terus-menerus itu menghasilkan profil pengguna yang sangat detail. Apa masalah, kebutuhan, hobi, minat, nilai hidup, orientasi politik, dan orientasi religius para warganet terekam dengan begitu detail di sana.
Baca juga Membangun Budaya Damai Melalui Umpan Balik
Surplus data pengguna kemudian diolah untuk menghasilkan surplus prediksi perilaku pengguna. Prediksi perilaku inilah yang kemudian menata jagat digital kita.
Seperti dijelaskan Lenier, tidak ada yang benar-benar alamiah dan terjadi secara kebetulan dalam jagat digital kita.
Informasi apa yang kita akses, musik atau film apa yang kita nikmati, pandangan ideologis yang terpaparkan di beranda media sosial, dengan siapa kita berkawan, kelompok percakapan mana yang kita ikuti, lebih kurang telah terkurasi dan tertata berdasarkan prediksi perilaku pengguna.
Baca juga Membangun Komunikasi Damai
Sistem algoritma di sini membantu kita menggeluti hal-hal yang kita minati dan mengabaikan hal-hal lain. Namun, konsekuensinya adalah kita terperangkap dalam lingkup ketertarikan, sudut pandang, dan pilihan informasi yang ”itu-itu saja”.
Suatu keadaan yang umumnya tak disadari pengguna internet, tetapi menentukan bagaimana mereka bersikap dan membuat keputusan. Kita menggenggam kebebasan untuk memilih di antara pilihan-pilihan yang sesungguhnya terbatas dan terberi secara algoritmis.
Lebih serius lagi ketika keputusan dan sikap itu terkait kepentingan orang banyak. Misalnya sikap politik dalam pemilu, penerimaan terhadap fakta kemajemukan atau cara pandang terhadap kemanusiaan.
Baca juga R20: Catatan dari Forum Perdamaian Dunia ke-8 di Solo
Yang kita hadapi dalam hal ini terutama sekali bukanlah cakrawala pemikiran, nilai, dan informasi yang luas dan terbuka, melainkan paparan gagasan, informasi, dan nilai yang telah terkurasi secara algoritmis. Dalam cakrawala yang terberi itulah, kita notabene membangun preferensi pribadi tentang keyakinan religius, pandangan ideologis atau artikulasi politik.
Permasalahannya adalah preferensi tersebut tidak kita bangun dengan sikap yang terbuka, alih-alih dengan sikap reaktif terhadap perbedaan pandangan. Kita cenderung hanya mau menerima argumentasi yang memperkuat keyakinan kita dan mengabaikan argumentasi yang lain. Kita cenderung hanya mau berteman dan berdiskusi dengan orang-orang yang segaris pemikiran.
Hal yang tumbuh subur di sini adalah kelompok percakapan yang searah dan arus informasi yang tertentu. Keduanya kurang merangsang kebebasan berpikir dan dialog antar-pemikiran yang sesungguhnya sangat fundamental dalam masyarakat yang pluralistis.
Baca juga R20: Fikih Toleransi dan Rekonsiliasi Konflik
Aporia demokrasi digital?
Meminjam istilah Lenier, sistem algoritma telah menjadi the master of context for humanity. Rumus-rumus algoritmis tak diragukan lagi sangat membantu manusia dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis.
Namun, menjadi sangat problematis jika rumus-rumus tersebut juga diterapkan pada hal-hal yang memengaruhi bahkan membentuk ulang segi-segi kemanusiaan, moralitas, dan keadaban bermasyarakat kita.
Apa boleh buat, inilah yang sedang menggejala dalam kehidupan kita belakangan. Sedang berlangsung proses pengarusutamaan penerapan teknologi kecerdasan buatan di berbagai bidang tanpa antisipasi yang memadai atas risiko-risiko sistemisnya. Kita sedang terpesona oleh prinsip personalisasi, otomatisasi, robotifikasi produksi, dan distribusi konten tanpa memperhitungkan benar apa dampaknya jika konten tercerabut dari konteks, akar-masalah, dan landasan epistemologis yang melingkupinya.
Baca juga Mazhab Pembinaan versus Mazhab Penjeraan
Apa yang dapat disimpulkan untuk sementara ini? Di era supremasi algoritma hari ini, manusia digital menikmati kebebasan sekaligus terisolasi dalam ruang kehidupan yang terberi. Kita menggenggam otonomi diri sekaligus terdikte oleh tangan-tangan yang tak tampak. Kita sedang menghadapi aporia demokrasi digital.
Digitalisasi memberikan peluang yang individu lepas dari struktur kekuasaan yang menindas dan otoriter. Ada banyak kasus yang sering menjadi rujukan di sini dan Musim Semi Arab menjadi contoh utama.
Namun, digitalisasi juga telah menghadapkan kita pada jenis kekuasaan yang baru. Jenis kekuasaan yang sama sekali tidak menyeramkan, tidak berwajah bengis, dan menakut-nakuti dengan moncong senjata. Mereka adalah sang kapitalis baik hati, yang selalu memberikan kegembiraan kepada kita melalui rupa-rupa layanan dan kemudahan yang saban hari bisa kita akses dengan begitu mudah.
Baca juga Muktamar Muhammadiyah dan Nasionalisme Indonesia
Dan Schiller (2000) menyebutnya sebagai kapitalisme digital (digital capitalism). Sulit untuk berkata ”tidak” terhadap kapitalisme jenis ini karena seperti terangkum dalam istilah freenemy, mereka pembawa masalah sekaligus pemberi solusi, pengendali sekaligus pembebas, pencipta belenggu sekaligus pembawa peluang untuk menghadapi belenggu.
Terhadap kekuasaan kapitalisme digital itu, yang perlu kita bangun adalah sikap kritis dan berjarak. Pada setiap layanan atau teknologi yang mereka tawarkan, sesungguhnya selalu terselip motif ekonomi dan pengawasan digital. Menangkap motif ini sangat penting.
Bukan karena kita harus serta-merta menolak tawaran-tawaran tersebut, melainkan karena kita mesti mampu membedakan benar antara memanfaatkan teknologi atau diperbudak oleh teknologi. Tidak pelak lagi kemampuan inilah yang menentukan kadar kebebasan kita di era supremasi algoritma saat ini.
*Artikel ini terbit di kompas.id, Senin, 30 Januari 2023
Baca juga Politik Identitas Keindonesiaan