Terorisme, Anarkisme, dan Deradikalisasi (1)
Oleh Hasibullah Satrawi
Alumnus Al Azhar Kairo Mesir, Pengamat Politik Timur Tengah dan Dunia Islam
Sebagai presiden terpilih, Jokowi menyatakan akan memberi perhatian pada penyelesaian isu radikalisme dalam periode pemerintahan keduanya.
Ini salah satu visi besar yang kontekstual untuk masa sekarang. Visi besar tentu memiliki tantangan tak kalah besar. Sebagai langkah awal, beberapa kementerian yang selama ini tak terlalu masuk dalam penanganan masalah radikalisme mulai didorong berperan secara lebih aktif. Bahkan, deradikalisasi menjadi salah satu tugas khusus Menko Polhukam Mahfud MD.
Persoalannya, sebagai sebuah masalah, radikalisme belum jadi rumus yang dimafhumi semua pihak, alih-alih disepakati. Radikalisme pun acap jadi konsepsi liar, multitafsir, dan cenderung jadi ”penghakiman” ke pihak lain sekaligus ”pembersih” untuk diri sendiri. Bahkan, belakangan jadi kontroversi. Sebagian pihak menggunakan istilah radikalisme, padahal yang dimaksud adalah terorisme. Sebagian lain menggunakan istilah radikalisme untuk merujuk problem intoleransi, anarkisme, serta penolakan pada Pancasila dan NKRI.
Baca juga Bunuh Diri dan Terorisme
Masih banyak lagi kemungkinan lain sebagai bentuk rumusan subyektif radikalisme, termasuk bentuk pakaian dan ekspresi tertentu. Ketika istilah radikalisme jadi kontroversi, beberapa persoalan riil yang tak secara mufakat disebut dengan istilah radikalisme justru kian akut.
Pelbagai macam aksi kekerasan (dari penusukan hingga pengeboman) sebagai salah satu inti persoalan justru kian tak terkendali makan korban dari kalangan masyarakat sipil hingga aparat. Di sini dapat ditarik kesimpulan awal, di balik kontroversi istilah radikalisme, ada kegagalan mendefinisikan beberapa inti persoalan secara tepat, akurat, dan disepakati bersama.
Terorisme
Persoalan pertama adalah terorisme. Merujuk UU No 5/2018, terorisme didefinisikan ”Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan” (Pasal 1 Ayat 2).
Dengan definisi itu, cakupan terorisme sudah sangat jelas. Sejatinya terorisme tak boleh diperluas menjadi radikalisme yang cenderung liar dan subyektif mengingat definisi itu telah memberikan gambaran yang sangat jelas, termasuk motifnya; ideologi, politik, dan gangguan keamanan.
Baca juga Peta Terorisme Pasca-Baghdadi
Terlebih lagi ketentuan selanjutnya dalam UU ini tak hanya membatasi persoalan terorisme pada aksi pengeboman ataupun penyerangan (aksi kekerasan), tetapi juga peran dan keanggotaan seseorang dalam sebuah organisasi teror, di dalam maupun di luar negeri (Pasal 12 A). Bahkan, juga termasuk pelatihan militer (Pasal 12B).
Hal yang jamak disalahpahami banyak pihak selama ini adalah bahwa terorisme seakan selalu berangkat dari radikalisme (dalam hemat penulis, istilah yang lebih tepat adalah anarkisme atau intoleran) ataupun radikalisme selalu berakhir dengan terorisme. Padahal, yang terjadi di lapangan tak selalu demikian. Sebagian orang jadi teroris tanpa melalui proses radikalisme, sebaliknya tak selalu orang yang disebut radikal menjadi teroris.
Adalah benar bahwa ada sebagian orang yang jadi teroris setelah mengalami radikalisasi. Namun, hal ini terlalu kecil kasusnya untuk dijadikan sebagai rumus paten bahwa seorang teroris harus melalui radikalisasi ataupun orang yang radikal pasti menjadi teroris. Singkat kata, hal-hal yang terkait dengan terorisme bersifat spesifik, tak bisa diperluas ke wilayah lain. Dalam hal aksi kekerasan yang dilakukan, contohnya, kelompok teroris kerap menggunakan cara-cara nonkonvensional, seperti pengeboman, penembakan, bahkan taktik perang kota.
Baca juga Kisah Korban dan Mantan Pelaku: Role Model Rekonsiliasi
Hal lebih kurang sama juga terjadi dalam konteks doktrin. Kelompok teroris memiliki jenis doktrin spesifik yang tak dimiliki kelompok lain yang selama ini dianggap radikal. Dalam hal pengafiran, contohnya, kelompok teror tak hanya melakukan pengafiran secara umum, tetapi sampai tahap pengafiran secara spesifik (takfir mu’ayyan), seperti vonis kafir yang dijatuhkan kepada aparat keamanan yang dianggap sebagai anshar thaghut (penolong thaghut) dan anggota DPR yang dianggap merampas hak legislasi (tasyri’) dari Allah. Bahkan, sebagian kelompok teroris (khususnya yang bergabung dengan NIIS) sampai pada tahap tidak mau makan daging yang dijual di pasar karena keislaman orang yang menyembelih diragukan atau bahkan telah dianggap kafir.
Secara jumlah, kelompok teroris seperti ini bisa dibilang sedikit. Menurut beberapa sumber di lapangan, saat ini terdapat sekitar 600 orang yang dipenjara karena persoalan terorisme. Walaupun, misalkan, angka ini diperbesar menjadi 700-an (dengan penangkapan pasca-penusukan Wiranto dan bom Medan) atau bahkan 2.000 (dengan mereka yang sudah bebas) atau bahkan 20.000 sekalipun, itu tetap sedikit sebagai sebuah jumlah, khususnya jika dibandingkan populasi penduduk Indonesia. Namun, dilihat dari sadisme dan kekerasan yang dilakukan, kelompok ini tak bisa dianggap remeh. Apalagi, mereka memiliki militansi dan orientasi hidup berbeda; kebanyakan orang takut mati, tetapi kelompok teroris justru berani mati. Kelompok ini secara spesifik dan definitif bisa disebut dengan istilah terorisme daripada radikalisme.
*Artikel ini telah dimuat di harian Kompas edisi Senin, 16 Desember 2019
Baca juga Negara dan Kompensasi Korban Terorisme




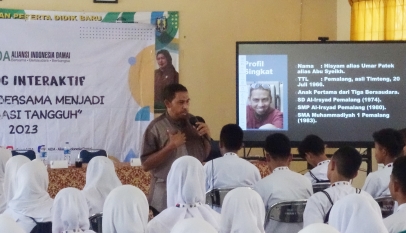

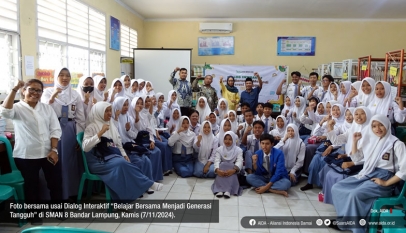
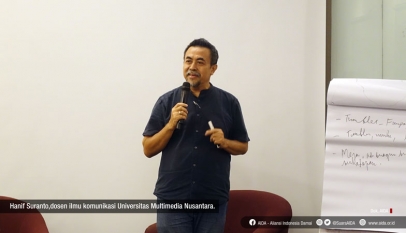
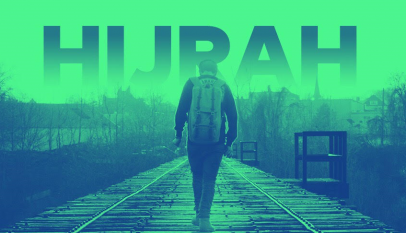


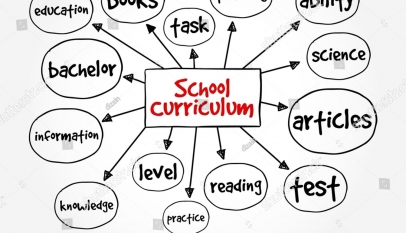

1 Comment