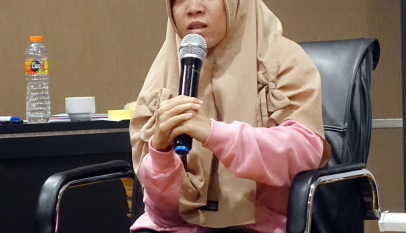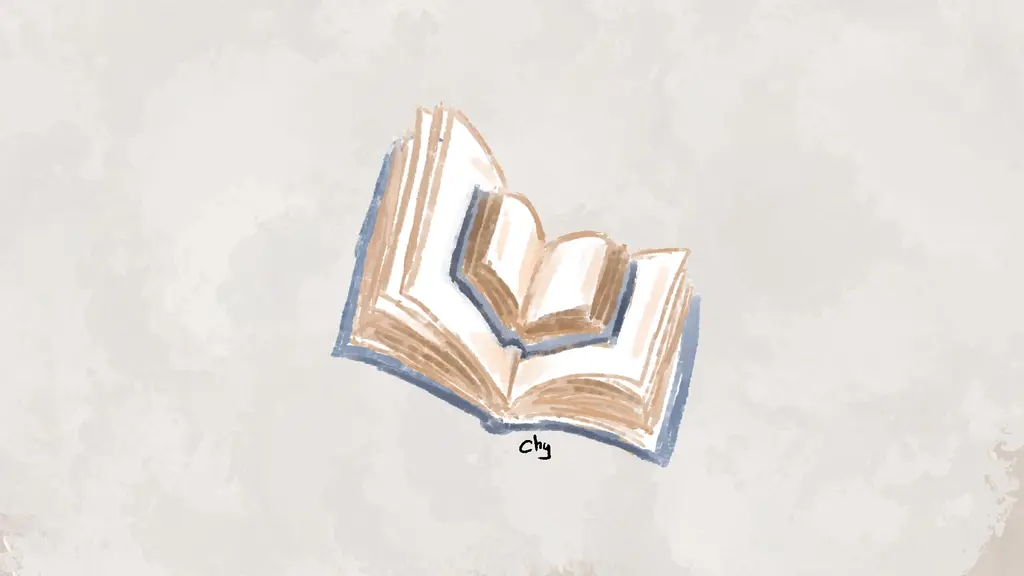Efek Sorotan
Oleh: Alissa Wahid
Saat sedang menyusuri jagat maya, sering sekali kita disodori berita tentang para pesohor dan juga para pemengaruh (influencers). Kelompok kedua ini biasanya orang-orang yang menjadi terkenal melalui media sosial, baik karena kepakaran tematis mereka maupun karena aksi-aksi yang dibuatnya.
Teknologi informasi dan media sosial menciptakan egalitarianisme dalam akses informasi. Siapa saja dapat menjadi sumber informasi dalam topik apa saja. Setiap orang dapat menerima informasi tanpa batas dari siapa saja yang menarik perhatian mereka.
Baca juga Akhlak Mulia
Salah satu dampaknya adalah fenomena matinya kepakaran (the death of expertise) yang dipopulerkan Tom Nichols. Para pakar yang menguasai pengetahuan atau topik tertentu menjadi kalah pengaruh dibandingkan dengan orang awam yang piawai dalam media sosial. Contoh paling kuat di Indonesia adalah para pemuka agama yang berilmu tinggi banyak dikalahkan oleh para pesohor media sosial yang mengajarkan agama walaupun tidak memiliki keilmuan yang memadai.
Di sisi lain, para artis yang tidak memiliki akses kepada industri seni dapat menampilkan dirinya di media sosial dan platform internet dan menemukan panggungnya di jagat maya. Salah satu contohnya adalah Alip Ba Ta, sosok yang memukau dunia melalui permainan gitarnya. Atau para MUA (make-up artist) yang bermunculan menjadi influencers media sosial senyampang menguatnya industri kecantikan.
Baca juga Ki Hadjar dan Engku Syafei, Inspirator Kemerdekaan dari Ruang Kelas
Demikian juga para crazy rich yang awalnya tidak dikenal, tetapi berkat media sosial dapat memamerkan kekayaan dan gaya hidup hedonistik mereka. Bahkan, hal ini menjadi salah satu media promosi investasi bodong, seperti yang kita lihat beberapa waktu lalu.
Cukup banyak masyarakat yang tergiur dengan gaya hidup serba mewah dan nyaman seperti itu sehingga tergerak berinvestasi yang menjanjikan cara mudah dan cepat. Ujungnya, publik pun tertipu.
Peluang terkenal dan mendapatkan keuntungan materi melalui media sosial memang sangat besar. Walhasil, banyak orang ”biasa” dari sudut-sudut Indonesia pun membanjiri media sosial dan platform internet lainnya dengan kreasi konten-konten yang beraneka warna. Bahkan, kadang dibuat sebombastis mungkin, menabrak kelaziman dan bahkan etika, dengan alasan demi konten.
Baca juga ”Overthinking”
Sejatinya, setiap orang memiliki keyakinan bahwa orang-orang di sekitar memiliki perhatian berlebih kepada dirinya. Ini biasanya membuat orang menjadi lebih sadar diri dan menahan diri. Padahal, kenyataannya, publik di sekitarnya tidak terlalu memperhatikan. Demikian kesimpulan sebuah penelitian pada 1999 oleh psikolog Tim Gilovich.
Fenomena ini disebut Spotlight Effect (Efek Sorotan), seakan kita berada di bawah lampu sorot yang terang benderang dan membuat semua orang dapat melihat kita secara utuh. Ini adalah salah satu bentuk bias kognitif, di mana kita merasa poros dunia adalah kita. Kita menjadi lebih hati-hati dalam menampilkan diri di ruang publik. Padahal, setiap orang merasa demikian pula.
Baca juga Islam Indonesia Berkelanjutan
Menariknya, di Indonesia, khususnya di jagat maya, justru yang terjadi sebaliknya. Kesadaran efek sorotan ini justru membuat banyak orang memanggungkan dirinya untuk mendapatkan perhatian publik. Insentifnya jelas: penghasilan dan popularitas. Karena itu, muncul juga fenomena narsis yang disematkan kepada para pesohor media sosial atau mereka yang beraspirasi menjadi pesohor.
Berhubung masyarakat Indonesia tidak membedakan urusan pribadi dengan urusan publik, muncullah dampak lain, yaitu keingintahuan yang besar mengenai seluruh detail aspek kehidupan si pesohor. Semisal kasus-kasus konflik keluarga seorang pemengaruh gaya hidup dan kecantikan. Dan ini ditangkap oleh penyedia jasa informasi berbasis platform internet melalui kecerdasan artifisial (AI) sehingga berita-berita mengenai para pesohor ini berhamburan di jagat maya.
Baca juga Merawat Kebangsaan
Seluruh fenomena ini menciptakan banyak tantangan baru. Berbagai jebakan psikososial pun menguat dalam skala yang mengkhawatirkan. Semisal kecenderungan untuk faking good alias berpura-pura menampilkan sesuatu yang sebetulnya tidak dilakukan di dunia nyata. Akibatnya, masyarakat kita dapat bergeser menjadi masyarakat munafik.
Gambaran di media sosial yang selalu indah, misalnya kemesraan pasangan pesohor yang bertagar #relationshipgoal, atau perjalanan dengan pesawat privat, dan lain-lain, berkembang menjadi impian rakyat jelata di Indonesia.
Baca juga Otonomi bagi Anak
Bahkan, ketika impian tersebut berjarak demikian jauh dari kenyataan, atau terbukti sang pesohor hanya berpura-pura demi konten, masyarakat tetap bertahan pada impian tersebut. Akibatnya, sebagian anggota masyarakat kita pun menjadi masyarakat yang tidak realistis.
Padahal, cepat atau lambat, sering kali kepura-puraan itu terekspos akibat kepiawaian netizen untuk mencari informasi. Di dunia maya sering disebut bila netizen Indonesia sudah seperti Badan Intelijen Negara dalam hal mencari informasi.
Baca juga Ilusi Media Sosial
Bila kemudian terungkap, ramai-ramai publik dunia maya menghakimi dan menghujat sang pesohor. Bahkan, seringkali hujatan tersebut merembet kepada orang-orang terdekat si pesohor. Akibatnya, masyarakat kita telah bergeser menjadi masyarakat penghujat.
Perubahan sosial ini terjadi tanpa benar-benar kita sadari. Kita bisa bayangkan apabila ini terus berlangsung dan menguat. Apakah masyarakat Indonesia akan membentuk kultur dan nilai kepura-puraan, munafik, tidak realistis, suka mengurusi orang lain, tak mampu membedakan urusan publik dan privat, dan suka menghakimi dan menghujat? Pelik bukan?
*Artikel ini diterbitkan Harian Kompas, Minggu, 2 Oktober 2022
Baca juga Tawaf