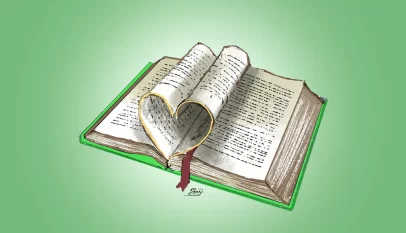Beragama Maslahat
Oleh: Ahmad Najib Burhani,
Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Satu hal yang mengejutkan dan sering menjadi pertanyaan dari rancangan RPJPN 2025-2045 adalah munculnya istilah ”Beragama Maslahat” sebagai salah satu dari 17 arah pembangunan nasional.
Maslahat bukanlah istilah yang familiar di telinga banyak orang. Karena itu, apa makna istilah ini dan di mana letak ”Moderasi Beragama” yang sejak 2017 begitu gencar dikampanyekan oleh pemerintah?
Peristiwa 9/11 atau Serangan 11 September 2001 ke World Trade Center (WTC) merupakan titik awal kata ”moderat” atau ”Islam moderat” menjadi istilah yang populer. Istilah ini sering dihadapkan atau menjadi lawan dari ”Islam radikal” atau terorisme.
Baca juga Bagaimana Menangani Perundungan Anak
Kemudian, setelah Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dan Pemilihan Presiden 2019, istilah ”Moderasi Beragama” begitu deras masuk ke masyarakat melalui berbagai program yang dilakukan pemerintah, terutama Kementerian Agama. Program-program itu, di antaranya, adalah Rumah Moderasi Beragama (RMB), Masjid Pionir Moderasi Beragama (MPMB), Indeks Moderasi Beragama, Kampung Moderasi, dan Literasi Moderasi Beragama.
Moderasi beragama ini bahkan masuk dalam RPJMN 2020-2025 sebagai penjabaran dari salah satu dari tujuh agenda pembangunan, yaitu ”Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Agenda ini dilakukan, di antaranya, dengan cara ”memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial”.
Baca juga Titik Buta Kekerasan di Sekolah
Kesalahan dan simpang siur sering terjadi terhadap istilah ”Islam moderat” dan ”moderasi beragama”. Bahkan, dua istilah acapkali dipahami secara bergantian dengan makna yang dianggap sama. Ini terjadi karena memang ada pendefinisian yang beririsan dan isu keduanya yang berdekatan, yaitu menghadapi sikap beragama yang ekstrem, maraknya intoleransi, terganggunya kerukunan dan harmonis sosial.
Ditilik dari konteks waktu dan persoalan sosial yang melingkupi, dua istilah itu jelas berbeda dan memiliki sasaran yang tak sepenuhnya sama. Islam moderat adalah terjemahan dari wasathiyyatul Islam atau Islam Wasathiyyah dan terutama ditujukan sebagai respons terhadap berbagai tindak ekstremisme, seperti teror dan bom bunuh diri, yang banyak terjadi pasca-Peristiwa 9/11. Moderat di sini adalah kata sifat yang berbeda dari moderasi yang merupakan kata kerja.
Baca juga Polarisasi dan Pentingnya Akal Sehat
Setelah Peristiwa 9/11, istilah Islam moderat identik dengan peaceful Islam atau Islam yang damai dan menentang berbagai tindak terorisme. Tentu, bagi mereka yang tak suka dengan istilah ini, ia kadang dimaknai sebagai ”Islam lunak” atau Islam yang telah beraliansi dengan Amerika Serikat dalam war on terror atau Islam yang telah ”terbeli” oleh pemerintah.
Terlepas dari perbedaan itu, Islam moderat adalah sebuah paham dan sikap keislaman yang antiterhadap berbagai bentuk kekerasan atau ekstremisme. Islam moderat ini mendapat respons dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam wujud ”Islam Nusantara” dan ”Islam Berkemajuan”. Meski ada elemen kritik, ketiganya tampak berjalan untuk saling melengkapi.
Baca juga Kenapa Orangtua Menganiaya Anaknya?
Nah, berbeda dari Islam moderat, moderasi beragama tak eksklusif Islam. Ia menyangkut semua agama di Indonesia dan targetnya adalah agar umat beragama menghindarkan diri dari manipulasi dan melakukan abuse terhadap agama untuk kepentingan politik, agar umat beragama tak memusuhi mereka yang berbeda agama.
Seperti ditulis Suhadi Cholil dalam ”Freedom of Religion amid Polarization and Religious Moderation Policy” (2022), konteksnya bukanlah merebaknya terorisme atau aksi bom bunuh diri, melainkan polarisasi politik dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Tokoh pengusung utamanya tak lain adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Baca juga Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Ketika itu, dikotomi antara Muslim dan non-Muslim begitu keras dan bahkan menyebar ajakan untuk tidak melakukan shalat jenazah bagi sesama Muslim yang memilih calon lain jika ia meninggal dunia. Polarisasi tajam itu diringkaskan dengan munculnya dua istilah dikotomis yang pejoratif, yaitu ”cebong vs kampret” atau ”kadrun vs buzzerRP”.
Setelah berjalan beberapa tahun, program moderasi beragama itu bisa dikatakan terlihat dampaknya pada Pilpres 2024 ini. Seperti ditulis Soderborg dan Muhtadi dalam ”Indonesia’s polarisation isn’t dead, just resting” (2023), tak terjadi polarisasi keras atau penggunaan politik identitas yang masif dalam pesta demokrasi kali ini.
Baca juga Perluas Hak Korban dalam Proses Peradilan Pidana
Walakin, kondisi ini tentu saja tak bisa dialamatkan sepenuhnya pada program moderasi beragama. Faktor penting yang memengaruhi meredupnya politik identitas dan polarisasi itu tentu saja adalah pembubaran FPI dan HTI yang sebelumnya menjadi kompor utama penyebaran politik identitas dan polarisasi.
Faktor penting lainnya adalah bergabungnya Prabowo ke Jokowi dan menjadi aliansi pemerintah sejak diangkat menjadi Menteri Pertahanan pada 2019. Pilihan politik Prabowo dari oposisi menjadi bagian pemerintahan ini tentu saja membuat mereka yang selama ini mendukung polarisasi menjadi kecewa dan disorientasi.
Baca juga Rekayasa Media Sosial yang Meresahkan
”Untuk apa mati-matian ikut dalam polarisasi jika ternyata justru pimpinan atau orang yang dibelanya malah berbalik arah”, begitu kira-kira ungkapan kekesalan mereka.
Jika polarisasi sudah mereda, lantas apa target dari moderasi beragama selanjutnya? Memang, social cleavage atau social faultlines, seperti agama dan etnisitas, itu bisa saja tak dimanipulasi dalam kontestasi politik tertentu. Namun, bukan berarti ia telah mati. Ia masih tetap berpotensi untuk dipakai memecah belah masyarakat atau negara. Ia selalu bisa menjadi sumber kekayaan perspektif dan keragaman budaya, tetapi ia juga selalu memiliki potensi sebagai ancaman terhadap persatuan.
Harapannya, masyarakat sudah semakin dewasa menghadapi politik identitas dan tak mau dibawa ke arah polarisasi tajam yang pasti merugikan semua elemen masyarakat dan negara. Jika itu terjadi, tentu saja program moderasi beragama perlu berganti sesuai dengan kebutuhan baru.
Baca juga Perspektif Korban untuk Dialog Damai Israel-Palestina
Hal lain, yang perlu dimoderasi di masyarakat tidak saja model keberagamaan, tetapi juga aspek kehidupan lain. Polarisasi dan intoleransi tak mesti karena paham atau interpretasi keagamaan. Kadang, teroris dan kelompok radikal itu adalah bagian dari kelompok ”new born” yang menggunakan agama sebagai tameng tindakannya.
Kadang, polarisasi terjadi karena politik dan seseorang menjadi radikal karena persoalan sosial lain. Di sinilah ”beragama maslahat” menemukan urgensinya, sebagai estafet dari moderasi beragama.
Baca juga Menjadi Guru yang Humanis
Lantas, apa makna dan ke mana arah beragama maslahat ini? Seperti disampaikan Amich Alhumami dari Bappenas pada diskusi di Jakarta (8/6/2023), RPJPN itu melintasi sekat-sekat pemerintahan dan politik. Karena itu, frasanya harus memayungi semua, melampaui periode pemerintahan. Beragama maslahat ini mengacu pada sikap keagamaan yang, di antaranya, ”mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kemaslahatan umum (maslahah al-ammah, the common good, bonum commune), keadilan, keberimbangan, ketaatan pada konstitusi, dan kearifan lokal”.
Moderasi Beragama sendiri tetap ada dalam tahapan pembangunan hingga 2034.
*Artikel ini terbit di Kompas.id, Sabtu 13 Januari 2024
Baca juga Mitos Literasi dan Kemalasan