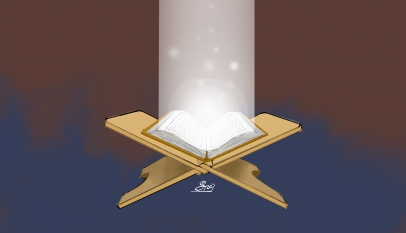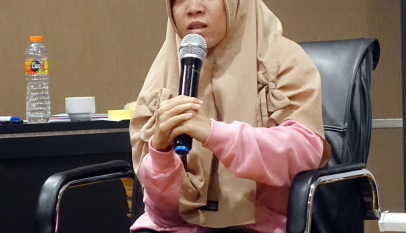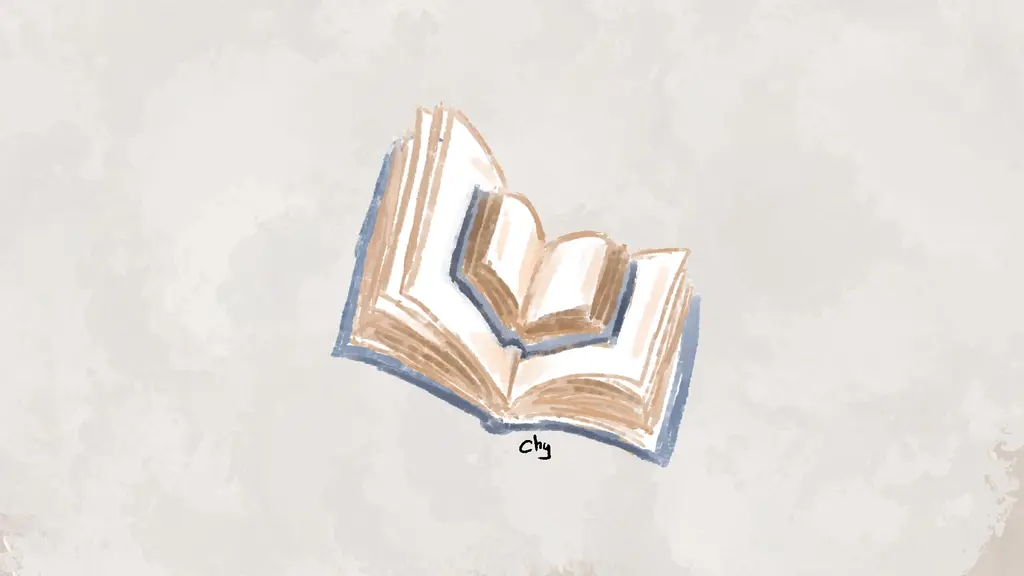Menjaga Api Harapan di Pesantren
Oleh: Anggi Afriansyah,
peneliti Sosiologi Pendidikan di Pusat Riset Kependudukan BRIN
Orangtua memiliki banyak harapan ketika memasukkan anak-anak mereka ke pesantren. Ketika masuk ke pesantren, doa-doa dilangitkan agar anak-anak mendapat bimbingan yang baik, tertempa mental dan karakter, memiliki ilmu agama yang memadai untuk diamalkan untuk diri dan masyarakat. Dengan pengetahuan dan pengalaman masing-masing orangtua memilih pesantren yang diharapkan dapat membantu anak-anak mereka menjadi anak-anak saleh-salehah.
Namun, kasus-kasus yang terjadi di pesantren belakangan ini perlu menjadi perhatian khusus. Cerita tentang kekerasan yang terjadi di pesantren sesungguhnya bukan perkara baru. Namun, kisah-kisah tersebut seringkali redup tenggelam. Penyelesaian secara kekeluargaan, seperti kasus-kasus perundungan di sekolah, menjadi salah satu alasan mengapa kasus-kasus kekerasan, kekerasan seksual, perundungan nampak sulit diselesaikan.
Baca juga Mengabaikan Surga
Meski ada bukti-bukti bahwa kekerasan tersebut telah mengakibatkan korban, bahkan hingga meninggal, tampak kita belum begitu ‘peduli’ terhadap kasus-kasus tersebut. Kita ramai sebentar, kemudian lupa kembali, hingga akhirnya ada kasus-kasus baru hadir. Alarm tanda bahaya terkait dengan perundungan, kekerasan sekolah, atau kasus-kasus di sekitar relasi anak-guru-orangtua di sekolah atau di pesantren tampak tak pernah diperhatikan secara seksama dan diselesaikan secara menyeluruh. Akhirnya ketika kasus-kasus muncul dan viral, semua baru menaruh perhatian secara detil pada kasus-kasus tersebut.
Jika membaca kasus-kasus tersebut, dapatkah kita memposisikan diri sebagai orangtua korban –membayangkan anak tercinta yang disayangi sejak kecil tiba dengan kondisi memar, dan kemudian harus dimakamkan? Anak yang kita harapkan pulang ke rumah berubah akhlak dan pengetahuan keagamaannya. Anak yang setiap detik didoakan itu kemudian kembali dalam keadaan tak bernyawa. Bahkan tak bisa lagi mengadu kepada kita, orangtuanya, tentang hal-hal rumit yang mereka temukan dalam dunia keseharian. Tentang sulitnya menghadapi masa muda, soal pertemanan, atau senangnya belajar di pesantren dengan berbagai dinamikanya.
Baca juga Sekolah Bahagia
Jika melalui pendekatan tersebut, kita tak hanya memandang korban secara kuantitatif. Satu, dua, tiga korban semata dari segi angka-angka. Kita akan melihat dari segi atau jiwa yang hilang, ada anak yang dicintai, ada harapan yang hilang. Pada porsi tersebut, penanganan kasus-kasus kekerasan dan perundungan harus diperhatikan. Para aparatur hukum, pengelola pesantren dan lembaga pendidikan harus memberi simpati dan empati yang porsinya pas pada korban.
Yang repot, ketika menghadapi kasus-kasus seperti ini, pihak-pihak yang seharusnya menjadi aktor utama untuk menyelesaikan kasus lebih mendahulukan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, yang alih-alih mengutamakan korban, malah justru lebih menguntungkan mereka yang menjadi pelaku. Pelaku melenggang bebas, tanpa hukuman memadai. Sementara korban, dalam berbagai derajat luka yang tersisa baik mental atau fisik harus tetap merana. Bahkan ketika meninggal, orangtua dan keluarga adalah pihak terakhir yang setiap saat memendam duka mendalam.
Baca juga Jalan Panjang Menuju Palestina Merdeka
Jika tujuan utama pesantren adalah mendidik anak, maka tindakan kekerasan yang terjadi di pesantren perlu dinihilkan, bahkan jika itu didasarkan pada upaya pendisiplinan. Meski perlu diakui, bahwa dalam konteks pendisiplinan sering kali penegakan menggunakan kekerasan masih mewarnai ruang pendidikan kita, termasuk di pesantren. Jika cara pandang ini dipertahankan, tentu relevansi pendidikan atau pendidikan pesantren akan semakin dipertanyakan. Jika orangtua saja tidak pernah menggunakan kekerasan pada anak, mengapa pihak lain boleh menggunakan kekerasan tersebut kepada anak-anak atau santri-santri?
Perlu ada metode-metode yang lebih arif bijaksana dalam mendisiplinkan anak. Bukan dalam arti membebaskan anak untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan, tetapi memberikan rambu-rambu yang perlu ditaati anak. Dalam terminologi psikologi sering disebut self-disciplined, di mana anak-anak didik mentalnya untuk memahami pentingnya disiplin diri. Artinya, pada tahap awal anak-anak perlu dibangun kesadaran mengapa disiplin itu penting.
Baca juga Antara Rafah, Tel Aviv, dan Riyadh
Dalam konteks ini, jika menggunakan terminologi Simon Sinek, start with why? Mengapa para santri harus disiplin, mengapa disiplin itu penting, mengapa setiap cita-cita dapat dicapai dengan disiplin yang tangguh, dan pertanyaan-pertanyaan lain.
Apalagi sudah terbukti, mereka yang memiliki disiplin diri adalah sosok-sosok yang dapat meraih harapan-harapan di masa depan. Para penghafal Al Quran adalah sosok yang kokoh disiplin dirinya. Para ahli tafsir, untuk mengasah diri, perlu membaca Al Quran secara berulang, memahami makna, hingga mendapatkan tafsir yang memadai dengan konteks sosial. Dalam proses tersebut mereka menempa diri dan memiliki disiplin diri yang tangguh.
Baca juga Paradoks Pendidikan dan Keterpinggiran
Maka dari itu, seperti yang sudah dicontohkan melalui pendidikan pesantren di masa lalu, disiplin diri menjadi penting. Nilai-nilai penghormatan pada yang memiliki ilmu pengetahuan menjadi poin penting dalam proses pendidikan di pesantren. Tak mengherankan jika para santri dengan mudah patuh dan taat kepada para pengelola pesantren. Poin ini juga perlu menjadi penekanan. Ketika para pengelola merupakan sosok terhormat karena ilmu pengetahuan yang dimiliki, maka proses pendisiplinan dan internalisasi ilmu serta akhlak akan lebih mudah diupayakan. Sebab, secara batiniah, santri-santri lebih tergerak untuk menghormati sosok-sosok mumpuni tersebut.
Para pengelola pesantren pun perlu secara terbuka menyampaikan kepada orangtua bagaimana pola pendidikan yang diberikan di pesantren. Pola pendisiplinan yang dilakukan, dan kerja sama yang perlu dilakukan untuk menjadikan anak-anak yang memiliki akhlakul karimah serta wawasan keagamaan yang mumpuni. Apalagi, harapan untuk menjadi anak-anak yang dapat bermanfaat bagi kemanusiaan setelah lulus menjadi doa dari orangtua yang menitipkan anak-anaknya ke pesantren.
Baca juga Tantangan Pendidikan Indonesia
Gus Dur (2001) dalam karyanya Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren menjelaskan dengan sangat presisi peran seorang kiai bagi pesantren. Gus Dur menjabarkan betapa kiai memiliki kewibawaan moral yang besar dengan hal tersebut menjadi bagian penting untuk menyelamatkan santrinya dari kesesatan. Wibawa moral tersebut juga mengikat para santri, sehingga menjadikan para kiai sebagai sumber inspirasi dan penunjang moral dalam kehidupan pribadi, dan oleh sebab itu dalam banyak aktivitas serta kehidupan para santri terbiasa berkonsultasi dan mengikuti petunjuk-petunjuk kiai.
Jika memperhatikan uraian Gus Dur, tingginya tanggung jawab moral kiai juga dibangun oleh keteladanan mereka. Tak mungkin mereka diikuti dengan sepenuh hati jika tidak ada keteladanan di dalam diri para kiai. Jika meminjam Max Weber (1947), para kiai memiliki charismatic authority. Karisma, merujuk pada Weber, merupakan kualitas tertentu dari kepribadian seseorang yang membuatnya berbeda dari orang biasa dan dianggap memiliki kekuatan atau kualitas supernatural, superhuman, atau memiliki kualitas yang luar biasa. Jika menggunakan terminologi Weber, maka hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Gus Dur terkait dengan wibawa moral.
Baca juga Buku di Bayang-bayang Kecerdasan Buatan
Posisi tersebut menempatkan kiai pada posisi terhormat baik dalam pandangan santri-santrinya ataupun masyarakat secara keseluruhan. Karisma tersebut menggerakkan kehidupan pesantren, dan menularkan kepada kehidupan masyarakat lewat alumni-alumni pesantren yang hadir di masyarakat.
Peristiwa kekerasan tersebut tentu menjadi salah satu penanda terkait perlunya kembali meninjau pesantren-pesantren di Indonesia, bukan dalam konteks pengawasan, tetapi dalam arti memberi perhatian mendasar terkait bagaimana kehidupan pesantren digerakkan. Secara struktural, Kementerian Agama memiliki tanggungjawab untuk memastikan gerak langkah pesantren tetap sebagai bagian penjaga moral bangsa ini.
Baca juga Tidak Semua Orang Bisa Menjadi Pendidik
Dan, dari segi orangtua, orangtua perlu lebih selektif dalam menilai pesantren-pesantren yang memiliki kewibawaan moral yang terjaga dalam rekam jejak selama ini, sehingga menjadi institusi yang tepat dalam mendidik anak-anak mereka. Kita tentu berharap, pesantren tetap menjadi institusi penting dalam menjaga obor harapan dalam menjadi penjaga moral di tengah kompleksitas kehidupan bangsa ini.
*Artikel ini terbit di detik.com, Jumat 17 Maret 2024
Baca juga Berlarilah Menuju Allah