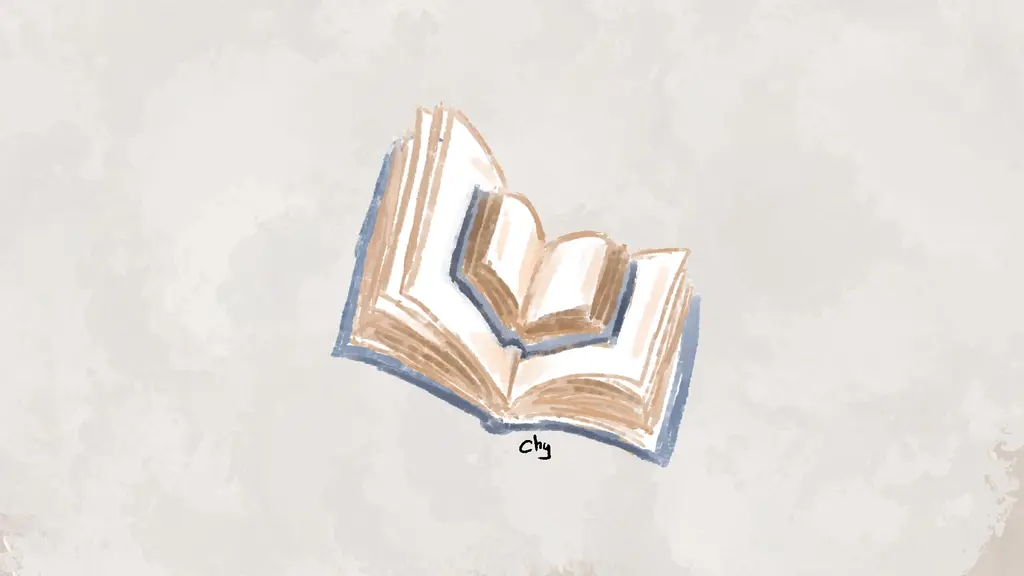Mencari Kita di Tengah Aku
Oleh Alissa Wahid
Direktur Jaringan Gusdurian Indonesia
”The Great Reset”. Inilah istilah yang banyak digunakan untuk menggambarkan bagaimana dahsyatnya perubahan tatanan dunia dan masyarakat yang kita yakini dan jalani akibat pandemi Covid-19.
Lurah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Wahyudi Anggoro Hadi menggambarkannya dengan baik. Katanya, melalui pandemi ini kita belajar bahwa puncak relasi sosial adalah keluarga, puncak relasi ekonomi adalah kerja sama, dan puncak relasi politik adalah musyawarah.
Pandemi memaksa kita lebih banyak tinggal di rumah. Orang tua berinteraksi 24 jam dengan anak-anaknya. Suami dan istri pun hidup bersama tanpa memiliki identitas dan ruang personal di pekerjaan dan aktivitas pribadinya.
Baca juga Psikologi Memaafkan (bag. 1)
Kita meninggalkan kompetisi ekonomik untuk bahu-membahu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Kehidupan politik relatif sepi dari keramaian yang tak memberdayakan. Ego sektoral melebur dalam satu padu kerja bareng mengatasi persoalan.
Polarisasi
Namun, apakah ketiga perubahan itu berlaku permanen dan membawa perubahan berkelanjutan? Tampaknya tak secara otomatis demikian. Kita melihat di tahun ini, sebagian relasi ini kembali ke pola-pola sebelum pandemi. Kepentingan dan agenda masing-masing kembali menyeruak, baik pribadi maupun kelompok, baik tingkat nasional maupun global.
Kita melihat polarisasi yang semakin membesar dalam berbagai hal, tidak hanya di dalam konteks politik praktis.
Baca juga Psikologi Memaafkan (bag. 2)
Kualitas kesejahteraan warga menjadi titik kesenjangan yang terdampak langsung. Usaha kecil menengah yang ambruk dan korporasi yang mengurangi tenaga kerjanya berdampak pada angka kemiskinan yang meningkat. Sementara itu, selepas restriksi perjalanan, keluarga kelas menengah ke atas menikmati revenge travel yang telah dua tahun ini ditinggalkan.
Merujuk buku The Spirit Level: Why More Equal Societies Almost Always Do Better yang ditulis Wilkinson dan Pickett (2009), jika kesenjangan ini tak tertangani dengan baik, beberapa dekade ke depan kita akan panen masalah kualitas hidup, seperti tingkat kejahatan, kesejahteraan anak dan perempuan, angka harapan hidup dan tingkat kesehatan, serta tingkat dan kualitas pendidikan.
Saat ini pendidikan berkualitas lebih dapat diakses oleh warga kelas menengah ke atas dan pendidikan berbasis digital pun mudah diadaptasikan.
Baca juga Psikologi Memaafkan (Bag. 3)
Sementara bagi warga menengah ke bawah, terutama yang tinggal di wilayah perdesaan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), pandemi membawa kesulitan berlapis. Ketimpangan akses internet, ketidakmampuan finansial untuk menyediakan gawai, serta literasi digital yang rendah pada guru dan murid membuat learning loss yang lebih besar bagi mereka.
Kita juga melihat polarisasi corak keberagamaan di Indonesia, terutama pada umat Islam yang merupakan kelompok umat beragama terbesar. Meminjam pandangan Syafii Anwar, polarisasi terjadi antara paradigma beragama yang substantif inklusif dan eksklusif legal formalistik.
Yang pertama memandang bahwa setiap individu memiliki hak kewargaan yang setara, karena itu kehidupan keberagamaan pun harus dijaga agar inklusif. Yang kedua memandang bahwa demokrasi berarti mayoritaslah yang berkuasa, karena itu adalah wajar melakukan formalisasi aturan agama kelompok mayoritas.
Baca juga Fondasi dan Keutamaan Memaafkan (Bag.1)
Alhasil, sikap eksklusif umat beragama atas nama kelompok mayoritas di berbagai tempat pun mendorong hilangnya hak konstitusi kelompok warga negara beragama minoritas.
Teknologi informasi pun mencatatkan dampak polarisasinya. Kita melihat kecenderungan warga bangsa yang semakin saling terhubung melalui platform jejaring dan media sosial.
Di satu sisi, ini membuat warga bangsa lebih mudah saling menolong atau beramai-ramai mengangkat sebuah isu yang krusial. Berbagai kasus ramai di media sosial dan berujung perubahan kebijakan atau penyelesaian kasus yang terkawal. Ketika ada warga bangsa yang membutuhkan, netizen tidak segan bertindak atau merogoh kantong untuk membantu orang yang bahkan tak dikenalnya. Untuk itu, bangsa kita diganjar peringkat 1 dalam World Giving Index 2019.
Baca juga Fondasi dan Keutamaan Memaafkan (Bag. Terakhir)
Sebaliknya, media sosial juga menjadi tempat penghakiman yang luar biasa kejam. Doxxing (berburu dan membuka identitas pribadi) dilakukan dengan cepat. Perisakan daring pun terjadi dengan riuh rendah. Ini membuat Indonesia mendapat predikat bangsa yang paling kurang beradab menurut Digital Civility Index 2020 yang dilansir Microsoft.
Dan tentu saja, polarisasi akibat politik praktis yang berkelindan dengan politik identitas. Dalam masyarakat yang sosiosentrik, identitas menjadi sentimen yang paling mudah untuk mendapatkan dukungan politik. ”Kampret” dan ”cebong” pun menjadi label yang merendahkan kemanusiaan pendukung lawan politik. Tak heran keluarga bisa retak karena perbedaan pilihan politik.
Semangat persaudaraan
Setiap polarisasi ini bisa berdampak jauh, setidaknya relasi antarmanusia pun bisa rusak karenanya. Karena itu, kita perlu segera melakukan berbagai upaya dengan sengaja karena hampir tidak mungkin gejala-gejala ini bisa sembuh dengan sendirinya.
Baca juga Pendidikan dan Ketenangan Jiwa
Kita perlu kembali ke semangat senasib-sepenanggungan sebagai bangsa dan negara. Membangun semangat persaudaraan kebangsaan dengan nation building.
Gotong royong adalah prinsip hidup bersama yang nyata dalam setiap kelompok masyarakat Indonesia dan mengalami penguatan sepanjang pandemi. Karena itu, kita perlu meneguhkan gotong royong sebagai nilai dasar maupun pendekatan pembangunan bangsa.
Namun, gotong royong tidak bisa diharapkan tumbuh begitu saja, apalagi hanya dijadikan slogan. Meminjam teori Otto Scharmer dalam buku The Essence of Theory U (2018), gotong royong sebagai pendekatan kolaboratif generatif/produktif hanya bisa terwujud apabila kita mampu melepaskan diri dari tiga penghambatnya, yaitu Voice of Judgement, Voice of Cynicism, dan Voice of Fear.
Baca juga Ancaman Ekstremis-Radikalis di Era Disrupsi
Suara-suara ini membuat kita sibuk berkompetisi, berdebat untuk memaksakan kepentingan, bukan berdialog, apalagi berkolaborasi. Kita terjebak polarisasi cebong-kampret, menciptakan blunder penyelenggara negara yang mengabaikan persoalan rakyat, juga meningkatkan ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah dan parpol.
Mental set bahwa kelompok kita perlu menjaga diri dari ancaman kehadiran kelompok lain membuat kita bercuriga pada agenda kelompok lain, dan berupaya merebut dan mempertahankan kekuasaan. Tak bisa dimungkiri, paradigma relasi kuasa saat ini mendominasi mulai dari kekerasan berbasis jender di dalam keluarga sampai pada kepentingan ekonomi dan kekuasaan negara.
Gotong royong menurut Scharmer mensyaratkan tiga sikap mental yang tampak trivia, yaitu Pikiran Terbuka, Hati Terbuka, dan Tekad Terbuka (Open Mind, Open Heart, dan Open Will). Dengan tiga hal ini, pendekatan hierarkis struktural serta kompetisi bisa digantikan dengan kerja sama sejati karena ia akan menumbuhkan mental set adil dan welas asih serta bertanggung jawab.
Baca juga Menghentikan Kebiasaan Buruk
Kalau kita selami, ketiga hal ini bukanlah nilai baru dalam masyarakat kita. Sayangnya, perjalanan hidup bangsa yang tidak dilengkapi dengan pembangunan kebangsaan yang kuat yang membuat kita menyisihkan nilai-nilai ini untuk pencapaian material.
Bangsa kita dipenuhi dengan berbagai filosofi yang kuat. Tri Hita Karana, misalnya, menjadi falsafah masyarakat Bali untuk membangun kehidupan yang bermakna dan sejahtera melalui harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan sesama manusia, dan harmoni dengan alam.
Hal ini senada dengan konsep Islam tentang tiga dimensi hubungan yang harus dibangun setiap manusia: hablum min Allah (hubungan dengan Tuhan), hablum min an-nas (hubungan dengan sesama manusia), serta hablum min al-alam (hubungan dengan alam).
Baca juga Manfaat Pemaafan
KH Ahmad Siddiq melengkapi dengan tiga persaudaraan (ukhuwah): ukhuwah diniyah (persaudaraan umat seagama), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sesama warga bangsa), dan ukhuwah basyariah (persaudaraan sesama manusia).
Untuk itulah kita membutuhkan kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang meneladankan (ing ngarso sung tulodo), kepemimpinan yang selaras dengan derap langkah bangsanya (ing madyo mangun karso), dan kepemimpinan yang tut wuri handayani.
Dalam tulisannya di tahun 2012, Gus Dur menyebutkan sebagian besar negara di dunia mencita-citakan kemerdekaan dan kemakmuran sebagai tujuan berdirinya negara, berbeda dengan Indonesia. Beliau mengingatkan, bangsa kita telah menetapkan tujuan berdirinya negara Indonesia adalah keadilan dan kemakmuran. Keduanya mensyaratkan kita mengikatkan diri pada kebersamaan kita, membangun hubungan utuh dan saling memperkuat, bergerak bersama.
Baca juga Membangun Religiositas Humanis, Menuju Altruisme
Apabila kita berhasil membangun kembali jembatan-jembatan hubungan antarpenghuni bumi nusantara ini, niscaya Recover Together Recover Stronger tak hanya menjadi slogan belaka dan akan berwujud nyata menjadi kebangkitan bangsa yang adil dan makmur.
*Artikel ini terbit di Harian Kompas, 28 Juni 2022
Baca juga Hati Nurani dan Jiwa Pemaaf