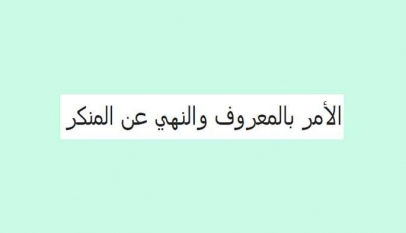Distorsi Kaidah Ulil Amri:
Upaya Memahami dan Menyikapi Kepemimpinan secara Utuh
Oleh: Fikri
Master Ilmu Politik Universitas Indonesia
Istilah ulil amri mungkin tidak populer di masyarakat umum, namun menjadi perdebatan di kalangan aktivis Islam. Banyak perbedaan pendapat tentang status, hak, dan kewajiban, serta relasinya dengan rakyat dalam kacamata Islam, khususnya di negara-negara demokrasi yang mayoritas penduduknya muslim. Secara terminologis, istilah ulil amri disebut sebagai para pemilik otoritas dalam urusan umat, yaitu orang-orang yang memegang kendali semua urusan.
Menurut Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ Al Fatawa, “Ulil amri adalah pemegang dan pemilik kekuasaan. Mereka adalah orang-orang yang memerintah manusia. Perintah tersebut didukung oleh orang-orang yang memiliki kekuatan (ahli qudrah) dan ahli ilmu. Karena itu ulil amri terdiri dari dua kelompok manusia: ulama dan umara; bila mereka baik, manusia pun akan baik, bila mereka buruk, manusia pun akan buruk.”
Baca juga Pemerintahan Ideal Menurut Islam
Sejalan dengan itu, Imam As-Syaukani juga menyebutkan dalam Fathul Qadir, “Ulil amri adalah para imam, penguasa, hakim dan semua orang yang memiliki kekuasaan yang syar’i.” Ulil amri juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak mereka adalah untuk ditaati, sebagaimana perintah dalam Al-Qur’an, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian (Q.S. An-Nisa: 59). Namun ketaatan kepada pemimpin tersebut tidak berdiri independen, harus diikuti selama tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya, yang menurut Imam As-Syaukani, yang ‘syar’i’. Kata syar’i ini yang nanti akan menjadi perdebatan.
Kaidah-kaidah memahami ulil amri
Pertanyaan yang muncul di sebagian umat Islam adalah bagaimana memahami ulil amri yang secara syar’i wajib ditaati, karena ada upaya untuk mendistorsi pemahaman tentang ulil amri tersebut. Sebagai misal ada kelompok yang menggeneralisasi beberapa kesalahan yang dilakukan seorang pemimpin, lantas memberikan fatwa wajib untuk diperangi. Menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengacu pada beberapa kaidah.
Pertama, mengembalikan kepada syarat atau asal seseorang menjadi muslim, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Dengan mengucapkan dua kalimat tersebut, siapa pun telah berstatus muslim. Artinya pemimpin muslim juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai sesama muslim. Oleh karena itu haram hukumnya mengeluarkan atau memvonis seseorang keluar dari Islam apalagi dengan dasar keragu-raguan. Pasalnya keyakinan tidak bisa dibatalkan dengan keraguan, sebagaimana kaidah fiqih, اليقين لا يزول بالشك.
Baca juga Refleksi Hari Ibu: Perempuan, Kasih Sayang dan Perdamaian
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin menerangkan hal itu dalam Syarah Al-Arba’in An-Nawawiyah Al-Mukhtashar (1425 H) dengan merujuk pada hadis sahih dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah.”
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Kitab Majmu’ Fatawa, Jilid 12 juga mengatakan, “Tidak ada seorang pun berhak mengkafirkan seorang muslim lainnya, walaupun dia telah melakukan kekeliruan atau kesalahan, sampai ditegakkan hujjah (argumen) terhadapnya dan dijelaskan jalan yang benar kepadanya. Orang yang telah berstatus muslim dengan pasti, maka statusnya itu tidak akan lepas hanya dengan sebab sesuatu yang masih diragukan. Bahkan status keislamannya itu tetap melekat padanya sampai hujjah berhasil ditegakkan dan syubhat (kesamaran) telah berhasil dihilangkan.”
Baca juga Pahlawan Perdamaian
Kedua, melihat pada aspek level keimanan. Setiap muslim tentu saja memiliki tingkat keimanan yang berbeda-beda. Demikian halnya seorang ulil amri. Sebagian mereka memiliki iman yang kuat dan sebagian lemah. Di mana pun level keimanannya, hal itu tidak menggugurkan statusnya sebagai seorang muslim termasuk jika ia menjadi ulil amri.
Perkara tersebut didasarkan pada kisah Al Hajjaj, seorang gubernur Kufah, Irak, pada masa khilafah Bani Umayyah. Al Hajjaj merupakan pemimpin kejam dan dijuluki tangan besi. Namun salah seorang sahabat Nabi, Anas bin Malik, mengatakan kepada seseorang yang bertanya kepadanya agar bersabar.
Baca juga Proses Panjang Meninggalkan Ekstremisme
Zubair bin ‘Adi berkata, kami mendatangi Anas bin Malik mengeluhkan perihal Al Hajjaj. Anas pun menjawab: “Bersabarlah, karena tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya akan lebih buruk sehingga kamu berjumpa dengan Rabb-mu. Aku mendengarnya dari Nabi Saw” (H.R Bukhari dalam Al Hafizh Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al ‘Asqalani, 1432 H, Fathul Bari fi Syarhi Shahih Al Bukhari).
Ketiga, istilah hakimiyah atau persoalan hukum menurut pendapat sebagian ulama bukan perkara ushul atau dasar. Maka dari itu, jika seorang ulil amri belum mampu memerintah atau berkuasa dengan adil dan penuh secara syar’i, tidak lantas boleh diperangi. Hal ini merujuk kepada kisah Raja Najasyi (Habasyah) yang belum mampu sama sekali menjalankan kekuasaannya sebagai ulil amri secara syar’i, bahkan ia sendiri menyembunyikan statusnya sebagai seorang muslim, dikarenakan rakyat belum menerima dan ditakutkan terjadi kerusakan.
Baca juga Pentingnya Ibroh Terorisme
Melihat kondisi tersebut Rasul tetap mengategorikan Raja Najasyi sebagai muslim. Nabi dan para sahabat pun melakukan salat gaib ketika ia meninggal. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW memberitahukan kematian Raja Habasyah kepada mereka pada hari kematiannya, dan beliau berkata, “Mintakan ampun untuk saudara kamu.” Kemudian Rasulullah Saw menyuruh mereka membentuk saf di musala, lalu salat untuknya dan bertakbir empat kali takbir.” (Al Hafizh Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al ‘Asqalani, Ibid).
Keempat, perlu membedakan antara pengkafiran mutlak/perbuatan dengan pengkafiran mu’ayyan/individu. Jika seorang ulil amri melakukan tindakan kesalahan atau kekufuran, maka harus dilihat dalam konteks perbuatannya, bukan dengan memvonis individunya. Jika terjadi vonis individual, misalnya menyematkan status kafir, maka akan berdampak pada kehalalan ulil amri tersebut untuk dibunuh atau diperangi. Pandangan tentang perbedaan ini merujuk kepada beberapa kisah.
Baca juga Belajar Zuhud dari Penyintas Bom
Pertama, kisah Usamah bin Zaid dalam perang Badar. Ketika itu Nabi Saw marah saat sahabat Usamah membunuh musuh yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Usamah meyakini bahwa ikrar tersebut hanyalah kepura-puraan. Namun menurut Nabi, manusia tidak bisa diketahui isi hatinya, padahal saat itu dalam kondisi perang yang berkecamuk. Berdasarkan sebuah hadis, “Wahai Usamah? Apakah engkau membunuhnya setelah ia mengucapkan Laa Ilaaha illallaah? Saya (Usamah) menjawab, “Wahai Rasulullah, ia mengucapkannya sekadar untuk melindungi dirinya.” Namun beliau tetap bertanya, “Apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan Laa Ilaaha Illa Allah?” Usamah berkata, ‘Beliau terus mengulang-ulangi ucapan itu, sehingga aku berangan-angan (seandainya) aku belum memeluk Islam sebelum hari itu” (HR. Bukhari dan HR. Muslim).
Kedua, kisah yang dialami beberapa ulama, salah satunya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ia tidak memvonis kafir kepada bangsa Tartar yang saat itu menguasai Mardin (sekarang masuk wilayah Turki), walaupun mereka banyak berbuat kezaliman. Ibnu Taimiyah memang mengkritik atau menasehati kekuasaan bangsa Tartar tersebut dalam konteks perbuatannya.
Baca juga Menggelorakan Ketangguhan
Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang penduduk Mardin. Ia menjawab, “Apakah wilayah itu wilayah perang atau damai, ini adalah situasi yang rumit. Wilayah itu bukan tempat tinggal yang damai di mana syariat Islam diberlakukan dan dijaga oleh pasukan Muslim. Wilayah itu juga bukan untuk diperangi karena penduduknya bukan orang kafir. Wilayah itu masuk kelompok ketiga. Kaum muslim yang tinggal di sana harus diperlakukan berdasarkan hak mereka sebagai muslim, sedangkan non-muslim yang tinggal di sana dan berada di luar kekuasaan hukum Islam harus diperlakukan berdasarkan hak mereka” (Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, Jilid 28).
Bersikap kepada pemimpin
Mengacu pada kaidah-kaidah di atas, pemimpin muslim yang walaupun tingkat keimanannya rendah, tidak berhukum kepada hukum Allah disebabkan udzur syar’i, ditambah memang perkara hakimiyah bukan perkara ushul, maka tidak jatuh kepadanya vonis kafir mua’yyan/individu. Sehingga ulil amri tersebut wajib ditaati.
Masalahnya, sebagian dari kelompok ekstremis begitu mudah berlepas diri dan memerangi ulil amri tanpa memerhatikan kaidah-kaidah yang jelas, walaupun mereka menggunakan argumentasi/dalil atau fatwa ulama yang sebenarnya telah mereka distorsi. Untuk itu perkara mengenai ulil amri ini sangat penting, sehingga harus berhati-hati dalam memahami dan bersikap.
Baca juga “Ketangguhan Mental Para Penyintas dan Mantan Pelaku Terorisme”
Mungkin banyak para pemimpin yang jauh dari kata ideal. Akan tetapi jika pemimpin tersebut masih melakukan shalat, membolehkan syiar-syiar Islam, masyarakat bebas melakukan ibadah, maka haram memerangi seorang ulil amri. Banyak kisah seorang khalifah atau gubernur pada masa kejayaan Islam terdahulu memimpin dengan zalim dan sewenang-wenang, namun karena posisi mereka berada dalam kaidah-kaidah di atas, maka para sahabat dan ulama memerintahkan bersabar dalam menghadapinya. Namun tetap diwajibkan menasehati terhadap tindakan mereka yang salah, tidak dengan mengkafirkan secara personal yang berakibat dihalalkan darahnya sehingga wajib diperangi.
Cara yang baik dan sesuai ajaran Islam adalah menasehati dengan lisan yang lembut, karena nasihat akan lebih mudah masuk. Proses penyampaiannya harus dilakukan dengan baik, tidak dengan berkata kasar apalagi sampai memerangi disebabkan perkara yang bersifat prasangka.
Baca juga Menghargai Kearifan Budaya
Salah satu contoh pola hubungan vertikal antara pemimpin dan rakyatnya, sebagaimana pendapat para ulama, dijelaskan oleh Imam Ahmad yaitu dengan cara mengambil tangannya lalu dibawa ke tempat kosong. Jika ia (pemimpin) menerima maka itu menjadi kebaikan. Jika tidak maka kita telah melakukan kewajiban kepada mereka. Tidak ada kewajiban atau anjuran untuk membunuh atau memerangi jika mereka menolak. “Barangsiapa yang hendak menasehati penguasa dengan sebuah perkara, maka janganlah ditampakkan. Tetapi ambil tangannya lalu bawalah ke tempat kosong. Jika ia menerima, maka itulah yang didapat. Jika tidak, maka engkau telah melakukan kewajibanmu kepadanya” (Muhammad Nasiruddin al-Albani, 1980, Zhilaalul Jannah fii Takhriij as-Sunnah).
Poin tersebut penting untuk dijadikan sebagai landasan amar makruf nahi munkar kepada penguasa, yaitu larangan untuk bertindak buruk secara terang-terangan, tidak dianjurkannya menasehati penguasa di hadapan khalayak ramai, dikarenakan sifat kekuasaan yang cenderung egois dan memiliki kemampuan melakukan kesewenang-wenangan. Sehingga penting untuk menasehati pemimpin empat mata dan berbicara dari hati-hati guna melunturkan sifat egoisnya.
Baca juga Memaknai Hijrah dalam Bingkai Perdamaian
Yang perlu digaris bawahi dari perkara ini adalah bahwa kepemimpinan itu sangat penting. Tidak boleh ada kekosongan dalam kepemimpinan dalam jemaat, oleh karena mempunyai tujuan (maqashid imamah) yaitu untuk menjalankan syariat. Adapun syariat juga mempunyai tujuan (maqashid syariah) yang salah satunya adalah agar tercipta keadilan. Dengan keadilan maka akan tercipta perdamaian. Karena perkara kepemimpinan sangat penting, maka hal-hal yang menyebabkan seorang ulil amri diperangi wajib dihindari.
Untuk menjaga relasi tersebut diperlukan kerjasama dan hubungan yang baik antara penguasa, ulama, dan rakyat. Saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Wallahu a’lam.