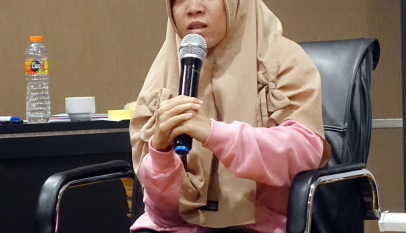Transformasi Masyarakat Digital
Oleh: Meuthia Ganie-Rochman
Sosiolog Organisasi, Universitas Indonesia
Digitalisasi sudah menjadi bagian hidup masyarakat di seluruh dunia. Koneksi telepon seluler melebihi jumlah penduduk dunia yang 8 miliar jiwa. Pengguna internet lebih dari 5 miliar dan pengguna media sosial hampir 5 miliar.
Di Indonesia, pola yang sama terjadi, yaitu terdapat sekitar 354 juta telepon seluler dan 213 pengguna internet dan 167 juta pengguna media sosial dari jumlah penduduk berkisar 275 juta jiwa (WeAreSocial, 2023).
Teknologi digital dan dalam bentuk lanjutannya, kecerdasan buatan (artificial intelligence/ AI), mempunyai banyak sekali dampak positif, seperti pengelolaan lebih baik dan luas, pertukaran gagasan luas yang menghasilkan lebih banyak inovasi, memfasilitasi kerja sama, prediksi dan penentuan target yang lebih tepat, dan banyak lagi.
Baca juga Inovasi Beragama
Seperti teknologi mana pun, selalu ada sisi positif dan negatif dampaknya. Di Indonesia, arus dominan, terutama pemerintah, masih memandang teknologi digital dari segi positifnya.
Pandangan yang menyuarakan kekhawatiran atas dampak digital sering dikecilkan sebagai ”kelompok orang yang selalu ada di setiap era teknologi yang selalu khawatir atas dampak negatif suatu perubahan besar teknologi”. Bahkan, mereka dilecehkan sebagai kelompok yang ”takut pada kemajuan”.
Penilaian baik buruknya dampak teknologi tergantung dari beberapa kondisi yang ada pada era tersebut dan ini yang akan berdampak ke depan. Poin dasarnya adalah kemampuan semua institusi dan organisasi yang ada untuk melakukan penyesuaian.
Baca juga Beda Idul Fitri Muhammadiyah dan NU Garis Lucu
Tiga sihir
Sebelum membahas kapasitas untuk mengarahkan teknologi, kita bahas dulu beberapa macam gagasan yang menyihir dari teknologi digital/plus AI.
Sihir pertama adalah pandangan bahwa digitalisasi dan AI akan mengefisienkan proses dan selanjutnya menghasilkan pekerjaan-pekerjaan baru. Orang-orang yang berpandangan demikian biasanya melanjutkan dengan usulan agar pemerintah bersama dunia usaha mengembangkan skema-skema baru pelatihan tenaga kerja.
Pelatihan ini dimaksudkan untuk perluasan akses penggunaan teknologi digital. Namun, yang berpandangan demikian lupa bahwa teknologi digital plus AI mempunyai karakter yang sangat berbeda dengan revolusi teknologi lainnya.
Baca juga Jihad Kesantunan Berbahasa Era Demokrasi
Perbedaan pertama adalah bahwa teknologi ini lebih dikembangkan untuk mengefisienkan proses dan mengonsolidasi perusahaan. Teknologi digital bukan dimaksudkan untuk mendampingi kapasitas manusia untuk naik ke karya yang lebih tinggi, melainkan menggantikan apa yang dilakukan manusia.
Artinya, perusahaan-perusahaan akan tidak mau ketinggalan menggunakan teknologi ini sesuai dengan logika dasarnya. Itulah sebabnya, secara konsisten terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di perusahaan. Misalnya, di Amerika Serikat, dari tahun 1970 hingga sekarang, digitalisasi menyebabkan penurunan pekerja dengan keahlian menengah sebesar 15 persen.
Untuk perkembangan terakhir AI, sekitar 300 juta pekerjaan di Eropa dan AS akan bisa diotomatisasikan dengan teknologi chatbot (Diane Coyle, Project Syndicate, 10/4/2023).
Baca juga Kekerasan Pemuda, Cermin Asuhan Keluarga
Jadi, perkembangan digitalisasi plus AI justru tidak mendorong munculnya bidang-bidang pekerjaan baru dengan penyerapan kerja baru yang luas.
Ramifikasi yang ada adalah pemanfaatan teknologi digital plus AI yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Ini artinya menghancurkan basis ekonomi dan daya beli dalam jangka panjang.
Perbedaan lain adalah pengembangan teknologi AI bisa dilakukan dalam ruang yang tertutup tanpa infrastruktur fisik yang luas dan mudah terlihat. Pihak mana pun yang mempunyai sumber daya sangat besar—yang bisa saja kekayaannya berasal dari sumber/cara ilegal—membeli sejumlah ahli terbaik di dunia untuk mengembangkan sistem AI-nya sendiri.
Baca juga Ramadhan dan Kesalehan Negara
Perusahaan-perusahaan besar yang resmi, seperti Microsoft dan Google, bisa melontarkan ke ”pasar” begitu saja karena belum ada norma dan aturan untuk harus melalui seleksi prosedur tertentu untuk melontarkan produksinya.
Padahal, kontrol dalam sistem produksi selalu diperlukan untuk mengenali risiko terjadinya dampak buruk.
Persoalan mendasar yang harus dipikirkan adalah bagaimana teknologi ini berisiko menghasilkan ketimpangan dengan struktur sosial ekonomi baru?
Baca juga Kekerasan Budaya
Perluasan akses digitalisasi tidak begitu saja menyelesaikan masalah, seperti yang sering digagas pemerintah. Persaingan yang tidak sepadan (the winners take all) karena perusahaan bermodal besar akan menggunakan AI untuk menguasai pasar, atau perluasan tenaga prekariat tanpa masa depan pasti sudah sering diangkat.
Selain itu, akan muncul bentuk-bentuk struktur ketimpangan baru. Mari kita bayangkan sebuah contoh jika universitas dan lembaga pendidikan tinggi lainnya memperbolehkan penggunaan chatboat oleh para mahasiswa dan periset dalam suatu kerangka prosedur baru, misalnya untuk mencapai analisis yang jauh lebih bermutu. Prosedur baru ini hanya dapat dipenuhi universitas-universitas yang memiliki sumber daya besar, sementara yang lainnya akan masuk dalam kategori ”recehan”.
Sihir kedua adalah terjadi demokratisasi baru karena penggunaan media sosial yang luas. Juga ada harapan untuk terjadi akuntabilitas lebih besar dengan pengembangan e-government. Namun, penggunaan teknologi ini belum menunjukkan suatu arah baru demokratisasi dan akuntabilitas yang inklusif.
Baca juga Manusia Digital dan Ke(tidak)bebasan
Media sosial hanya menghasilkan informasi dan kemudian tanggapan yang reaksioner, sering emosional, tidak membutuhkan komitmen yang mendalam, dan jauh dari deliberasi. Akibatnya, pemerintah pun cenderung bersikap reaksioner.
Sementara, persoalan terkait e-government adalah hampir tidak adanya partisipasi masyarakat dalam konstruksi normatif di dalam aspek pembuatan sistem. Tambahan pula, penarikan data melalui e-government belum disertai dengan mekanisme solid mengarah pada perbaikan birokrasi.
Sihir ketiga adalah anggapan bahwa individu semakin mudah mendapatkan informasi untuk membuat keputusan-keputusan. Itu benar, tetapi terjadi keterlibatan yang berlebihan pada pencarian melalui digital dan melupakan keterlibatan dan pengembangan komitmen di dunia nyata.
Baca juga Pendidikan Tanggung Jawab Bersama
Data dari WeAreSosial menunjukkan, rata-rata orang Indonesia menggunakan media sosial lebih dari tiga jam sehari. Media sosial digunakan untuk antara lain mengisi waktu luang (58 persen) dan mengetahui apa yang sedang ramai dibicarakan (51 persen).
Bisa dibayangkan waktu yang hilang untuk melakukan interaksi berkualitas, memikirkan peningkatan kapasitas diri dan lingkungan, serta mengikuti kegiatan sebagai bagian dari warga negara yang baik.
Sekarang ini, baik anggota masyarakat maupun para elite sosial dan politik hanya menyukai informasi-informasi praktis dan singkat tentang isu-isu dalam masyarakat. Bisa dibayangkan pikiran apa yang bisa dihasilkan dari model mendapat ”pengetahuan” seperti itu.
Baca juga Ruang Merawat Diri
Retransformasi
Bagaimana mengatasi persoalan-persoalan di atas sebagai suatu bangsa yang tidak ingin tenggelam?
Pertama-tama, harus diangkat visi dan gagasan tentang kompetensi hidup dalam era digital. Bukankah belakangan ini konsep ini seakan tenggelam dalam berbagai persoalan tata kelola negara dan polarisasi sosial melalui media sosial?
Bangsa ini harus merumuskan kembali kecakapan individu, organisasi, dan institusional macam apa yang dibutuhkan negara ini. Sering kali kompetensi harus dikaitkan dalam tiga level itu.
Baca juga Internalisasi Kerukunan di Tengah Keragaman
Jika kita bicara tentang seorang pemimpin publik, ia harus juga kompeten dalam memperbaiki lembaga-lembaga yang ada.
Para pemimpin politik dan pembuat kebijakan setidaknya merasa sangat concern dengan tiga sihir digital di atas. Tindakan yang diambil harus melibatkan pihak yang kompeten.
Dalam suatu terbitan Forum Ekonomi Dunia yang membuat 20 kutipan para ahli tentang harapan dunia pascapandemi, ada satu yang menarik perhatian. Memimpikan kepemimpinan yang dapat bekerja sama dengan ilmu pengetahuan. Ini penting mengingat keadaan dunia yang banyak mengalami perubahan membutuhkan model-model pengelolaan baru.
Baca juga Mencari Celah Kebaikan
Kedua, dalam mengembangkan e-government, pemerintah harus memasukkan elemen kesejahteraan inklusif. Artinya, pengembangan sistem tidak hanya melibatkan ahli digital dan sistem data yang tidak memahami aspek sosial kesejahteraan dan transformasi sosial.
Pemerintah juga harus mendorong berbagai bentuk integrasi sistem. Bukan hanya antarlembaga pemerintah, yang seharusnya memang sudah lama terus diupayakan.
Pemerintah harus mendorong kerja sama baru antarberbagai pelaku ekonomi, membuka ruang kewiraswastaan sosial, dan inisiatif organisasi sosial untuk mengembangkan ketahanan sosial ekonomi.
Baca juga Melawan Rasa Takut
Di tingkat lembaga nonpemerintah, kompetensi baru adalah memperkuat jaringan kerja sama antarorganisasi. Lembaga pendidikan mengembangkan program-program dalam dan luar kurikulum dalam kerangka program/proyek pemecahan masalah sosial.
Dengan cara ini, organisasi masyarakat membuat anak muda kembali ke dunia nyata, dunia yang membutuhkan bangunan moral kontekstual dan tindakan kolektif.Penulis pernah mengusulkan gagasan pengembangan big data sebagai alat membangun kesadaran kolektif dan akuntabilitas pejabat publik. Teknologi sungguh tergantung dari cara kita mengendalikan kekuatan yang memanfaatkannya.
*Artikel ini telah terbit di Kompas.id, edisi Selasa, 16 Mei 2023